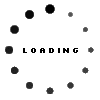Ilham Almujaddidy & A.S. Sudjatna | CRCS | Event Report

Dialog antaragama sebagai upaya penyelesaian konflik bukan hal yang mudah dilakukan. Tidak jarang terjadi, dialog yang dimaksudkan untuk menjembatani perbedaan dan meminimalisasi konflik tidak berjalan sesuai tujuan awal, atau bahkan kontraproduktif dan menimbulkan masalah baru.
Dalam diskusi Forum Umar Kayam, Pusat Kebudayaan Koesnadi Hardjosoemantri (PKKH) UGM, pada Senin 25 Juli 2016, dosen CRCS Dr. Suhadi Cholil membahas persoalan ini. Dalam diskusi bertajuk “Menunda Keyakinan: Refleksi Membangun Pluralisme dari Bawah” itu, pengajar matakuliah Interreligious Dialogue di CRCS ini memberikan identifikasi-identifikasi penyebab dialog gagal mencapai tujuannya.
Pertama, kurangnya pemahaman substantif tentang fungsi dan metode dialog antaragama yang menyaratkan, antara lain, adanya saling percaya. Adanya praduga-praduga negatif terhadap mitra dialog dapat menimbulkan tiadanya saling percaya itu, dan pada gilirannya menjadi hambatan utama bagi efektivitas proses dialog.
Kedua, dialog antaragama yang semestinya menjadi interaksi untuk saling mengakomodasi masing-masing pihak yang terlibat, dalam prosesnya, malah terjebak dalam upaya untuk mendominasi.
Ketiga, dialog antaragama diandaikan sebagai penuntas konflik. Yang jarang dipahami, dialog dalam praksisnya tidak serta merta bisa menyelesaikan konflik. Beberapa konflik, apalagi konflik agama yang melibatkan klaim-klaim teologis yang sulit untuk dijembatani, tidak mudah dimediasi dengan dialog semata, dan karena itu memerlukan alternatif resolusi konflik yang lain.
Dengan menyadari hal-hal yang menghambat dialog antaragama itu, pemahaman yang tepat mengenai fungsi dan metode dialog antaragama bagi para pihak yang terlibat di dalamnya mutlak diperlukan, termasuk mensinergikan pengetahuan teoretis dan praksis.
Yang kerap menjadi problem di lapangan ialah banyak akademisi yang hanya fokus pada persoalan-persoalan teoretis atau teologis semata, namun abai pada ranah praktis. Sementara di sisi lain, ada banyak aktivis yang kurang reflektif secara teoretis maupun teologis, namun begitu aktif di pelbagai aktivitas dan advokasi perdamaian. Ketika kedua belah pihak ini terlibat dalam sebuah dialog, kerap kali muncul kesalahpahaman yang dapat memicu timbulnya permasalahan baru, dan karena itu kontraproduktif.
Hal lain untuk meminimalisasi hambatan dalam dialog antaragama ialah dengan mendudukkan isu teologis secara tepat. Tidak dapat dimungkiri, isu teologis merupakan isu sensitif, dan karena itu, jika tak hati-hati, justru dapat merusak proses dialog itu sendiri. Dalam proses dialog antaragama, isu teologis berada dalam ketegangan antara klaim eksklusifitas dan kehendak untuk menerima adanya keyakinan yang berbeda.
Dalam persoalan yang terakhir ini, Dr. Suhadi tidak mengusulkan untuk membuang eksklusivitas itu. Baginya, eksklusivitas itu sendiri tidak salah dalam dirinya sendiri. Ia akan menjadi masalah ketika tidak diterjemahkan dengan proporsi yang tepat di ruang publik. Banyak dari yang terlibat dalam proses dialog tidak membedakan antara ruang privat untuk ranah teologis dan ruang publik untuk pencarian titik temu guna menyelesaikan konflik. Karena kurangnya pemahaman untuk melokalisir klaim-klaim teologis pada ranah pikiran dan hati, dialog antaragama, alih-alih menjembatani perbedaan, justru rawan menjadi adu klaim teologis.
Merespons isu eksklusivitas teologis dalam dialog antaragama ini, Dr. Suhadi menawarkan gagasan bahwa untuk mengembangkan dialog antaragama yang lebih produktif, perspektif yang terbaik adalah dengan mendahulukan urusan sivik (kewargaan) dan menunda keyakinan. Hal ini tentu tidak berarti keyakinan ditinggalkan. Keyakinan ditunda, tidak dikedepankan, dan baru ditengok kembali ketika dibutuhkan dalam proses dialog.
*Laporan ini ditulis oleh mahasiswa CRCS, dan disunting oleh pengelola website.
Arsip: