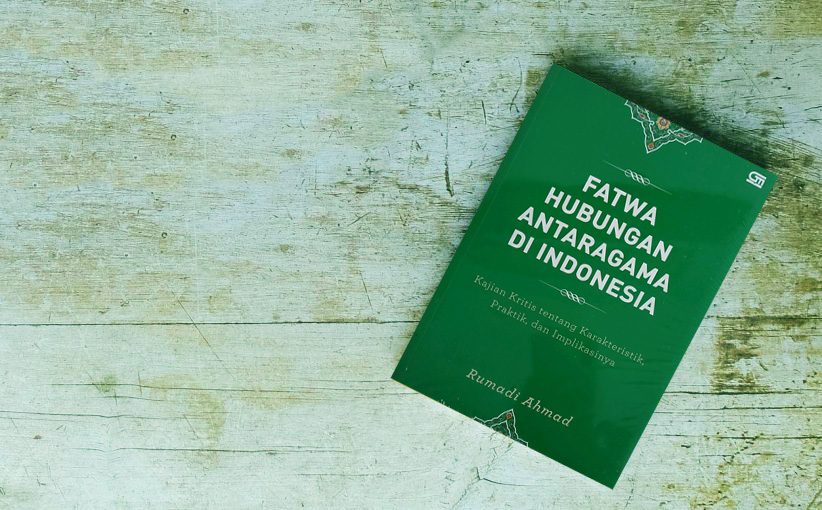
Semangat Eksklusif di Balik Fatwa-Fatwa Hubungan Antaragama
Gedong Maulana Kabir – 4 April 2020
Banyak Muslim di Indonesia yang melandasi cara mereka bergaul dengan pemeluk agama lain berdasarkan pada fatwa-fatwa dari organisasi Islam yang mereka ikuti. Hal ini memang tidak serta merta buruk. Hanya sayangnya, banyak dari fatwa-fatwa itu yang dirumuskan dengan berdasar pada literatur yang ditulis pada Abad Pertengahan, ketika semangat zamannya (Zeitgeist) jauh berbeda dengan semangat zaman kiwari, yang ditandai dengan perjumpaan antaragama yang kian intens dan tak terhindarkan.
Buku Rumadi Ahmad berjudul Fatwa Hubungan Antaragama di Indonesia (2016) mendaftar fatwa-fatwa itu. Ia mengajukan pandangan bahwa banyak dari fatwa-fatwa menyangkut hubungan antaragama itu lahir dilatari oleh motivasi untuk menjaga kemurnian akidah Islam dan membentengi diri dari pengaruh buruk agama lain (h. 273). Alasan demikian tak pelak membuat corak fatwa-fatwa itu cenderung eksklusif, bernada kontestasi, dan kadang antagonistik.
Anatomi fatwa
Buku Rumadi mengompilasi fatwa-fatwa hubungan antaragama dengan merujuk pada buku Ahkam al-Fuqoha: Hasil-Hasil Muktamar dan Permusyawaratan Lainnya (2010), yang menghimpun 536 keputusan dari 36 forum Bahtsul Masail NU; Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama dalam 6 jilid yang menghimpun fatwa-fatwa dari Majelis Tarjih Muhammadiyah; dan Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 (2011) yang mengompilasi keputusan-keputusan dari Komisi Fatwa MUI.
Dari sekian banyak fatwa itu, hanya tentang pernikahan beda agama yang ketiga lembaga tersebut memberikan pandangan yang relatif sama. NU melarang dengan catatan jika perempuan yang dinikahi tersebut bukan kafir kitabi murni. Muhammadiyah memberikan fatwa haram atas pernikahan ini, dan MUI melarang.
Ada pula fatwa yang hanya dibahas oleh dua lembaga saja, misalnya:
- mengucapkan selamat natal. Muhammadiyah menganjurkan untuk tidak melakukan, dan MUI secara tegas melarang umat Islam untuk mengucapkan sekaligus menghadiri perayaan natal;
- soal doa bersama umat agama lain, NU tidak memperbolehkan jika cara dan isinya tidak bertentangan dengan syariat Islam, sedangkan MUI melarang orang Islam mengikuti doa bersama umat agama lain;
- tentang waris beda agama, Muhammadiyah berpandangan seorang muslim ‘tidak berhak’ menuntut warisan dari orang tua non Muslim (begitu juga sebaliknya), sedangkan menurut MUI orang beda agama ‘tidak bisa’ saling mewarisi;
- soal mempelajari kitab dari non-Muslim, menurut NU dilarang kecuali bagi orang yang bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, sedangkan menurut Muhammadiyah hal tersebut boleh jika bermanfaat dan tidak perlu dilakukan jika tidak bermanfaat.
Ada pula fatwa hubungan antaragama yang hanya dikeluarkan oleh satu lembaga saja. Dalam hal ini Muhammadiyah mengeluarkan beberapa fatwa, di antaranya:
- hukum bergaul dengan non-Muslim yang hanya boleh dilakukan dalam konteks kemasyarakatan tetapi tidak untuk konteks peribadatan;
- membolehkkan menerima makanan sejauh tidak diharamkan dalam Islam dan juga membolehkan memberikan maupun menerima donor darah dari non-Muslim;
- soal cara menjawab salam dari non-Muslim dibolehkan dengan kalimat ‘alaikum atau wa ‘alaikum;
- larangan untuk memberikan salam kepada non-Muslim;
- boleh menerima bantuan dari non-Muslim jika pemberian itu murni dan tidak mengikat;
- boleh menyantuni yatim non-Muslim;
- tidak dilarang melayat jenazah non-Muslim;
- adapun soal mendoakan orang tua non-Muslim, menurut Muhammadiyah diperbolehkan jika tidak menyangkut hasil peribadatan, misalnya berdoa semoga Allah memberi petunjuk.
Adapun kasus-kasus yang hanya difatwakan oleh NU adalah:
- Jika ada non-Muslim yang dengan benihnya sendiri menggarap sawah dari Muslim, maka si Muslim tidak wajib memberinya zakat meskipun hasilnya mencapai satu nisab;
- tentang hukum seorang Muslim yang menyewakan rumah untuk orang Majusi yang akhirnya digunakan untuk beribadah, NU menghukumi sah penyewaannnya dan uangnya halal, namun jika dia telah tahu atau menduga bahwa orang Majusi tersebut akan menyembah berhala di rumah itu, maka hukumnya menjadi haram;
- tidak boleh menguburkan orang murtad yang tidak menjadi muallaf lagi di area kuburan orang Islam;
- orang non-Muslim yang di akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah tidak diakui sebagai Muslim karena dia tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah;
- tidak wajib mengimani kitab orang Kristen, Katolik, dan Yahudi sekarang karena mereka telah mengubah kitab tersebut sehingga itu bukan lagi kitab samawi;
- jika ada orang tua Muslim memberikan nasehat, “kamu harus tetap pada agamamu”, pada anaknya yang non-Muslim maka sejauh ucapan tersebut tidak dimaksudkan merelakan kekufuran si anak, maka ucapan tersebut tidak membuat orang tua menjadi kufur. Namun jika ucapan tersebut berarti keridhoan orang tua atas kekufuran si anak, maka orang tua tersebut menjadi kufur;
- tentang orang Muslim yang masuk pada perkumpulan non-Muslim, NU memiliki 3 pandangan yaitu pertama haram jika itu merugikan Islam, kedua baik jika itu menguntungkan Islam, dan ketiga boleh sekiranya itu tidak menguntungkan maupun merugikan Islam;
- soal tafsir dan terjemahan Al-Qur’an yang diproduksi oleh non-Muslim dalam bahasa asing sangat diragukan kebenarannya dan orang awam dilarang membaca dan mengutip terjemahan maupun tafsir seperti itu;
- orang Muslim tidak boleh menguasakan urusan kenegaraan kepada non-Muslim kecuali dalam keadaan darurat, yaitu: pertama bidang yang tidak mampu ditangani sendiri oleh orang Muslim, kedua bidang yang sebenarnya orang Muslim mampu menangani namun ada indikasi kuat akan berkhianat, dan ketiga sejauh penguasaan urusan kenegaraan kepada non-Muslim itu membawa manfaat;
- soal hukum meresmikan tempat ibadah non-Muslim tidak ada jawaban pasti, namun dilarang bergaul terlalu dekat dengan non-Muslim karena hal itu bisa mengantarkan orang pada perasaan cinta, kecenderungan hati, bahkan kerelaan pada kekufuran.
Sedangkan kasus hubungan antaragama yang hanya difatwakan oleh MUI adalah:
- tentang adopsi anak yang hanya boleh dilakukan oleh orang yang seagama dan anak angkat yang tidak bisa mewarisi harta orang tua angkatnya;
- keharaman mengikuti senam yoga yang mengandung ritual, spiritual, meditasi, maupun mantra agama lain; dan
- keharaman pluralisme, liberalisme, dan sekularisme karena dianggap merusak Islam.
Problem motivasi dan rujukan
Fatwa-fatwa di atas menunjukkan adanya kecenderungan ketiga lembaga ini menjadi fleksibel dan inklusif jika hubungan antaragama tidak terkait langsung dengan akidah. Namun jika hubungan ini terkait dengan akidah, secara umum coraknya menjadi cenderung eksklusif (h. 273). Di antara beberapa persoalan yang dibahas dalam fatwa, banyak yang menjadi eksklusif karena persoalan tersebut dihukumi dengan penafsiran akidah yang kaku.
Jika hendak ditelisik kembali, hal itu karena fatwa dari Muhammadiyah (h. 7) dan MUI (h. 168) tidak bisa dilepaskan dari isu Kristenisasi. Keduanya dengan tegas menempatkan agama yang lain (terutama Kristen) sebagai ancaman. Sedangkan di NU (terkadang juga MUI), alasannya bisa jadi karena dalam penetapan fatwa banyak dipengaruhi oleh kitab-kitab dari Abad Pertengahan yang semangat zamannya telah berbeda dari zaman kini.
Bagi Rumadi, kitab-kitab fikih dari berabad-abad lampau tersebut sebagiannya merefleksikan kehidupan sosial politik di awal pertumbuhan dan perkembangan Islam ketika hubungan Muslim dan non-Muslim cenderung bermusuhan (h. 63). Aura menempatkan non-Muslim sebagai warga kelas kedua sangat kental. Selain itu, Al-Qur’an memang memberikan rujukan yang jika dipahami secara tekstual akan menjadi sangat eksklusif, misalnya QS. Al-Baqarah ayat 120 yang kurang lebih artinya: “Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan membiarkanmu, sehingga kamu mengikuti agama mereka.” Padahal jika dilihat konteksnya, ayat ini menjelaskan perpindahan arah kiblat untuk kaum Muslim dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, sedangkan Yahudi tetap mempertahankan arah kiblat yang pertama.
Elemen di luar fatwa
Meski fatwa-fatwanya eksklusif, ia tidak serta merta terterjemahkan ke dalam kehidupan sosial, karena ada beragam elemen di luar fatwa yang menentukan efektivitas fatwa tersebut. Di antara yang bisa disebut adalah, pertama, fatwa tidak memiliki kekuatan mengikat kecuali bagi yang mau mewajibkan dirinya mengikuti fatwa tersebut (mulzim binafsih). Hal ini berbeda dengan hukum positif atau keputusan hakim.
Kedua, lembaga agama acap kali bersifat politis. Hal ini paling terlihat dalam MUI. Beberapa fatwa yang kentara nuansa politisnya adalah pemboleh Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) di era Orde Baru. Ada pula fatwa tentang KB ketika mayoritas ulama di luar MUI tidak sepakat dengan itu. Perlu dicatat bahwa dua fatwa tersebut cenderung menyokong kebijakan pemerintah pada saat itu. Soal lain yang belakangan menjadi polemik adalah soal otoritas label halal yang (hanya bisa) difatwakan oleh MUI.
Ketiga, adanya patronase yang lebih kuat dengan tokoh kharismatik tertentu seperti ustaz/ustazah atau kiai lokal. Meskipun organisasi keagamaan memberikan fatwa yang keras dalam hubungan antaragama, sejauh patronasenya tidak memberikan arahan serupa maka kondisinya akan tetap kondusif. Sebaliknya, meskipun organisasi tidak memberikan fatwa yang keras dalam menjalin relasi antarumat beragama, jika ustaz/ustazah atau kiai patronasenya memberikan ceramah yang keras, hubungan antaragama akan tetap menjadi keras. Hal yang paling fatal adalah jika organisasi dan tokoh keagamaan patronasenya sama-sama memberikan arahan yang keras dalam berelasi antar agama, maka potensi munculnya sikap yang keras dan eksklusif di masyarakat akan makin kuat.
Berbeda dengan rujukan-rujukan tradisional dari forum-forum penghasil fatwa yang tidak mudah diganti, elemen-elemen di luar fatwa itu bisa diupayakan perubahannya melalui aktivisme masyarakat sipil. Dari yang sudah diuraikan di tulisan ini, setidaknya perubahan bisa diupayakan dalam dua level. Pertama di level wacana, yakni dengan mengarusutamakan semangat inklusif dan persaudaraan antarumat beragama, untuk mengikis semangat yang eksklusif dan antagonitik yang melatari kelahiran fatwa. Kedua, di level praktis, dengan mengubah peta patron-patron pemimpin agama yang berpengaruh besar di mata jemaahnya.
_____________________
Gedong Maulana Kabir adalah mahasiswa Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS), Sekolah Pascasarjana UGM, angkatan 2019. Baca tulisan-tulisan Gedong lainnya di sini.

