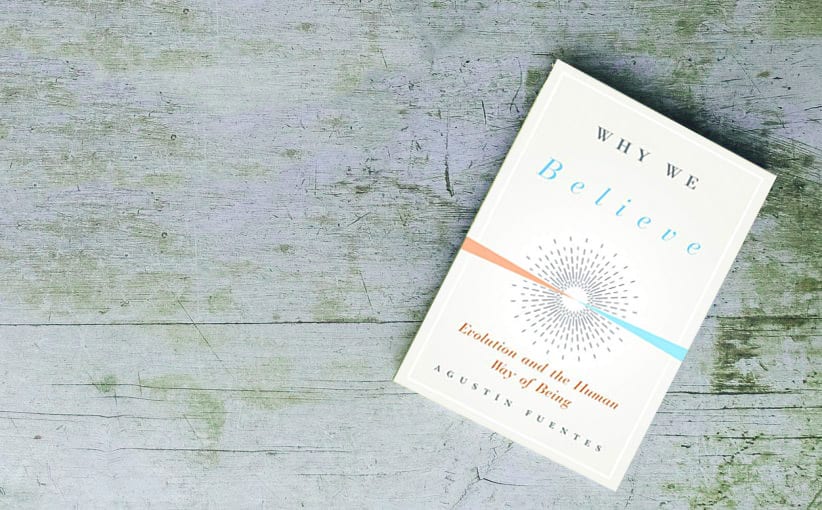
Asal Mula Kepercayaan dalam Penjelasan Evolusioner
Tarmizi Abbas – 24 Juni 2020
Kepercayaan (belief) sering dikaitkan dengan agama. Dalam anggapan umum, manusia yang memiliki kepercayaan berarti secara langsung telah beragama. Padahal, dengan atau tanpa agama, manusia adalah makhluk yang secara alamiah berkepercayaan, dan ini berlaku bukan saja melalui agama, melainkan juga melalui suatu ajaran filsafat, ideologi, atau nilai etis tertentu. Sebelum agama-agama terlembaga, kepercayaanlah yang memungkinkan umat manusia menjawab pertanyaan-pertanyaan eksistensial seperti persoalan hidup dan mati, asal mula alam semesta, hingga apa tujuan keberadaan dunia ini. Pertanyaannya: apa yang melatari lahirnya kepercayaan itu?
Agustín Fuentes, profesor antropologi yang selama puluhan tahun menekuni primatologi di Universitas Notre Dame, berupaya menjawab pertanyaan itu dalam bukunya Why We Believe: Evolution and the Human Way of Being (Yale University Press, 2019). Baginya, kepercayaan dapat dijelaskan secara ilmiah. Pertama, sebagai antropolog, Fuentes mengungkap kepercayaan sebagai sesuatu yang berjangkar langsung pada pengalaman umat manusia dalam memperkuat struktur sosial dan menunjang kehidupan sehari-hari mereka. Kedua, sebagai ilmuan evolusi, Fuentes menelaah apa yang mendasari kemampuan manusia untuk percaya (human capacity to believe) melalui faktor internal dan eksternal seperti gen, ekologi, sejarah, dan tingkah laku.
Buku Fuentes ini menyajikan pembacaan yang apresiatif dalam menjelaskan makna kepercayaan dalam sejarah manusia. Fuentes juga mengambil jarak dari penjelasan reduksionis bahwa kepercayaan hanyalah sekumpulan informasi yang terkandung di dalam DNA manusia akibat interaksi mereka dengan lingkungan sekitar. Ia juga membedakan apa yang dimaksud dengan “memiliki kepercayaan” dan “kapasitas untuk memercayai”. Yang pertama sering diasosiakan dengan agama, sedangkan yang kedua adalah suatu kemampuan alamiah yang melekat pada diri manusia.
Diskontinuitas dalam Evolusi
Alasan mengapa manusia berkepercayaan, bagi Fuentes, ialah karena kita merupakan spesies yang berbeda dan paling aneh kendati memiliki kedekatan secara genetik dengan anggota keluarga besar primata lainnya seperti simpanse, bonobo, gorila, dan orangutan (h. 14). Sejarah evolusi primata yang melahirkan manusia memperlihatkan sebuah diskontinuitas, alih-alih kontinuitas. Jika evolusi manusia berkontinuasi, seharusnya ia memiliki kesamaan perilaku dengan primata lainnya yang memiliki garis keturunan langsung dari cikal-bakal mereka, yakni kera besar (the great ape). Yang terjadi sekitar 8-10 juta tahun lalu justru memperlihatkan ketaksinambungan ketika makhluk Hominin muncul di dataran Afrika. Berbeda dari primata lainnya, Hominin tidak bergelantungan di pohon, memliki bentuk otak yang lebih besar, menghabiskan sebagian besar waktu di tanah, dan berjalan dengan dua kaki (bipedal). Hominin juga memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan sesamanya secara emosional dan gestur tubuh yang lebih baik.
Australopithecus afarensis dinilai merupakan kandidat paling identik dengan genus Homo yang keduanya termasuk sebagai Hominin. Keberadaan afarensis dijumpai sekitar 3-4 juta tahun lalu dan telah menyebar ke bagian utara dan selatan, bahkan di luar Afrika, sedangkan Homo baru muncul dua juta tahun lalu di tempat yang sama dan diyakini sebagai cikal-bakal manusia. Sayangnya, afarensis mengalami kepunahan karena bencana alam serta menjadi mangsa predator, sama halnya dengan Neanderthals dan Heidelbergensis yang berada dalam genus Homo.
Satu-satunya yang tersisa hanyalah Sapiens dari genus Homo yang muncul sekitar 100-400 ribu tahun yang lalu. Sapiens bukan hanya berbeda dari segi fisik, melainkan juga dari cara mereka memandang dunia, menciptakan perkakas dari batu, dan mengontrol api untuk pertama kali. Sekitar 65-40 ribu tahun yang lalu, Sapiens telah mengembangkan simbol dan bahasa untuk berkomunikasi.
Transformasi radikal di dalam sejarah Sapiens ini, bagi Fuentes, diikuti pola kehidupan yang semakin kompleks. Seturut upaya mempertahankan hidup sosial, Sapiens memproduksi suatu pandangan tentang dunia. Hal seperti ini, ujar Fuentes, dipengaruhi oleh niche, sebuah terminologi yang diadopsinya dari seorang ekolog Amerika, G. Evelyn Hutchinson (1903-1991). Niche merupakan kemampuan multidimensional sebuah organisme agar dapat bertahan hidup dengan memanfaatkan interaksi terhadap lingkungannya. Alih-alih statis dan instan, niche manusia berkembang melalui kegagalan dan percobaan terus-menerus. Niche juga secara langsung membedakan manusia dengan para pendahulu mereka sebelumnya, wabilkhusus dalam soal berkolaborasi, mengimajinasikan sesuatu, menciptakan alat bantu, dan memproduksi pengetahuan. Dan yang paling penting, tulis Fuentes, niche manusia adalah asal mula kapasitas manusia untuk percaya.
Dari Niche ke Kultur
Lima belas hingga dua belas ribu tahun lalu adalah titik tumpu untuk memahami lebih dekat kemampuan untuk percaya sebagai bagian esensial yang mendefinisikan manusia. Disebut esensial karena, untuk memahami kehidupan yang kian kompleks, manusia harus memiliki kepercayaan. Penjelasan ini, bagi Fuentes, adalah transformasi dari niche ke kultur, yakni ekosistem yang memfasilitasi seluruh pikiran dan pengalaman manusia ke dalam tindakan yang riil. Jadi, dari yang semula hanya kemampuan untuk membayangkan, menjadi kemampuan untuk menjelaskan dan merepresentasikannya ke dalam benda-benda material. “Kultur memungkinkan manusia untuk meyakini dirinya sebagai pusat alam semesta” (h. 38).
Pengejawantahan kultur dapat disaksikan ketika manusia memahami fenomena kematian, sifat binatang, cuaca, matahari, dan fenomena alamiah lainnya tidak hanya sebagai keniscayaan alam, melainkan juga turut menjelaskan kenapa hal tersebut terjadi. Hal ini turut andil dalam kelahiran peradaban, dari praktik-praktik domestikasi hewan hingga pembangunan kota-kota kecil. Kultur juga menjelaskan keterikatan manusia terhadap tempat-tempat yang mereka bangun sebagai sebuah identitas yang diikat oleh sejarah bersama.
Sebagaimana niche, kultur juga terus berkembang untuk menjawab hajat hidup manusia dengan melahirkan seperangkat nilai yang baru, seperti ideologi dan sistem politik dan ekonomi. Sekali kultur diterapkan dan menjadi konsensus bersama, manusia mengharuskan dirinya untuk membuat komitmen terhadapnya. Mereka yang melanggar dihukum dan dikucilkan dari kelompok inti. Akan tetapi, komitmen ini pada gilirannya juga turut melahirkan ketimpangan kelas ketika segelintir manusia lain mulai mengklaim hak kepemilikan pribadi. Pada situasi yang sama, manusia juga mulai menetapkan komitmen terhadap diferensiasi gender dalam soal mengelola perkebunan, pendidikan, urusan rumah tangga, dan peran sosial lainnya, yang berlangsung ratusan tahun.
Bagaimana dengan Agama?
Agama yang terlembaga dan lahir dari kultur manusia, menurut Fuentes, baru muncul sekitar 4000-8000 tahun lalu. Kemunculan agama ini ditandai oleh penciptaan makna (meaning-making) mengenai Sesuatu yang transenden, seperti Tuhan, dewa, atau entitas ilahiah lainnya yang dipercaya berandil dalam menentukan nasib manusia. Penjelasan Fuentes tentang agama bukanlah sebagaimana umum dipahami sebagai sebuah sistem kepercayaan dengan doktrin yang mengikat, tempat-tempat sakral, dan praktik peribadatan. “Agama” yang dimaksud oleh Fuentes adalah “menjadi religius” (being religious), yang menjadi modus manusia dalam memaknai kehidupannya. Dengan kalimat lain, “menjadi religius” bagi Fuentes berusia lebih purba dari agama sebagai sistem kepercayaan.
Namun demikian, bagi saya, Fuentes tampaknya kurang masuk lebih jauh ketika mengajukan pandangan bahwa untuk memercayai keberadaan entitas ilahiah, seseorang tidak butuh agama sama sekali (h. 58). Pandangan ini benar dalam penjelasannya terkait “kapasitas manusia untuk percaya”, tetapi tidak ketika kita hendak menjelaskan secara lebih terperinci ihwal bagaimana hubungan Yang Ilahi itu dengan dunia, termasuk manusia di dalamnya. Agama-agama sebagai sistem kepercayaan menyediakan seperangkat bahasa untuk menjelaskan hal ihwal yang terakhir ini.
Di dalamnya, teologi-teologi lahir, berikut turunannya seperti praktik peribadatan dan nilai-nilai etis. Sayangnya, buku Fuentes kurang rinci dalam memberikan penjelasan evolusioner dari kelahiran kognisi yang memungkinkan manusia untuk memikirkan bagaimana relasi Yang Ilahi dengan manusia, yang pada gilirannya melahirkan sistem kepercayaan yang mendasari agama-agama terlembaga sampai hari ini.
____________________
Tarmizi “Arief” Abbas adalah mahasiswa Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS), Sekolah Pascasarjana UGM, angkatan 2019. Baca tulisan Arief lainnya di sini.

