
Gus Dur, Papua, dan Kewarganegaraan Bineka
Zulfikar Riza Pohan – 15 September 2019
Ketika menjadi presiden selama kurang lebih 21 bulan (Oktober 1999—Juli 2001), Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menghadapi Indonesia yang sedang terancam disintegrasi. Lepasnya Timor Timur (kini bernama Timor Leste) di masa pemerintahan Habibie turut menyulut gerakan memisahkan diri dari Republik Indonesia di Aceh dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan di Irian Jaya (kini Papua) dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Ditambah adanya konflik komunal etnoreligius di Maluku dan panasnya kontestasi politik di Jakarta, harus diakui bahwa tantangan yang dihadapi Gus Dur saat itu sangat berat, terutama mengingat posisinya sebagai pengemban amanat GBHN 1999-2004 untuk mempertahankan kesatuan wilayah RI.
Kendati berat, di masa pemerintahannya Gus Dur berhasil mempertahankan Aceh dan Papua agar tetap menjadi bagian Indonesia. Tidak sedikit yang mengakui bahwa hal ini merupakan salah satu warisan besar Gus Dur sebagai presiden. Apa pendekatan yang diambil Gus Dur kala itu?
Membahas isu ini, anggota Ombudsman RI dan pendiri Wahid Foundation Dr Ahmad Suaedy membedah buku terbarunya Gus Dur, Islam Nusantara, dan Kewarganegaraan Bineka: Penyelesaian Konflik Aceh dan Papua 1999-2001 di Pendopo Hijau LKiS pada 7 September 2019 di acara Kongkow Bareng Gusdurian Jogja. Buku ini diangkat dari disertasinya di UIN Sunan Kalijaga yang diujikan terbuka pada Mei 2018. Berhubung saat ini isu Papua sedang memanas, tulisan ini ingin meringkas yang disampaikan Dr Suaedy di acara itu ditambah sejumlah informasi dari bukunya, dengan fokus khusus pada Papua.
Negara-sentrisme yang berlebihan
Untuk memahami seberapa signifikan kebijakan Gus Dur pada awal dekade lalu, perlu kita lihat bagaimana pemerintah sebelumnya memperlakukan Papua dengan pendekatan keamanan/militer. Ketika muncul deklarasi kemerdekaan Papua oleh OPM pada 1 Desember 1961 dengan pengibaran bendera Bintang Kejora, Presiden Soekarno memandang hal ini sebagai kemerdekaan negara boneka yang sengaja diciptakan Belanda dan imperialis untuk merongrong Indonesia. Soekarno akhirnya melancarkan Operasi Pembebasan Irian Barat.
Pada 1969 Presiden Soeharto menggelar Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) dengan pemungutan suara dilakukan oleh perwakilan rakyat Papua. Pepera ini hingga kini diperselisihkan legitimasinya karena, setidaknya bagi pendukung kemerdekaan Papua, ia dilakukan di bawah tekanan militer dan tidak dilaksanakan dengan cara “satu orang satu suara” sehingga tak merepresentasikan prinsip “penentuan nasib sendiri”. Di bawah Soeharto jumlah kekayaan Papua yang diambil ke Jakarta amat timpang dibanding tingkat pemberdayaan masyarakat Papua; penyeragaman kebudayaan terjadi (khususnya terkait tanah adat), ditambah dengan kebijakan transmigrasi spontan ratusan ribu orang yang hingga tingkat tertentu meminggirkan masyarakat Papua dan menciptakan pembedaan antara pribumi dan pendatang. Di bawah Soeharto pula jumlah tentara di Papua dari tahun ke tahun bertambah, dan naik drastis seiring pelaksanaan dwifungsi ABRI. Ketika pada 1982-1998 diberlakukan Daerah Operasi Militer (DOM), Papua disesaki aparat militer dan kepolisian, aksi kekerasan meningkat, dan banyak laporan mewartakan terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM yang akut.
Alih-alih meredam, perlakuan negara terhadap Papua dengan pendekatan militeris dan represif itu justru menambah energi bagi gerakan kemerdekaan Papua. Dalam uraian Dr Suaedy, pendekatan pemerintah saat itu cenderung terpusat pada negara (state-centrism), yang mempersepsikan negara semata-mata sebagai “administrator penduduk” dalam bingkai yang teritorialistik seraya mengabaikan hak-hak kewarganegaraan. Dalam cara pandang ini, rakyat hanya dianggap sebagai objek yang kudu melayani negara. Diakui atau tidak, gerakan kemerdekaan Papua memiliki bahan cukup untuk membangun narasi ketertindasan guna mengonstruksi identitas “kebangsaan Papua”.
Mengikuti kajian akademik mengenai pembedaan antara kenegaraan (statehood) dan kebangsaan (nationhood), Dr Suaedy dalam bukunya menguraikan perlakuan negara yang terlalu kuat elemen statehood-nya, sementara pengakuan dan penghargaan terhadap nationhood dari rakyat Papua belum selesai. Idealnya, hubungan kedua hal ini harus setara dan timbal balik. Negara tidak akan wujud tanpa rakyat, dan rakyat terwadahi kebangsaannya dalam lembaga bernama negara. Menurut Dr Suaedy, Gus Dur ingin merestorasi kedua elemen pembentuk negara bangsa (nation-state) ini ke dalam proporsi yang seimbang.

Dialog dalam kewarganegaraan bineka
Pendekatan yang diambil Gus Dur dalam persolaan Papua merentang dari pendekatan personal-dialogis hingga transformasi kelembagaan pemerintahan, yang didasari oleh visi yang disebut Dr Suaedy dengan “kewarganegaraan bineka”. Konsep dari istilah yang dipakai Dr Suaedy ini diinspirasi oleh karya Renato Rosaldo dan Will Kymlicka tentang kewarganegaraan multikultural (multicultural citizenship) yang dalam pengertian Rosaldo (2003) merujuk pada “the right to be different (in terms of race, ethnicity, or native language) with respect to the norms of the dominant national community”. Kewarganegaraan bineka berarti pengakuan dan pemenuhan hak-hak khusus yang berbeda kepada komunitas yang tidak berbagi norma kultural nasional yang dominan. Dalam penjelasan Dr Suaedy, wujud konkret dari visi ini antara lain ialah pengubahan nama Irian Jaya menjadi Papua dan perancangan UU Otonomi Khusus lengkap dengan dana otonomi khusus.
Setelah Soeharto lengser dari takhta, muncul Gerakan Aspirasi Merdeka (Gerasem) pada Juli 1998. Seiring berhasilnya referendum kemerdekaan Timor Timur, gerakan kemerdekaan di Papua makin bersemangat. Salah satu pemimpin Papua yang dihormati, Theys Hiyo Eluay, menyeru rakyat Papua agar mengibarkan bendera Bintang Kejora untuk memperingati “Hari Kemerdekaan Papua” pada 1 Desember 1999.
Belum dua bulan sejak dilantik, Gus Dur segera menangani Papua dengan misi awal mengembalikan rasa percaya Papua terhadap negara, yang menjadi prasyarat jika ingin Papua tak lepas dari Indonesia. Gus Dur menampilkan gestur dengan pesan politik yang mendalam ketika pada 31 Desember 1999 ia menginap di Jayapura untuk keperluan “melihat matahari terbit pada hari pertama milenium kedua di ujung timur provinsi Indonesia”. Gus Dur malam itu menemui pemimpin adat dan agama dan perwakilan masyarakat Papua. Pada waktu itu, kelompok yang pro-otonomi dan pro-kemerdekaan relatif seimbang.
Di penghujung milenium itulah Gus Dur mengumumkan penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua dan memperbolehkan pengibaran bendera Bintang Kejora (yang dianggap simbol separatisme di masa Orde Baru), dengan syarat posisinya di bawah bendera Merah Putih. Sama seperti pembolehan Gus Dur terhadap pengibaran bendera Bulan Bintang berdasar merah (yang merupakan simbol GAM) di Aceh, Gus Dur berpandangan bahwa bendera-bendera ini bisa diakui sebagai simbol ekspresi kultural.
Gus Dur juga melakukan apa yang Dr Suaedy sebut sebagai “membuka ruang kontroversi”. Mobilisisasi massa untuk menyampaikan aspirasi yang tulus, termasuk menyatakan keinginan untuk merdeka (bukan pernyataan resmi kemerdekaan secara sepihak), harus diberi ruang dan aparat keamanan dilarang menggunakan kekerasan. Melalui Keppres 173/1999, Gus Dur melepaskan 72 tahanan politik dan memberikan abolisi terhadap 33 narapidana politik Papua. Sepanjang pemerintahan Gus Dur, dua orang Papua menjadi menteri, yakni Freddy Numberi sebagai Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Manuel Kaisiepo sebagai Menteri Muda Urusan Percepatan Pembangunan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia.
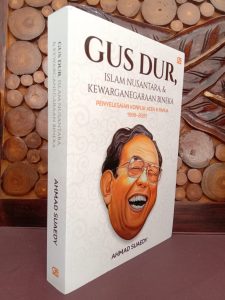
Dalam penyelenggaran Kongres Rakyat Papua (KRP) II untuk membahas pelurusan sejarah Papua dan perjuangan Papua ke depan (yang dipandang banyak orang waktu itu sebagai acara separatisme), Gus Dur memberikan dana satu miliar. Dalam wawancara yang dikutip Suadey, Gus Dur mengatakan, “Saya akan sumbang kalian untuk kongres sebanyak satu miliar. Ini bukan uang saya, tetapi uang Anda sendiri. Maaf, Indonesia baru bisa sumbang segitu. Moga-moga di waktu lain akan bisa mengembalikan lebih banyak kepada masyarakat Papua” (h. 307).
Hanya saja, kebijakan Gus Dur mendapat penolakan yang tak ringan di pemerintahan. Oposisi terhadap Gus Dur menguat di parlemen dan militer. Aparat penegak hukum bahkan kadang bisa bergerak sendiri di luar keinginan presiden. Namun, Gus Dur tetap berupaya keras mendorong lolosnya RUU Otonomi Khusus Papua. Apa yang ingin dilakukan Gus Dur memang belum selesai, tetapi setidaknya ia telah memberikan visi bagaimana menyelesaikan persoalan Papua agar bisa tetap dalam bingkai Republik Indonesia.
Menjelang akhir diskusi bukunya, Dr Suaedy menyampaikan bahwa persoalan Papua harus dikembalikan pada garis UU Otonomi Khusus Papua itu, tentu saja dengan mengedepankan pendekatan dialogis, penjaminan HAM, dan penghentian rasisme. Pengabaian hal-hal ini berarti juga penolakan terhadap visi “kewarganegaraan bineka” yang diperjuangkan Gus Dur.
____________________
Zulfikar Riza Pohan adalah mahasiswa Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS), Sekolah Pascasarjana UGM, angkatan 2019.
Gambar header: Gus Dur menemui masyarakat adat Papua pada 31 Desember 1999. Sumber: Biro Dokumentasi Sekretariat Negara RI.

