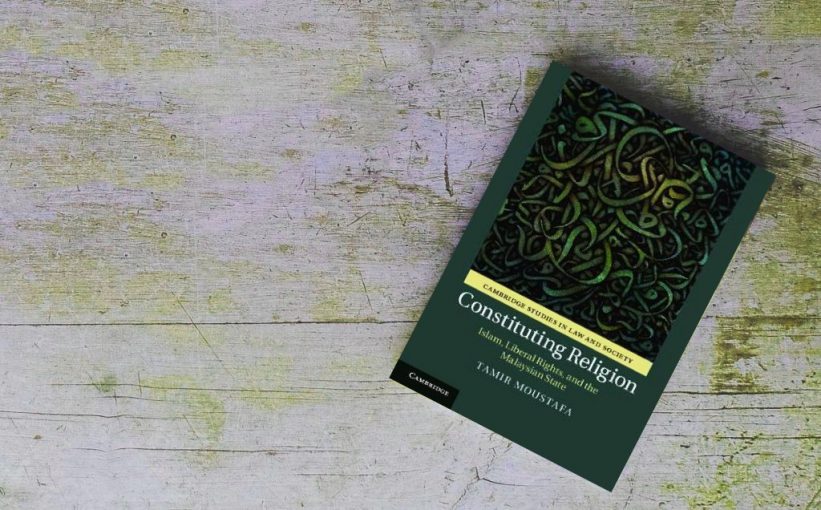
Judisialisasi Agama dan Dampaknya di Malaysia
Fiqh Vredian – 8 Jan 2019
Ketika terjadi benturan antara aspirasi muslim konservatif dan nilai-nilai liberal mengenai kebebasan beragama dan kesetaraan sipil, akar konflik seringkali dipahami berada “di luar sistem hukum”. Di satu sisi, pengadilan dianggap sebagai pelindung hak-hak dasar warga dan benteng negara hukum yang demokratis. Di sisi lain, gerakan Islamis diposisikan sebagai pengguncang independensi hakim dan pengadilan.
Akan tetapi, pemahaman ini cenderung menyederhanakan masalah. Tamir Moustafa, profesor di Simon Fraser Universiy, memberikan pemahaman yang lebih bernuansa dalam buku terbarunya, Constituting Religion: Islam, Liberal Rights, and the Malaysian State (2018). Moustafa melakukan etnografi konstitusi untuk membaca bekerjanya komunitas hukum dan pertarungan mobilisasi agama di dalam dan di luar pengadilan di Malaysia, sebagai pijakan untuk melihat secara lebih luas situasi di negara-negara mayoritas Muslim.
Seperti halnya Malaysia, Indonesia menyaksikan konflik lintas agama yang menajam dalam ranah hukum dan pengadilan dalam dekade terakhir. Sejumlah analis mengaitkannya dengan fenomena “palingan konservatif” (conservative turn). Iklim demokrasi pasca-Reformasi dipahami menjadi lahan kondusif bagi merebaknya konservatisme, seperti penggunaan hukum penodaan agama yang berkali-lipat dibanding masa Orde Baru, penyerangan dan kriminalisasi terhadap minoritas, dan maraknya perda syariah. Penjelasan yang menitikberatkan penetrasi konservatisme ini mengabaikan fakta bahwa, sebagaimana disampaikan Moustofa, alih-alih menyelesaikan sengketa dan memproteksi kebebasan beragama secara konsisten, institusi hukum justru kadang mengintensifkan kontroversi dan memperparah polarisasi ideologis. Menariknya, Moustofa juga memotret kontribusi aktivis dan media liberal yang tanpa disadari turut memperuncing persoalan tersebut. Buku ini senada dengan studi-studi kontemporer agama, hukum, dan politik yang serupa sebelumnya.
Pengadilan Agama
Dalam proses pengadilan isu-isu agama, sering terjadi apa yang disebut Moustofa sebagai “judisialisasi agama” (judicialization of religion), yakni situasi ketika pengadilan kian merasuki ranah persoalan keagamaan dengan memberikan kata putus terhadap isu keagamaan yang diperselisihkan umat Islam sendiri. Pengadilan mengasumsikan otoritas agama berfungsi menentukan bentuk agama yang resmi dan kelayakan posisi suatu agama dalam tatanan hukum dan politik. Artinya, terdapat intervensi negara, dalam konteks ini pengadilan, dalam menyeleksi dan membentuk pandangan dan otoritas keagamaan. Akibatnya, serupa dengan Indonesia, Malaysia mengalami banyak sekali kasus terkait agama yang menyita perhatian dan demonstrasi publik, seperti individu yang tidak diakui haknya untuk berpindah konversi agama, mayat seseorang yang dipisahkan dari istrinya yang dianggap berbeda agama, larangan nikah beda agama, konflik pengasuhan anak beda agama, penyitaan buku dan pembrendelan penerbit yang dianggap menistakan Islam, pelarangan penggunaan nama Allah bagi umat Kristiani, dan kriminalisasi LGBT.
Kasus-kasus di atas tidak dapat serta merta dipahami semata sebagai persoalan pelanggaran kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi, dan masalah agama atau hukum Islam. Ia berakar dari kompleksitas dan dilema hukum dan kelembagaan yang dapat dilacak sejak zaman kolonial. Seperti hukum Belanda di Indonesia, hukum kolonial Inggris di Malaysia merombak secara radikal tradisi Islam dengan adanya kodifikasi hukum Islam. Kodifikasi “hukum Muhammad” sebagai invensi kolonial beserta Pengadilan Syariah dan “hukum Anglo-Muslim” (sebutan hukum Islam yang tersentralisasi dan mengikuti model hukum Barat) di masa kemerdekaan telah mengekang tradisi keragaman pandangan (ikhtilaf) yang vital dalam tradisi dan metodologi fikih (ushul al-fiqh). Dengan berbagai proses sekuler tersebut, hukum Islam (berbeda dengan syariah dan fikih) tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang Islami, religius, saleh, atau berkaitan dengan keyakinan dan praktik keagamaan, tetapi sebagai jenis hukum negara dan proyek kekuasaan negara yang koersif.
Pasal 3 konstitusi Malaysia yang menegaskan bahwa “Islam adalah agama federasi…” sering menjadi landasan mengadili kasus-kasus yang munguntungkan pihak Muslim. Namun pasal ini pada awalnya hanya ditafsirkan secara simbolik dan seremonial. Pasal tersebut baru memiliki konsekuensi hukum pascaamandemen Pasal 121 (1A) konstitusi Malaysia yang memperluas jurisdiksi Pengadilan Syariah sehingga bisa menangani segala macam kasus berkaitan dengan Islam. Pasal 121 (1A) ironisnya secara signifikan meningkatkan kuantitas penanganan dan kontroversi kasus-kasus Islam dan antaragama di pengadilan. Sejumlah ahli hukum dan politisi berhasrat mengobati ketidakpuasan masyarakat Muslim dan melindungi kedaulatan Pengadilan Syariah yang sebelumnya putusannya dapat dibatalkan oleh Pengadilan Sipil Federal. Upaya ini juga diiringi upaya beberapa ahli hukum dan hakim untuk melakukan Islamisasi melalui pengadilan dengan pandangan dasar bahwa Islam mengatur segala macam segi kehidupan manusia, termasuk sosial-politik dan hukum. Pandangan ini menafikkan konteks besar ekspansi sporadis kuasa negara modern saat dan sesudah masa kolonial yang memformat hukum Islam dan otoritas agama menjadi terlembagakan dan terbirokratisasi.
Pengadilan Opini Publik
Meskipun gerakan konservatif menjadi bagian penting dalam analisis, Costituting Religion memiliki jalan cerita yang berbeda dari tren kajian-kajian sebelumnya. Penjelasan yang menitikberatkan intoleransi dan fundamentalisme Islam seringkali menyederhanakan persoalan dengan narasi biner, yang Moustofa sebut dengan rights-versus-rites binary. Narasi ini tampak dalam pertempuran hukum di dalam dan di luar pengadilan. Kelompok konservatif seringkali menuduh sekularisme dan liberalisme bertentangan dan mengancam Islam, sementara kelompok liberal cenderung menempatkan penafsiran keagamaan yang tradisionalis-konservatif semata sebagai biang keladi. Kedua klaim tersebut direproduksi dan digaungkan dengan berbagai strategi untuk tidak hanya memenangkan pengadilan hukum (the court of law), tetapi lebih penting lagi pengadilan opini publik (the court of public opinion).
Pengadilan akhirnya bersaham memunculkan efek-efek radiasi (radiating effects) dalam membentuk kesadaran hukum publik, cuaca politik, dan imajinasi tentang identitas nasional. Litigasi liberal (proses pengadilan) justru dapat menjadi panggung dan ruang mobilisasi yang luas bagi kelompok konservatif untuk menggaungkan klaim mereka dalam membela Islam. Ironisnya, narasi kelompok yang mengadovaksi hak-hak ala liberalisme ini justru menyediakan bahan bakar bagi kelompok Islamis dengan menggunakan narasi rights-versus-rites binary tersebut.
Selain itu, berdasarkan analisis framing dan survei publik Mustofa, media massa yang mengadopsi dan menggaungkan narasi biner itu turut memperkeruh situasi dengan membela segmentasi masing-masing (liberal dan konservatif). Narasi-narasi yang menekankan benturan hukum Islam dan HAM kian menambah amunisi bagi kelompok konservatif bahwa Islam terancam oleh kekuatan Barat. Hal ini bukan bermaksud menyalahkan aktivis liberal, tetapi untuk menunjukkan dampak dari cara pandang biner di atas.
Atmosfir politik makin terpecah belah setelah narasi kelompok konservatif diadopsi dan didukung dalam berbagai khotbah Jumat yang disponsori pemerintah Malaysia. Para politisi oportunis memanfaatkan situasi ini untuk menaikkan reputasi keislaman mereka. Sementara itu, hakim-hakim yang kurang simpatik dengan narasi konservatif sulit keluar dari tekanan sosial-politik dari luar pengadilan. Situasi ini juga menghilangkan ruang akomodasi informal sebelum pengadilan yang dulu sempat tersedia sebagai ruang negosiasi di tengah ketatnya regulasi agama di Malaysia. Reformasi hukum yang sempat diupayakan juga terhenti dengan pelbagai kalkulasi hukum dan politik. Polarisasi ini mengingatkan kita pada pertempuran kelompok liberal dan konservatif dalam kasus UU Penodaan Agama di Indonesia yang sudah empat kali diuji di Mahkamah Konstitusi.
Membangun Kesadaran Hukum Baru?
Dalam situasi yang rumit itu, apakah masih ada harapan? Moustofa tampak memberikan harapannya pada organisasi seperti “Sister in Islam” di Malaysia, sebagai gerakan perempuan Muslim yang masuk ke dalam lapangan diskursif hukum Islam. Moustofa memandang gerakan ini berperan krusial sebagai tandingan produksi pengetahuan yang dimonopoli negara guna membangun kesadaran hukum baru. Sister in Islam melakukan pemberdayaan perempuan, studi hak wanita, advokasi hukum, dan edukasi publik tentang keragaman tafsir dalam hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan isu keadilan gender.
Sayangnya, alternatif Moustofa di atas tidak memuaskan ekspektasi saya yang semula membayangkan tawarannya bisa lebih segar. Gerakan serupa Sister in Islam telah menjamur di dalam dan di luar kampus di Indonesia dan kerap berbenturan dengan kelompok koservatif. Diskusi kompatibilitas Islam dan liberalisme seringkali mengarah pada bagaimana menjadikan HAM sebagai parameter reinterpretasi ajaran untuk menyelamatkan Islam dari ancaman fundamentalisme dan militanisme Islam. Padahal, sebagaimana disadari Moustafa, hukum modern yang dijadikan tulang punggung HAM telah membentuk cara berfikir para militan Muslim tersebut secara tidak sadar dalam membaca sejarah politik Islam dan mengimajinasikan tatanan hukum dan politik Islam.
Beranjak dari wacana tentang Islam dan liberalisme, menarik jika membaca tulisan Saba Mahmood, Is Liberalism’s Only Anwer? (2004) dan Secularism, Hermeneutics and Empire: Politics of Islamic Reformation (2006). Lepas dari nuansa supremasi keislaman, ia membuka kemungkinan arah sebaliknya, yakni bagaimana Islam menjadi sumber untuk mengkritisi prinsip dan kategorisasi sekuler-liberal. Menurutnya, sejarah politik dan tradisi Islam, yang mengandung etika lintas agama, secara selektif dan dengan kacamata baru dapat dijadikan sumber dalam mempertanyakan kontradiksi mesin kuasa negara-modern dan gagasan toleransi ala liberalisme. Gagasan Mahmood itu agaknya bisa melampaui pertanyaan-pertanyaan seperti apakah Islam kompatibel dengan HAM atau bagaimana membuat Islam semakin liberal, dan demikian membuat diskusi mengenai isu ini lebih produktif dan tidak biner.
______________
Fiqh Vredian adalah mahasiswa CRCS angkatan 2017.


Thank you for this thoughtful review. Readers may like to know that the book can be downloaded free of charge through the following link:
https://doi.org/10.1017/9781108539296