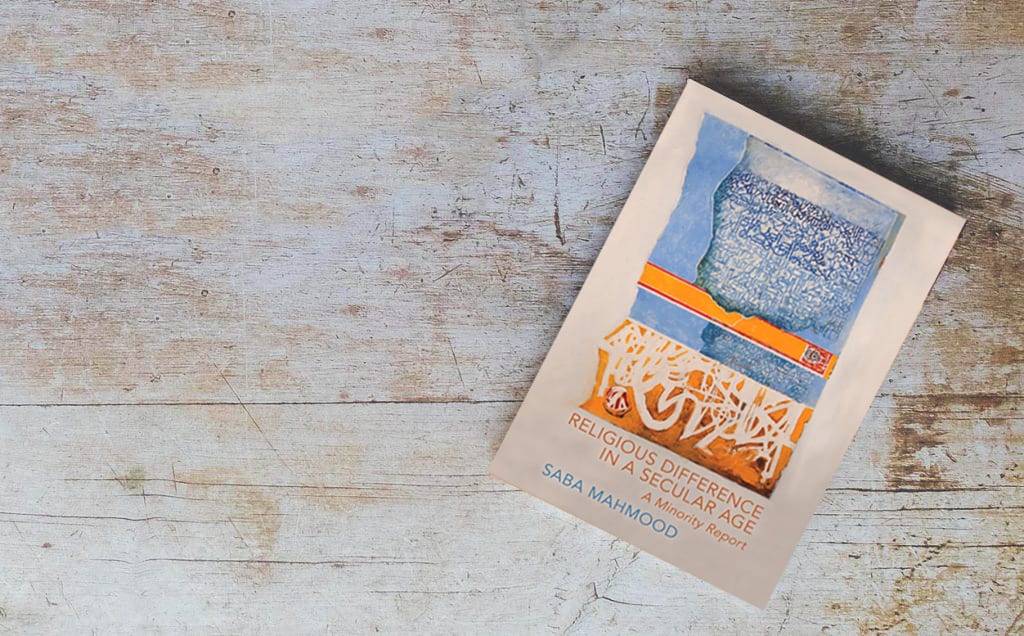
Masalah Sekularisme dan Dampaknya dalam Hubungan Mayoritas-Minoritas
Fiqh Vredian – 22 Agustus 2018
Ketika persekusi terhadap minoritas agama terjadi dan konservatisme agama kian meningkat, sejumlah pihak segera menyimpulkan bahwa akar dari masalah tersebut ialah karena kurangnya sekularisme. Solusi yang ditawarkan akhirnya adalah perlunya menambah dosis sekularisme. Namun pandangan ini kini mendapat kritik dari lingkaran kesarjanaan kontemporer.
Alih-alih mengatasi problem subordinasi minoritas agama, sekularisme justru dapat memperburuk konflik akibat ketimpangan mayoritas-minoritas dan makin menegangkan relasi antaragama betapapun pada mulanya sekularisme dikampanyekan di balik janji kesetaraan sipil dan kebebasan beragama. Argumen ini berada di jantung karya antropologis Saba Mahmood, Religious Difference in A Secular Age: A Minority Report (2015).
Di Indonesia, khalayak ramai acapkali memahami bahwa negara ini bukanlah negara sekuler dan bukan pula negara agama, tetapi negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau negara religius. Narasi ini mewarnai berbagai perdebatan sosial-politik dan hukum di Indonesia, mulai dari perdebatan dasar negara sampai keabsahan hukum penodaan agama. Sementara itu, beberapa pakar lebih terang menyebut Indonesia sebagai negara sekuler, dengan kategorisasi yang khas dan apresiatif. Alfred Stepan, misalnya, melakukan kategorisasi terhadap beragam jenis sekularisme (multiple secularisms) dari berbagai negara dan menempatkan Indonesia bersama Senegal dan India dalam model sekularisme dengan perhormatan terhadap semua agama (respect to all), adanya kerja sama positif (possitive cooperation) antara negara dan agama, dan upaya penghindaran diri dari bias mayoritarianisme (principled distance) sehingga tidak terperangkap menjadi negara teokratis.
Analisis terhadap sekularisme itu, yang memiliki kehendak untuk mengkritik cara pandang yang Eurosentris dan mengapresiasi keragaman cara untuk menjadi sekuler dan modern di negara-negara non-Barat, menurut Saba Mahmood, bermasalah. Karena, betapapun ada kesadaran poskolonial di dalam analisis itu, sekularisme mengandung dilema yang inheren: di satu sisi ia berusaha menghapus hierarki agama yang menjadi warisan masa pramodern, tetapi di sisi lain pada waktu yang sama ia masih mempertahakan ketimpangan antaragama.
Karya Saba Mahmood ini kurang lebih segendang sepenarian dengan karya-karya sebelumnya yang seirama. Setelah karya terkenal Talal Asad, Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity (2003), muncul karya-karya antropologi politik dan sejarah yang serupa, seperti The Politics of the Veil (Joan Wallach Scott, 2010) dan Questioning Secularism: Islam, Sovereignity, and the Rule of Law in Modern Egypt (Hussein Ali Agrama, 2012). Karya-karya ini menginterogasi sekularisme sebagai pengorganisasian ulang kehidupan keagamaan yang justru menempatkan minoritas agama dalam posisi sulit. Sekularisme, yang secara umum dipahami sebagai pemisahan domain otoritas agama dengan politik/hukum atau kian redupnya kehadiran agama di ruang publik, dikritik dari sisi bagaimana negara modern dalam kerangka sekularisme justru kian terlibat dalam regulasi kehidupan keagamaan.
Dua Dimensi
Saba Mahmood menganalisis sekularisme dalam dua dimensi: sekularisme politik (political secularism) dan sekularitas (secularity). Sekularisme politik berarti kuasa negara modern dalam mereorganisasi kehidupan sosial-keagamaan, menetapkan apa dan bagaimana seharusnya agama, termasuk melakukan penyensoran apa konten dan ekspresi keagamaan yang patut dalam kerangka moral-etis tertentu. Adapun sekularitas berarti seperangkat konsep, asumsi, dan watak yang mencirikan masyarakat sekuler yang dapat diraba ketika terjadi kontroversi karya seni atau sastra tertentu yang seringkali memunculkan benturan antara ketabuan agama dan kebebasan berekspresi.
Sekularisme politik dalam analisis Saba Mahmood antara lain tampak dalam kuasa negara dalam mengakui keberadaan atau merekognisi suatu agama dan mengatur atau membatasi kebebasan beragama. Saba melakukan perbandingan yang sangat kontras, antara yurisprudensi Mesir dengan syariah sebagai sumber legislasi utama yang dilegitimasi konstitusi dan negara-negara Eropa-Amerika yang terang menisbati diri mereka sebagai negara sekuler. Seperti aliran kepercayaan di Indonesia yang belum dianggap sebagai “agama” atau diperlakukan setara dengan enam agama yang diakui, Baha’i juga diperlakukan serupa di Mesir yang hanya mengakui tiga agama.
Sistem hukum sekuler tinggalan Prancis di Mesir meniscayakan kodifikasi hukum yang rigid dan tersentral dan memberikan wewenang pada hakim untuk menjadi penafsir syariah yang otoritatif. Konsep sekuler tentang pembagian kebebasan beragama, yakni antara keyakinan privat (forum internum) yang harus bebas dari koersi negara dan ekspresi publik (forum externum) yang dapat dibatasi oleh negara menjadi rasionalisasi hakim Mesir dalam membatasi Baha’i, dengan alasan ketertiban publik (public order).
Pada tahun 2008, Pengadilan Administrasi Mesir memutuskan pengosongan kolom agama bagi penganut Baha’i sembari menyatakan indikasi kesesatan Baha’i yang berakibat pada pelanggaran ketertiban umum berdasarkan syariah. Padahal, di dalam hukum Islam tidak ada konsensus terkait bagaimana dalam memperlakukan pengikut agama non-Abrahamik. Di masa Imperium Utsmani, agama-agama lokal di daerah dudukan, seperti Zoroaster di Persia dan Hindu dan Budha di India, diakui dan dilindungi keselamatan dan kebebasan beragamanya sepanjang membayar pajak khusus (jizyah)—satu hal yang umum dalam konteks integrasi ekonomi imperial pada saat itu dan bukan semata-mata inisiasi Islam.
Saba Mahmood ingin menunjukkan bahwa sekularisme ternyata tidak menghapus bekerjanya eksepsi mayoritarianisme di negara modern-sekuler, baik di Timur Tengah maupun Barat. Seperti di Mesir, meski menjunjung tinggi prinsip netralitas dan imparsialitas, Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Eropa sebenarnya juga terlibat dalam penalaran teologis tertentu. Pengadilan HAM Eropa dalam menangani kasus pelarangan jilbab di Swiss (2001), Turki (2005), dan Prancis (2009) menafsirkan bahwa jilbab adalah penanda identitas agama yang menyimbolkan ketimpangan gender, Islam politis, dan satu bentuk pendakwahan agama, alih-alih sebagai ekspresi keagamaan yang absah.
Pengadilan HAM Eropa dalam kasus-kasus itu berkesimpulan bahwa pelarangan jilbab bukanlah suatu pelanggaran terhadap kebebasan beragama umat Islam, melainkan pembatasan yang absah terhadap manifestasi agama di ruang publik. Menurut Saba, pembedaan keyakinan privat (forum internum) dari ekspresi publik (forum externum) tersebut bisa dirunut dari sejarah Kristen di Eropa. Dengan alasan ketertiban umum dan keniscayaan masyarakat demokratis, Pengadilan HAM Eropa memberi “margin of appreciation” kepada tiga negara tersebut untuk menentukan nilai, simbol, dan praktik yang dianggap essensial bagi identitas nasional masing-masing.
Dengan alasan yang tampak paradoksal, Pengadilan HAM Eropa membolehkan pemasangan salib di kelas sekolah-sekolah negeri di Italia, yang tidak seperti jilbab dianggap sebagai simbol pendakwahan agama di ruang publik, tetapi sebagai simbol “budaya” atau identitas Italia yang dekat dengan pusat Katolik. Seseorang bisa jadi berargumen bahwa contoh-contoh di Mesir dan Eropa tersebut tidak menggambarkan putusan yang adil dan jika kebebasan beragama benar-benar diterapkan, tidak akan ada pembedaan minoritas dan mayoritas. Pandangan ini, menurut Saba, justru menggambarkan paradigma “formalisme hukum” yang melihat implementasi hukum tergantung pada hakim dan institusi hukum tanpa melihat genealogi sosial-politik dari sistem hukum itu sendiri.
Dimensi sekularisme yang kedua, sekularitas, tampak dari kontroversi seputar publikasi karya-karya seperti novel Satanic Verses dan The Da Vinci Code dan ilustrasi Danish Cartoon dan Charlie Hebdo. Saba Mahmood mengkaji novel Arab Azazeel yang memicu kemarahan besar Gereja Kristen Ortodoks Mesir, yang pada akhirnya tetap gagal membuat novel tersebut dilarang melalui hukum penodaan agama dan menghambat produksi film novel tersebut. Mereka menyalahkan gambaran novel tersebut tentang kebrutalan Uskup Agung Cyril (yang dihormati sebagai “pilar keimanan”) dalam mempersekusi Yahudi dan kaum pagan, termasuk memerintahkan pembunuhan Hypatia, filsuf dan ilmuwan matematika Yunani yang melegenda.
Perspektif kebebasan berekspresi tidak memadai untuk melihat kompleksitas konflik tersebut. Novel Azazeel sejatinya mendorong pembacaan sekuler tertentu atas sejarah dan melanjutkan superioritas Kristen Barat atas Kristen Ortodoks Timur yang direpresentasikan melalui kekerasan dan irasionalitas. Kisah Hypatia menjadi bukti representasi tersebut, selain mewarnai kritik liberal atas otoritas gereja, simbol pertempuran rasionalitas saintifik versus kegelapan agama, dan kritik feminis terhadap patriarki monoteisme. Padahal, beberapa sejarawan menunjukkan bahwa sebenarnya pembunuhan Hypatia bukan karena paganismenya, tetapi justru lebih bernuansa politis sekuler, yakni karena dukungan politik dan intelektualnya terhadap lawan politik Cyril di Alexandria.
Youssef Zidan, penulis novel tersebut yang seorang Muslim dan menjadi direktur Pusat Manuskrip dan Museum Mesir, mengklaim novel tersebut berdasarkan data sejarah yang akurat dan merupakan karya sastra yang harus diapresiasi. Zidan yang menegaskan objektivitasnya sebenarnya memiliki posisi partisan dalam novel tersebut dengan memberi posisi protagonis pada pandangan Kalsedon (kodrat ganda keilahian dan kemanusian Yesus [dyophysitism]) yang ditolak dan dianggap sesat bagi Kristen Ortodoks Mesir sejak perselisihan Kristologis awal. Zidan bahkan memanfaatkan perselisihan ini untuk meragukan keilahian Yesus dan menginjeksikan keimanan sekuler-humanisnya bahwa agama adalah ciptaan manusia. Uskup Bishoy memberikan argumen historis yang tidak kalah canggih terhadap Kristologi Cyril tentang ketunggalan kodrat keilahian dan kemanusian Yesus (miaphysitism).
Akan tetapi, walaupun kedua pihak saling berusaha meruntuhkan argumen lawannya dalam ruang publik Mesir, menurut Saba Mahmood, keduanya berada dalam “dunia epistemologi yang sama” dengan menggunakan konsep sekuler sejarah dan temporalitas dalam memahami wahyu. Sementara pihak skeptis menggunakan kemungkinan kekeliruan faktual untuk meragukan wahyu dan eksistensi ilahi, pihak apologis berusaha membangun validitas faktual atas peristiwa biblikal (termasuk pencarian “Yesus historis”).
Daripada melihat peristiwa kewahyuan dalam kerangka sakralitas, masyarakat sekuler modern memisahkan mana yang benar-benar terjadi dan mana yang hanya hanya mitos spiritual. Pola pikir dikotomis ini tidak digunakan di masa pramodern dan tumbuh seiring sejarah sekularisasi agama sejak abad 18, termasuk pemisahan kebenaran metafisik (transenden) dan kebenaran empiris (imanen). Sekularitas ini memasok bahan bakar konflik yang tidak bisa dipertemukan (incommensurable divide) antara ketabuan agama dan kebebasan sekuler.
Polarisasi Mayoritas-Minoritas
Sayangnya, Saba Mahmood tidak memberikan jawaban jelas mengenai sejauh mana yurisdiksi hubungan negara dan agama dan bagaimana minoritas agama berhadapan dengan intervensi negara. Saba mendefinisikan persoalan sulit ini sebagai dilema sekularisme politik yang tidak menyediakan cara aksiomatik tertentu sebagai solusi. Membaca pandangannya yang kritis pada kuasa negara yang memiliki posisi sebagai pembawa kewajiban (duty bearer) dalam penegakan HAM, pembaca bisa berasumsi bahwa ia antipati terhadap strategi advokasi dalam sistem hukum kebebasan beragama.
Akan tetapi, Saba sebenarnya menyerukan politik yang tidak memperlakukan negara sebagai wasit dalam hubungan mayoritas-minoritas dan menggolong-golongkan agama. Pemisahan forum internum dan forum externum dalam pengaturan kebebasan agama dan doktrin ketertiban umum memberikan rasionalisasi mayoritarianisme dan kategorisasi tersebut yang, selain membatasi kebebasan beragama, juga dapat merawat ketimpangan dan konflik mayoritas-minoritas dan sewenang-wenang menentukan mana yang religius, mana yang kultural, dan mana aliran yang sesat. Senada dengan Elizabeth S. Hurd, dalam Beyond Religious Freedom, Saba Mahmood mengungkapkan bahwa pengaturan kehidupan keagamaan juga berdampak dalam mengubah identitas agama dan hubungan antaragama sembari menyarankan pelebaran lensa analisis untuk melampaui kebebasan beragama (dan kebebasan berekspresi) dalam membaca konflik.
Saba Mahmood juga tidak ingin kebebasan beragama dimanfaatkan untuk kepentingan geopolitik tertentu. Ia mengkritik politik representasi aktivisme Evangelikal Amerika dan American International Religious Freedom Act (IRFA) yang menggambarkan intoleransi yang inheren dalam Islam dan kebutuhan penyelamatan Kristen Ortodoks Koptik dari persekusi negara mayoritas Muslim. Narasi tunggal kebebasan beragama dan hak minoritas ini tumbuh diiringi penerapan paradigma “good governance” beserta doktrin pasar bebas dan privatisasi sektor publik. Kerumitan masalah yang juga melibatkan pemerintah sekuler dan para elite Kristen Ortodoks Koptik itu sendiri tidak diperhitungkan.
Pembahasan Saba Mahmood terkait sekularisme politik terlihat menutup kemungkinan bentuk agensi yang dapat berkontestasi dalam arena demokrasi untuk mendapatkan hak-hak kewargaan di tengah berbagai problem struktural yang ada. Saba nampak ‘membunuh’ agensi dalam konteks ini, yang berbeda dari buku pertamanya, The Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject (2011), yang menemukan dan membela bentuk agensi gerakan perempuan saleh di Mesir yang tidak disadari feminis liberal dan poskolonial: satu sisi seolah mempertahankan struktur patriarkis, tetapi di sisi lain memiliki gerakan proaktif di ruang publik.
Sembari belajar dari Saba Mahmood terkait kontradiksi sistemik negara sekuler dan upaya memperlebar dan mengevaluasi lensa analisis terhadap hak asasi manusia, penting kiranya untuk terus menggunakan berbagai opsi perjuangan legal dan nonlegal yang tersedia. Kita juga bisa menjelaskan, misalnya, kepada sejumlah kelompok Islam bahwa agenda untuk membuat masyarakat semakin Islami dengan cara mendisiplinkan agama lain melalui negara sejatinya merupakan agenda yang justru bersifat sekuler. Penting untuk memahami bahwa terlalu menghakimi konservatisme agama sebagai akar masalah sembari mengimajinasikan sekularisme sebagai panglima perdamaian, padahal sejatinya ia juga bagian dari masalah, merupakan satu masalah tersendiri.
_________
Fiqh Vredian adalah mahasiswa CRCS angkatan 2017.

