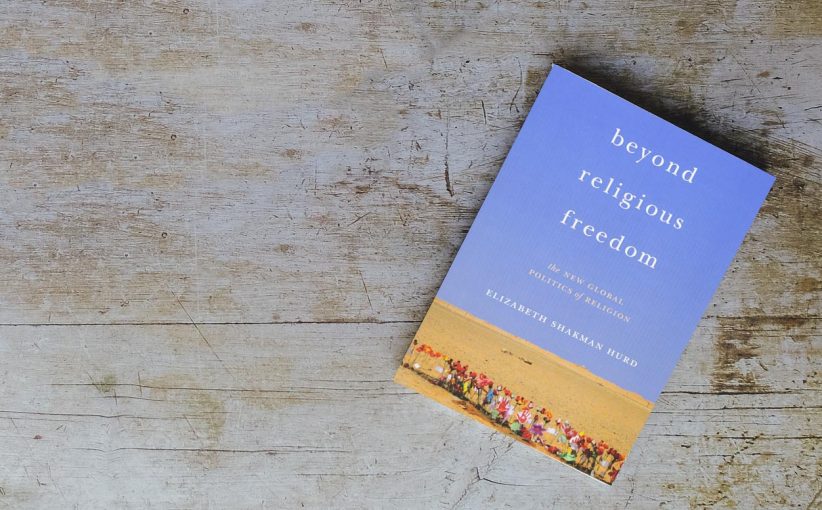
Melampaui Kebebasan Beragama?
Zainal Abidin Bagir – 3 Agustus 2017
~ Tinjauan terhadap buku Elizabeth Shakman Hurd, Beyond Religious Freedom: The New Global Politics of Religion, Princeton & Oxford: Princeton University Press, 2015, xvi+200 halaman.
Dalam sekitar dua dasawarsa terakhir, dengan makin pentingnya posisi agama dalam politik internasional maupun nasional di banyak negara, wacana mengenai Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) berkembang lebih pesat. Di Indonesia, wacana KBB menguat setelah Amandemen UUD 1945 menambahkan satu bab khusus yang komprehensif mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). Advokasi untuk KBB di Indonesia pun turut menguat dalam satu dasawarsa mutakhir ketika makin banyak terjadi kasus “penodaan agama”, rumah ibadah, maupun hak sipil kelompok-kelompok keagamaan tertentu.
Bersamaan dengan itu, wacana kritis atas KBB juga menguat. Meskipun kritik atas KBB, atau HAM secara umum, telah berusia setua ide ini, genre kritik yang baru muncul belakangan ini memiliki beberapa karakter khusus. Genre baru ini diwakili antara lain oleh buku yang dibahas di sini, Beyond Religious Freedom, juga karya-karya dengan judul seperti Politics of Religious Freedom (eds. Winnifred F. Sullivan, Elizabeth S. Hurd, Saba Mahmood, dan Peter G. Danchin, 2015), Problematizing Religious Freedom (Arvind Sharma, 2011), atau The Impossibility of Religious Freedom (Winnifred Sullivan, 2005).
Tiga bentuk “agama”
Buku Elizabeth Shakman Hurd, Beyond Religious Freedom, melihat KBB sebagai bagian dari politik agama global. Sebagai alat analisis utamanya, Hurd membedakan tiga ranah, atau bentuk, agama, yaitu agama yang diregulasi (governed religion), agama yang dikaji para sarjana (expert religion), dan agama sehari-hari yang dipraktikkan oleh kaum beragama (lived religion). Pembedaan ini merupakan pondasi dari argumen Hurd. Satu hal terpenting yang segera muncul dari tipologi ini adalah kesadaran bahwa agama—khususnya dalam dua bentuk yang pertama—merupakan hasil konstruksi. Hurd amat kritis pada yang pertama, dan tampak bersimpati pada yang terakhir.
Governed religion adalah agama sebagaimana dikonstruksi oleh kekuasaan politik, baik di tingkat nasional maupun internasional, atau organisasi-organisasi keagamaan yang memiliki kuasa untuk menentukan apa yang bisa diterima oleh agama tersebut. Salah satu contoh penting yang dibahas Hurd adalah kecenderungan global untuk mengampanyekan KBB dan toleransi antaragama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan beberapa negara Eropa. Hurd melihat, upaya ini berangkat dari suatu asumsi tertentu mengenai apa itu “agama”. Dengan ini, KBB bukan hanya melindungi umat beragama, tapi mengkonstruksi objek yang ingin dilindungi itu, dengan memprioritaskan agama sebagai identitas utama mereka. Dengan kata lain, ia mendefinisikan cakupan agama (utamanya agama-agama dunia yang mapan, dan bentuk-bentuk keagamaan lain sebagai “non-agama”, karenanya tak masuk dalam cakupan perlindungan KBB) serta karakteristik utamanya (yaitu kepercayaan atau belief, bukan praktik keagamaan). Dengan demikian, KBB bukanlah sesuatu ideal universal yang menjamin ruang bebas bagi seluruh agama dari sudut pandang yang netral, namun merupakan suatu bentuk konstruksi agama, dengan banyak konsekuensinya.
Expert religion memenuhi kebutuhan akan pengetahuan untuk memahami apa itu agama, yang kini berperan makin penting dalam politik, dan sesungguhnya ia juga mengkonstruksi agama, bukan sekadar mempelajari dan menjaga jarak darinya. Kedua bentuk agama di atas mendefinisikan atau mengkonstruksikan agama—maka pertanyaannya adalah: siapa yang berkepentingan untuk mendefinisikan, dan untuk apa? Lived religion tak bisa dan tak perlu didefinisikan, bahkan cenderung menghindari definisi. Ia memiliki lebih banyak ragam dan lebih cair, karena ia adalah apa yang dilakukan dalam praktik keagamaan sehari-hari oleh para pemeluk agama.
Konstruksi “agama” dalam KBB
Bab 2 sampai 5 dari buku Hurd menampilkan studi banyak kasus untuk mengajukan beberapa kritik atas KBB. Salah satunya adalah studi atas persekusi kaum Rohingya di Myanmar. Persoalan ini sesungguhnya melibatkan banyak dimensi, persaingan antarras, politik, dan ekonomi yang semua memiliki sejarah panjang. Tapi analisisnya menjadi miskin ketika kasus ini dibingkai terutama sebagai isu agama, dengan solusi berupa pemulihan KBB. Bukan hanya menyederhanakan kompleksitas rangkaian sebab-akibat, perhatian terlalu besar pada faktor agama sebagai penanda identitas kaum Rohingya justru menjadikan kasus ini lebih rumit. Dan sesungguhnya ini juga berarti menerima narasi kaum Buddhis garis keras, yang sengaja mempertegas perbedaan keagamaan Islam dan Buddha sebagai basis dari praktik yang mendiskriminasikan Rohingya. Nyatanya hubungan kedua kelompok agama itu baik-baik saja di tempat lain. Penggunaan kategori “agama” dalam argumen hak KBB perlu dilampaui untuk membuka wilayah analitik yang lebih luas, dan kemungkinan menawarkan solusi yang lebih tepat pula.
Bandingkan kasus ini dengan kasus komunitas Syiah di Sampang yang terusir dari kampung halamannya sejak tahun 2012. Benarkah ini adalah kasus Sunni-Syiah, karena nyatanya di banyak tempat lain kedua kelompok ini mampu berhubungan dengan baik? Dengan menandai korban sebagai “Syiah”, yang dipertegas di sini adalah dimensi perbedaan keagamaannya. Narasi bahwa ini adalah konflik Sunni-Syiah adalah persis upaya pembingkaian kelompok yang mengusir kaum Syiah itu, untuk menjadi justifikasi teologis tindakan mereka. Argumen KBB, ironisnya, kerap menggunakan narasi yang sama: penegasan adanya perbedaan agama, untuk mengajukan tuntutan bahwa kelompok agama minoritas itu mesti dipulihkan hak kewarganegaraannya yang setara. Lebih jauh, memberikan signifikansi terlalu besar pada identitas keagamaan mungkin berarti mengabaikan beragam faktor lain yang lebih signifikan.
Contoh menarik lain adalah komunitas K’iche yang menentang proyek pertambangan dan hidroelektrik di Guatemala. Karena penentangan itu, mereka mengalami diskriminasi, kekerasan dan pelanggaran hak ulayat mereka. Pelanggaran itu, yang dilakukan polisi dan negara maupun perusahaan, sesungguhnya adalah pelanggaran atas hak beragama mereka, namun tak pernah tercatat dalam laporan-laporan KBB internasional. Ini karena mereka dianggap tidak beragama dan pelanggaran itu tidak menyangkut hak atas kepercayaan mereka, sementara KBB terutama memperhatikan kepercayaan (belief) yang sifatnya doktrinal, bukan praktik. Bagi Hurd, ini menunjukkan sempitnya ide mengenai “agama” dalam KBB.
Sebagian orang akan berkeberatan terhadap gambaran Hurd di atas, karena tampaknya terlalu menyederhanakan penalaran advokat KBB. Namun Hurd menunjukkan beberapa contoh betapa dalam sebagian lingkaran kebijakan AS, KBB memang telah menjadi alat politik (misalnya terkait kasus Rohingya, minoritas Kristen Koptik di Mesir, atau kasus Suriah), dan kerap terlepas dari realitas di lapangan, sehingga alih-alih membantu, malah memperumit masalah.
Memperluas lensa analisis
Tampak di sini bahwa kritik Hurd sebetulnya tidak semata-mata mengenai KBB sebagai standar legal perlindungan umat beragama, tapi lebih dalam lagi, yaitu pada setiap upaya mengelola (governing) agama dan pada penggunaan kategori “agama” sebagai alat analisis. Yang menjadi perhatian utamanya adalah kemungkinan membangun suatu proyek politik alternatif untuk membela kelompok-kelompok yang terpinggirkan itu. Karena itu, sekadar memperluas definisi agama bukanlah solusi. “Mereka yang tertarik untuk berpikir kritis dan historis mengenai politik HAM internasional seharusnya tidak mereproduksi pembedaan-pembedaan dan wacana normatif tersebut, yang justru perlu diinterogasi.” (h. 63)
Di sini penting juga dilihat bahwa sementara Hurd mengkritik KBB sebagai suatu bentuk pengaturan agama (religious governance), jelas pula bahwa banyak negara mengatur (dan mengkonstruksi) agama secara lebih problematis. Pengaturan agama di Indonesia, misalnya, secara sistematis mendiskriminasikan kelompok-kelompok agama yang tak tercakup dalam definisi negara tentang apa itu agama.
Buku yang ditulis Samsul Maarif, Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama Indonesia (CRCS 2017) lebih jauh menunjukkan betapa ketika kelompok-kelompok tersebut dikategorikan sebagai “budaya”, mereka memiliki nasib yang lebih baik; sebagai “adat”, hak ulayatnya makin mendapatkan pengakuan. Namun sebagai komunitas “agama” mereka terus terdiskriminasi, dengan konsekuensi tak terpenuhinya hak-hak sipil mereka, misalnya terkait hak untuk pendidikan dan pekerjaan. Di satu segi ini memperkuat kritik Hurd atas kategori “agama”, namun di sisi lain ini juga menunjukkan bahwa di negara seperti Indonesia, kategori ini, karena akar historis-politis yang dalam, sulit dihindari, dan karenanya hak keagamaan mereka pun menjadi persoalan tersendiri. Rekognisi tidak lengkap tanpa rekognisi agama. Dalam hal ini, KBB internasional, yang terus memperluas cakupan “agama”, dan mengikat Indonesia untuk mematuhinya, dapat membantu mendorong perluasan rekognisi kelompok-kelompok itu.
Kritik lain yang bisa diajukan terhadap Hurd adalah bahwa tampaknya dalam banyak hal kritik kerasnya pada rezim KBB didasarkan pada politisasi KBB oleh negara-negara besar, khususnya Amerika. Meskipun Hurd menyampaikan bahwa ia tak berusaha mendelegitimasi KBB sebagai alat advokasi kelompok-kelompok rentan, ia tak selalu sensitif dengan peluang yang dibuka oleh KBB untuk memperbaiki situasi di banyak negara. Kembali menggunakan contoh agama leluhur di Indonesia, upaya yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi hanya mungkin dilakukan saat ini setelah HAM, termasuk KBB, mendapatkan pendasaran yang lebih kuat pasca-Reformasi 1998.
Mempertimbangkan bahwa argumen KBB dapat problematis dalam beberapa hal namun memiliki potensi perluasan rekognisi dalam hal-hal lain, penting ada posisi yang lebih bernuansa, tak sekadar menolak atau menerima. Sementara pengaturan agama sulit dihindari, karya Hurd ini menjadi konstruktif jika dilihat bukan sebagai upaya mendelegitimasi atau memberikan alternatif atas KBB—karena ia memang tak menawarkan itu. Yang penting adalah secara teliti mengidentifikasi ruang-ruang di mana KBB dapat memberdayakan dan juga ruang-ruang di mana kita mesti memperluas analisis.
Hurd mungkin tak bersepakat dengan kesimpulan ini, karena di banyak tempat ia tampak seperti ingin mendelegitimasi KBB. Namun setidaknya upayanya memproblematisasi KBB mengingatkan kita bahwa sementara KBB adalah angin segar di negara yang sedang mengalami demokratisasi seperti Indonesia, upaya membela kelompok yang rentan perlu terbuka pada bingkai normatif yang lebih luas.

