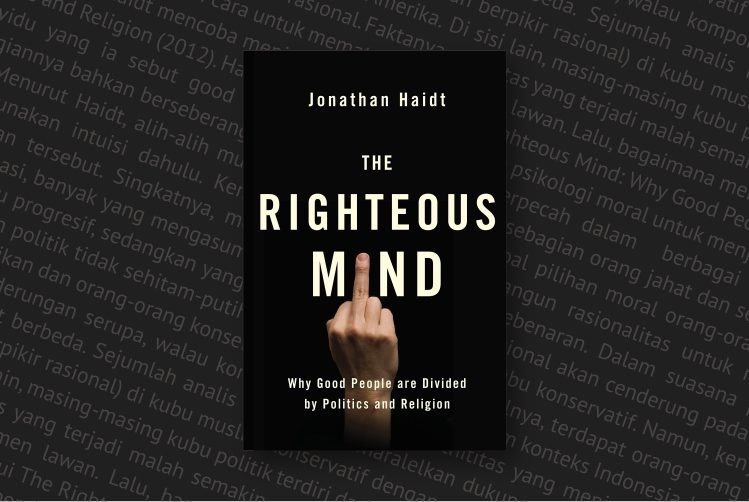
Menggugat Rasionalitas, Mengakali Intuisi
Fany N. R. Hakim –29 November 2021
Mengapa orang-orang “rasional” terbelah soal politik dan agama? Benarkah mereka rasional?
Dalam suasana politik yang terpolarisasi, banyak yang mengasumsikan bahwa orang-orang rasional akan cenderung pada kubu yang liberal atau progresif, sedangkan yang emosional akan berada di kubu konservatif. Namun, kenyataannya pembelahan politik tidak sehitam-putih itu. Di Amerika Serikat, misalnya, terdapat orang-orang liberal di kubu Partai Republik dan orang-orang konservatif di kubu Partai Demokrat. Data National Publik Radio (NPR) pada Pemilu AS 2020 silam menunjukan bahwa sekitar 61% umat Kristen mendukung Trump dan 64% pemeluk agama minoritas mendukung Biden, terlepas dari latar belakang etnisitas mereka. Artinya jumlah masyarakat yang menentang “asumsi umum” ini cukup signifikan.
Dalam konteks Indonesia, belakangan ini terjadi kecenderungan serupa, walau komponen agama atau etnititas yang menjadi dasar pembelahan politik tersebut berbeda. Sejumlah analis misalnya memaralelkan dukungan beberapa intelektual (yang diasumsikan berpikir rasional) di kubu muslim konservatif dengan orang-orang liberal di kubu Partai Republik. Di sisi lain, masing-masing kubu politik juga terdiri dari para intelektual yang punya argumen rasional. Faktanya, polaritas yang terjadi malah semakin meruncing karena tiap kubu justru mencari cara untuk mematahkan argumen lawan.
Lalu, bagaimana menjelaskan fenomena ini?
Jonathan Haidt mencoba menjawabnya melalui The Righteous Mind: Why Good People are Divided by Politics and Religion (2012). Haidt menggunakan pendekatan psikologi moral untuk menjelaskan mengapa individu yang ia sebut good people ‘orang-orang baik’ terpecah dalam berbagai kelompok, yang sebagiannya bahkan berseberangan. Tentu saja, bukan karena sebagian orang jahat dan sebagian lainnya baik. Menurut Haidt, alih-alih murni pertimbangan rasional, soal pilihan moral orang-orang cenderung menggunakan intuisi dahulu. Kemudian, mereka baru membangun rasionalitas untuk menjustifikasi keputusan tersebut. Singkatnya, mencari pembenaran bukan kebenaran.
Intuisi dan Pertimbangan Moral
Di bagian pertama bukunya, Haidt mengajak kita menelusuri dari mana dan apa itu moralitas. Setelah menggali berbagai penelitian antropologi dan psikologi evolusioner, Haidt menggarisbawahi bahwa masing-masing tradisi punya penjelasan berbeda, dan bahkan bertentangan, tentang apa itu moralitas. Karenanya, persoalan moralitas tak jarang melibatkan ketegangan dalam kelompok maupun kompetisi antarkelompok (h. 30). Batasan moral tiap indiviu akan berbeda bergantung pada pertimbangan moral yang dapat mereka rasionalisasi. Dengan kata lain, kemampuan kognitif menjadi hal yang cukup vital bagi seseorang untuk menentukan standar moralnya. Di bagian ini, Haidt banyak merujuk pada Charles Darwin untuk mendukung argumennya mengenai psikologi evolusioner. Bagi Darwin, seperangkat moralitas merupakan hal alami dan sifat bawaan sebagai bagian dari adaptasi evolusioner manusia. Ia menguraikan bagaimana evolusi bentuk dan kapasitas otak manusia memengaruhi proses kognitifnya sehingga mampu melakukan penilaian moral. Moralitas inilah yang membuat manusia bisa bekerja sama secara efektif.
Selanjutnya, Haidt menggunakan metafora gajah untuk mengilustrasikan bagaimana kecenderungan moral seseorang bekerja. Gajah dijadikannya sebagai tamsil bagi intuisi manusia, sementara si penunggang merupakan rasionalitasnya. Banyak orang berpikir bahwa gajah dikendalikan oleh penunggangnya. Akan tetapi, bagi Haidt, gajah adalah penunjuk jalan bagi penunggangnya. Jika sang gajah sudah memutuskan ke mana ia berjalan, si penunggang sebenarnya tidak cukup kuasa untuk menentukan arah mereka berjalan. Maka dari itu, dengan bersandar pada penalaran moral ala David Hume, Haidt menyimpulkan tesis pertamanya: intuisi dahulu, penalaran strategis kemudian. Dari sini ia mengajukan pandangan bahwa keberpihakan politik seseorang lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan moral yang bersifat intuitif. Karenanya, bagi Haidt, satu-satunya cara memengaruhi pemikiran seseorang bukanlah dengan argumen balik, melainkan melalui intuisi (hlm.57).
Di bagian selanjutnya, Haidt mengajukan tesisnya yang kedua: moralitas lebih dari sekadar (pertimbangan) soal ancaman bahaya dan keadilan. Haidt menjustifikasi tesis ini melalui pemikiran John Stuart Mill, filsuf utilitarian yang melihat bagaimana faktor-faktor material memengaruhi terbentuknya moralitas di masyarakat. Haidt mengilustrasikan landasan moral laiknya reseptor pengecap dalam lidah. Parabel ini cukup cerdas. Haidt mengibaratkan cara kerja moralitas kita seperti lidah dan rasa makanan. Jika kita mencicipnya dan itu terasa enak, kita akan menerimanya. Pun sebaliknya, kita cenderung menolak jika hal tersebut terasa kurang pas dengan selera kita.
Menurut Haidt, ada enam reseptor moral yaitu pemeliharaan, keadilan, kesetiaan, kekuasaan, kesucian, dan kebebasan. Masyarakat sekuler yang berpandangan liberal dan utilitarian, menurut Haidt hanya menggunakan dua reseptor: pemeliharaan dan keadilan sebagai landasan moralnya. Sementara kelompok konservatif menggunakan keenam reseptor. Dengan kata lain, pertimbangan moral yang digunakan oleh kelompok konservatif jauh lebih kompleks.
Kecenderungan Berkelompok
Tesis ketiga Haidt merupakan bagian paling krusial dalam membaca pembelahan politik berdasarkan agama. Haidt mengajukan pandangan bahwa masyarakat memiliki kecenderungan untuk berkelompok (groupist). Sikap ini pada gilirannya menimbulkan kompetisi antarkelompok. Dalam satu kelompok yang sama, bisa jadi ada ketegangan antarindividu. Namun, karena terikat standar moralitas yang sama dan rivalitas dengan kelompok lain, kompetisi individu ini bisa dipendam sementara demi kompetisi dengan kelompok lain. Haidt mengemukakan, “manusia membangun komunitas moral dari norma, institusi, dan tuhan yang sama, yang bahkan di abad ke-21, mereka [masih] berperang, membunuh, dan mati untuk mempertahankannya”(h. 262).
Berlandaskan pada kajian biologi evolusioner tentang mekanisme adaptasi organisme, Haidt berkesimpulan, “moralitas itu mengikat sekaligus membutakan.” Setiap kelompok cenderung membentuk kohesi karena dasar-dasar logika yang serupa. Ia memakai analogi sarang lebah: kesetiakawanan hanya berlaku pada lebah dari satu sarang yang sama. Sementara itu, moralitas yang membutakan merupakan gambaran bagaimana altruisme dalam diri manusia bersifat sempit dan strategis—tujuan utamanya demi kepentingan diri dan kelompok.
Dalam pembacaannya terhadap fenomena keagamaan, Haidt banyak mengamini pandangan Durkheimian dalam melihat agama sebagai fakta sosial. Ketika mengambil distingsi Durkheim akan ranah sakral dan ranah profan dalam agama, Haidt berpendapat bahwa gagasan tentang yang sakral meningkatkan keeratan dan kohesi dalam kelompok serta ketundukan terhadap pemimpin kelompok. Di bagian ini, Haidt mengkritik kampanye gerakan ateisme baru ala Richard Dawkins dan Daniel Dennet. Menurutnya, ateisme Dennet dan Dawkins itu tidak akan membawa kelompok mereka ke mana-mana karena tiadanya pengikat kelompok. Agama, menurut Haidt, memiliki simbol-simbol (sakral) yang mempersatukan umatnya dan karena itu lebih solid ketika berkompetisi dalam politik.
Yang Tercecer dari Tesis Haidt
Sebagai professor di bidang psikologi sosial yang berfokus pada topik etika dan sosiologi kebudayaan, Haidt dengan tekun menjahit pemikiran berbagai akademisi dan filsuf lintas bidang lalu mengartikulasikan tesis-tesisnya dalam berbagai metafora. Menurut Haidt, pendekatan psikologis yang mempelajari manusia pada tingkat individu dapat melengkapi kajian ilmu sosial lain. Belum banyak diskursus politik dan agama melalui pendekatan psikologi moral yang melihat pada kasus-kasus individu secara akumulatif. Padahal, politik merupakan sebuah strategi untuk memengaruhi massa yang umumnya menggunakan pendekatan emosional tinimbang rasional dan tak jarang memanfaatkan simbol-simbol moral keagamaan.
Dalam konteks Indonesia, tesis Haidt bisa digunakan untuk menjelaskan bagaimana hoaks, terutama tentang lawan politik dan agama, begitu cepat tersebar. Dalam paradigma Haidt, masyarakat cenderung bersifat implusif dan abai terhadap nalar yang strategis. Landasan moral yang beragam dan condong loyal terhadap kelompoknya juga turut mengekskalasi penyebaran hoaks tersebut. Pada akhirnya, lahirlah para intelektual “hipokrit” yang begitu membabi buta membela kelompoknya.
Akan tetapi, banyak celah yang perlu dikritisi dalam tesis-tesis Haidt tersebut. Meskipun pendekatan psikologi moral dan evolusioner dalam melihat fenomena politik ini menarik dan baru, agaknya Haidt banyak melakukan simplifikasi pada tesis-tesisnya. Pertama, mengenai intuisi yang mendahului rasionalitas. Dengan menopangkan diri pada teori evolusioner dan cara kerja otak manusia, tesis Haidt ini kurang memperhitungkan faktor sosio-kultural yang juga menentukan kecenderungan intuitif maupun rasionalitas manusia. Kedua, mengenai moralitas yang cenderung mengikat sekaligus membutakan. Haidt terlihat mengabaikan bahwa terdapat kelompok-kelompok dengan “landasan moral yang berbeda” tetap melakukan kerja sama dan saling membantu dalam membangun peradaban. Ia beranggapan bahwa setiap orang dalam kelompok—agama misalnya, hanya fokus pada kepentingan golongannya. Dalam hal ini, Haidt cenderung sinis dengan melihat agama dari satu sisi, yaitu sisi negatif yang menunjukkan bahwa agama hanya bermuara pada kekuasaan. Padahal, jika naluri manusia untuk berkelompok dan loyal terhadap kelompoknya adalah sebuah keniscayaan, dialog antaragama ini bisa dilihat sebagai upaya untuk memperluas “batas kelompok” tersebut, memperluas apa yang digambarkan Haidt sebagai sarang lebah.
The Righteous Mind: Why Good People are Divided by Politics and Religion
Jonathan Haidt
Vintage, 2012. 528 hlm.
ISBN 978-0307455772
______________________
Fany N. R. Hakim adalah Mahasiswa Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS), Sekolah Pascasarjana UGM, angkatan 2020. Baca tulisan Fany lainnya di sini.

