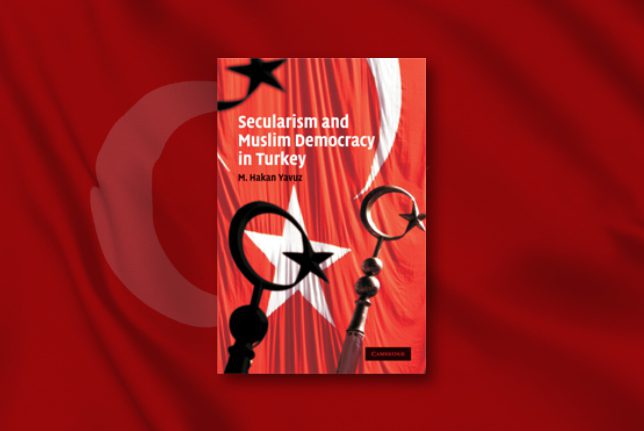
Pos-Islamisme, Borjuasi Muslim, dan Sekularisme di Turki
Imam Sopyan–27 November 2021
Ketika Samuel Huntington memublikasikan Clash of Civilization? (1993), banyak akademisi dan publik internasional yang menarik kesimpulan bahwa karakter Islam tidak cocok dengan demokrasi liberal. Buku Secularism and Muslim Democracy in Turkey, karya M. Hakan Yavuz ini secara eksplisit menolak tesis Huntington tersebut. Melalui investigasi terhadap “gerakan politik yang terinspirasi Islam” dalam konteks politik domestik Turki, Yavuz menunjukkan bahwa gerakan Islam politik juga kompatibel dengan demokrasi liberal. Yavuz mengajukan Adalet ve Kalkınma Partis (AKP) atau Partai Keadilan dan Pembangunan sebagai model partai pos-islamisme yang mampu memainkan peran penting dalam situasi demokrasi liberal. Eksistensi AKP bahkan mampu mengusik kemapanan sekularisme ala Kemal Attaturk yang bertahan puluhan tahun di Turki.
Dalam temuan Yavuz, sebuah partai politik secara tak terhindarkan harus memoderasi pandangan ideologinya untuk mampu bertahan dalam sistem politik kompetitif—yang didasarkan pada partisipasi berbasis regulasi. Yavuz menggarisbawahi setidaknya ada dua aspek penting yang memungkinkan AKP mengonsolidasi kekuatan dan memberikan perubahan dalam struktur sosial politik Turki. Pertama, peran borjuasi Muslim dalam memoderasi aksentuasi ideologi AKP; Kedua, sikap AKP terhadap sekularisme di Turki.
Borjuasi Muslim dan Sekularisme Turki
Menurut Yavuz, kemunculan kelas borjuasi muslim—atau yang ia sebut sebagai borjuasi Anatolia—memainkan peran penting dalam memoderasi gerakan politik Islam di Turki. Para borjuis Anatolia ini berkomitmen terhadap nilai-nilai demokrasi sebagaimana yang terekspresikan dalam dukungan mereka terhadap pertukaran budaya dan proyek intelektual yang baru. Mereka mendanai gerakan-gerakan Islam, baik secara politik maupun intelektual (hlm. 51).
Pembahasan tak kalah penting dari buku ini adalah sikap AKP terhadap sekularisme di Turki. Penting untuk diketahui, pola sekularisme yang berlaku Turki berbeda dengan sekularisme ala Barat. Yavuz mengidentifikasi setidaknya ada dua pola sekularisme yang dijalankan di Barat: pola Anglo-Amerika yang cenderung membebaskan agama dari kontrol negara, dan pola Prancis yang membebaskan ruang publik dan lembaga negara dari pengaruh agama. Di antara dua titik ekstrem ini, terdapat berbagai varian relasi agama dan politik. Dalam pandangan Yavuz, sekularisme ala Turki merupakan model ketiga yang menekankan pada “kontrol negara terhadap institusi dan ekspresi keagamaan”(hlm. 146). Agama—yang dikontrol secara ketat oleh negara—digunakan sebagai modal promosi pembangunan maupun alat legitimasi politik.
Lebih lanjut, Yavuz memaparkan bahwa ada tiga norma praktis sekularisme di Turki, yaitu (1) sekularisme militan Mustafa Kemal yang memosisikan Turki sebagai “anak kandung era Pencerahan Eropa”, (2) sekularisme berbasis Ottomanisme yang menempatkan Turki sebagai “pewaris Dinasti Saljuk dan Ottoman”—tipe sekularisme ini relatif bersahabat dengan Islam, dan (3) sekularisme libertarian sebagai tipe sekularisme yang ingin “membebaskan politik dan perdebatan agama”(158).
Setelah melakukan penelusuran teoretis terhadap sekularisme, Yavuz kemudian menginvestigasi pandangan dan sikap AKP terhadap sekularisme dengan mengajukan beberapa studi kasus, khususnya dalam isu penggunaan kerudung, sekolah imam, dan prostitusi. Para intelektual dan petinggi AKP sadar bahwa sekularisme Turki merupakan sebuah ideologi yang telah mapan dan “tak boleh diganggu”. Dalam konteks ini, Yavuz merujuk pada pidato Erdogan, pimpinan AKP, pada tahun 2006 sebagai sikap kontradiksi partai. Kontradiksi ini terungkap dari penerimaan AKP terhadap konsep sekularisme sebagai jargon dan ideologi politik tunggal di Turki, sementara pada saat yang sama memberikan tafsiran yang jauh berbeda—jika tidak dikatakan sama sekali bertentangan—dengan sekularisme versi Kemalis. AKP seolah-olah menerima sekularisme di hadapan publik tanpa kritik, tapi di internal partai mereka menolak sekularisme model ini (hlm. 159). Menariknya, sikap ini juga disebut Yavuz sebagai bentuk taqiyya. Dalam sejarah politik Islam, konsep dan praktik taqiyya ini berkaitan dengan strategi kelompok Syiah agar tetap selamat ketika berada di bawah rezim Sunni. Yavuz juga mengutip pidato Bulent Arinc, juru bicara parlemen dari AKP,
“Sekularisme harus dipandang sebagai mekanisme untuk membangun perdamaian dan kompromi. Sekularisme memerlukan netralitas agama terhadap keyakinan. Fungsi dasar sekularisme adalah memberikan peluang kepada agama untuk mengekspresikan dirinya sendiri dan memberikan kebebasan beribadah” (hlm. 161).
Bagi Yavuz, pidato ini menyiratkan sentimen mayoritas yang dikhawatirkan akan berujung pada pembentukan sebuah “negara Islam” jika ada dukungan dari mayoritas.
Akan tetapi, analisis Yavuz tersebut cukup kontradiktif dengan argumentasinya di awal buku. Pada bagian awal buku, Yavuz menjabarkan panjang lebar bahwa AKP bukan lagi kelompok islamis. Sebagai partai, AKP telah memutuskan akar ideologinya dari Refah Partisi (Partai Refah), partai berideologi Islam di Turki. Sebelum mendirikan AKP, Erdogan merupakan satu satu anggota Partai Refah dan sempat menjadi ketua cabang partai di distrik Istanbul.
Dalam hal ini, Yavuz barangkali mengabaikan kemungkinan evolusi di tubuh AKP sendiri. Semenjak awal pendiriannya pada 2001, AKP sudah mendeklarasikan diri sebagai bukan partai Islam—sebagaimana beberapa partai sebelumnya. Dengan kata lain, sikap AKP terhadap sekularisme Turki bukanlah sebuah kontradiksi apalagi taqiyya. Pidato Erdogan maupun Bulent Arinc yang menyinggung soal sekularisme pada 2006 merupakan respon politik terhadap dalam situasi dan peluang yang tengah berubah, terutama dalam hal akses mereka terhadap kekuasaan. Dalam konteks ini, apa yang disebut oleh Alfred Stepan sebagai multiple secularism tampak relevan dengan apa yang dilakukan oleh AKP. Sekularisme di Turki merupakan sebuah diskursus terbuka. Dalam hal ini, AKP mencoba untuk melakukan redefinisi sesuai kepentingan politik dan nilai yang dianutnya.
Beberapa Catatan
Eksplorasi Yavuz dalam memotret masa transisi sekularisme di Turki memberikan kita gambaran penting bagaimana sebuah ideologi politik dan agama memungkinkan untuk dimoderasi. Sayangnya, beberapa argumen Yavuz kurang didukung oleh elaborasi data yang memadai. Misalnya, ketika membahas pengaruh borjuasi muslim Turki, Yavuz tidak menyajikan data statistik tentang skala ekonomi komunitas muslim di Turki. Data tersebut akan membantu pembaca untuk memahami secara utuh seberapa besar pengaruh ekonomi borjuasi Anatolia tersebut terhadap para kapitalis pendukung Kemal—yang ia sebut sebagai kapitalis Pro-Kemalis Istanbul (hlm. 49). Di samping itu, penggunaan data statistik tersebut dapat mengungkap seberapa besar pendanaan yang diterima oleh AKP dari para borjuasi Anatolia ini dan bagaimana model hubungan seperti ini memengaruhi diskursus, program, dan agenda partai itu sendiri.
Dalam bagian “Kesimpulan”, ada beberapa hal penting yang menarik untuk didiskusikan lebih lanjut berkaitan dengan agensi AKP dalam kehidupan politik Turki. Pertama, bagi Yavuz, kemunculan AKP sebagai partai pemerintah menandai momentum berakhirnya kedaulatan ganda yang dimainkan oleh kekuatan militer Turki. Sebagai partai penguasa, AKP pelan-pelan mampu membatasi ruang gerak dan supremasi militer Turki melalui perubahan regulasi, khususnya yang berkaitan dengan isu hak asasi manusia dan kebebasan.
Di sisi lain, agensi borjuasi Muslim telah berdampak pada perubahan mendasar terhadap posisi negara dalam politik domestik Turki, yang bergeser dari sebuah institusi “semi-sakral” menjadi sebuah institusi yang berorientasi pada warga negara—yang memandang negara sebagai sekumpulan institusi yang bertugas untuk melayani masyarakat dan melindungi struktur nilai masyarakat itu sendiri. Nilai etika wirausaha yang dianut oleh kelompok borjuasi muslim ini—yang menekankan pada pentingnya menjadi kaya dan mampu merealisasikan potensi warga negara—telah membuat partisipasi warga negara dalam wajib militer menjadi tidak relevan. Wajib militer sebagai bukti loyalitas dan cinta tanah air merupakan wujud dari etika birokrasi dan perspektif negara-sentris. Yavuz juga mencatat perubahan yang terjadi dalam masyarakat Turki berkaitan dengan lunturnya aksentuasi “bahasa sekuler” meskipun lembaga militer, peradilan, dan pendidikan tinggi masih menjadi penjaga gawang sekularisme Kemalis.
Buku ini merupakan sebuah pengantar untuk memahami perkembangan situasi politik Turki pada awal abad ke-20. Penelusuran Yavuz atas kemunculan dan evolusi AKP memang bukanlah hal yang benar-benar baru dalam diskusi tentang Islam dan demokrasi atau tentang norma praktis sekularisme di negeri berpenduduk mayoritas muslim. Akan tetapi, buku ini bisa menjadi pendamping dan pembanding terhadap dinamika serupa. Misalnya, di Indonesia terdapat studi serupa yang dilakukan oleh Burhanudin Muhtadi (2008) tentang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Indonesia. Berkaca pada studi kasus PKS, Muhtadi mengemukakan bahwa demokrasi liberal telah memaksa partai politik untuk mengesampingkan ideologi mereka dan menekankan program dan idiom-idiom “sekuler” atau populis demi meraih suara pada pemilihan umum.
Secularism and Muslim Democracy in Turkey
M. Hakan Yavuz.
Cambridge University Press, 2009. 322 hlm.
ISBN 978-0521888783
______________________
Imam Sopyan adalah Alumni Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS), Sekolah Pascasarjana UGM, angkatan 2019. Baca tulisan Imam lainnya di sini.

