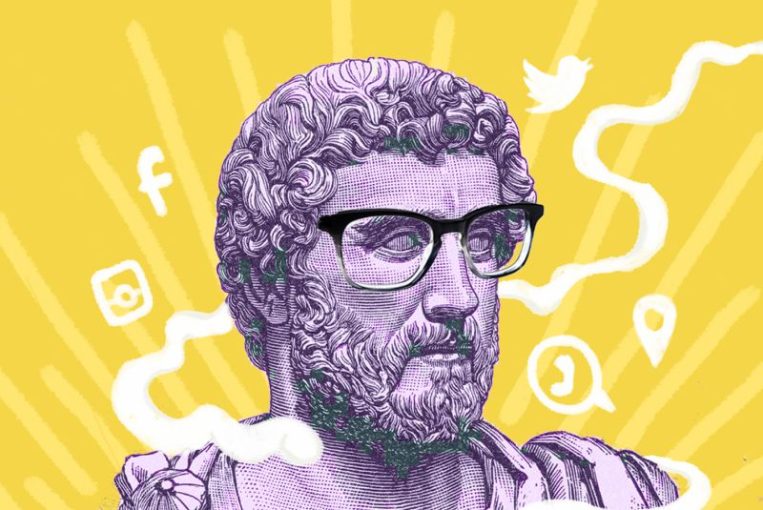
Stoikisme: Refleksi Spiritual Zaman Now
Irzha Ayu Mandira – 27 September 2022
“Ada dua hal penting yang perlu kita pahami: sesuatu yang ada di bawah kendali kita dan sesuatu yang ada di luar kendali kita”
Beberapa tahun ini, krisis eksistensi diri menjadi salah satu akar permasalahan yang dihadapi generasi muda. Mereka harus hidup dengan realitas bahwa masyarakat dan lingkungannya secara tidak langsung memiliki ekspektasi tertentu terhadap cara dan standar kehidupan mereka. Di sisi lain, media sosial tidak hanya menjadi candu tetapi juga menciptakan insekuritas di tengah standar sosial yang semakin tinggi. Namun, siapa sangka beribu-ribu tahun sebelumnya, ada seorang kaisar Roma yang menulis “solusi” terhadap masalah eksistensi diri yang sering diklaim sebagai masalah “zaman now”.
Mengenal Stoikisme ala Aurelius
Marcus Aurelius Antoninus adalah seorang kaisar Roma yang juga seorang filsuf. Ia adalah penguasa terakhir Roma yang masuk ke dalam jajaran Five Good Emperors. Selama berkuasa, Aurelius menulis jurnal pribadi yang ia sebut sebagai Τὰ εἰς ἑαυτόν atau perenungan. Jurnal yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan judul Meditations ini ini berisi kisah-kisah dan kiat untuk mengatasi kekhawatiran, hawa nafsu, dan kegetiran yang ia rasakan sebagai seorang kaisar besar Roma dan manusia biasa. Jurnal inilah yang nantinya akan menginspirasi banyak buku-buku stoikisme lain, bahkan hingga saat ini.
Stoikisme adalah sebuah aliran filsafat dari Athena yang menekankan pada pengendalian diri. Berasal dari kata stoa dalam bahasa Yunani yang artinya adalah ‘teras’, ajaran filsafat ini biasa diajarkan di teras-teras kuil. Menurut stoikisme, secara sederhana, puncak dari kebahagiaan adalah ketika kita dapat terlepas dari emosi negatif ciptaan kita sendiri maupun orang lain.
Stoikisme awalnya dipopulerkan oleh Zeno dari Citium. Namun, stoikisme ala Zeno masih merupakan gambaran umum tentang hubungan antara alam semesta dan kehidupan manusia, sementara stoikisme ala Marcus Aurelius jauh lebih praktikal. Aurelius menulis Meditations pada masa-masa terakhirnya berkuasa yang merupakan masa penuh tekanan: dari pergulatan internal dalam tubuh kekaisaran, kematian orang-orang terdekat—termasuk istrinya, hingga gejolak batin bahwa putranya bukanlah seorang pemimpin ideal untuk melanjutkan estafet kekaisaran. Aurelius menuliskan segala permasalahan yang dia hadapi, beserta sisi-sisi kemanusiaannya, sekaligus tameng untuk menghadapinya. Dia sering sekali menggunakan afirmasi kata dalam gaya penulisan seakan-akan ada dua kepribadian dalam satu raga yang saling berbicara. Saya akan mengambil contoh dari beberapa kutipan favorit saya:
“Choose not to be harmed—and you won’t feel harmed. Don’t feel harmed—and you haven’t been.”
“So other people hurt me? That’s their problem. Their character and actions are not mine. What is done to me is ordained by nature, what I do by my own.”
Cara kaisar Roma ini menuliskan jurnalnya mengingatkan saya kepada masa-masa saat seorang remaja merasa marah kepada dunia—tentu saya pun mengalaminya. Saya dan jutaan remaja lainnya membutuhkan afirmasi atas emosi yang dirasakan saat dihadapkan pada situasi yang tidak mengenakkan.
Pada bagian lain, Aurelius menulis:
“When you wake up in the morning, tell yourself: The people I deal with today will be meddling, ungrateful, arrogant, dishonest, jealous, and surly. They are like this because they can’t tell good from evil. But I have seen the beauty of good, and the ugliness of evil, and have recognized that the wrongdoer has a nature related to my own—not of the same blood or birth, but the same mind, and possessing a share of the divine. And so none of them can hurt me.”
Bagi Aurelius, kebaikan dan kejahatan adalah sifat bawaan yang sudah dimiliki seorang manusia. Oleh karena itu, ia mencoba mempersiapkan diri bahwa setiap hari dia akan menghadapi manusia yang punya bawaan untuk berbuat jahat, arogan, dan dengki. Karenanya, seorang manusia tidak selaiknya membenci manusia lain, sama tidak pantasnya dengan seorang manusia yang membenci datangnya fajar. Menghadapi situasi demikian, yang akan ia lakukan adalah memperlakukan mereka dengan kebaikan. Menurut Aurelius, orang-orang seperti itu sebetulnya tidak pernah merasakan kebaikan yang seharusnya. Baginya, hal-hal buruk yang tidak diinginkan itu adalah hal yang berada di luar kendali dan yang bisa dikendalikan oleh manusia adalah sikapnya sendiri.
Dalam setiap bagian dari jurnalnya, pikiran-pikiran Aurelius agaknya mengerucut pada sesuatu yang seharusnya menjadi fitrah setiap manusia dalam berhubungan dengan sesamanya, yaitu kasih sayang. Pemikiran Aurelius ini dikenal dengan ungkapan amor fati—secara harfiah berarti mencintai takdir—mencintai segala macam hal baik dan buruk yang terjadi pada diri kita. Akan tetapi, stoikisme ini terkadang disalahartikan sebagai bentuk pengendalian diri yang submisif bahwa seorang manusia seharusnya menerima takdir dan mengikuti alurnya seperti aliran sungai tanpa berusaha untuk menjadi lebih baik. Padahal, pengendalian diri ala stoikisme menekankan pada reaksi terhadap segala keputusan dan usaha yang kita buat sepanjang hidup, tidak menyerah pada keadaan, dan menyadari bahwa semua adalah sementara tetapi perlu diperjuangkan. Aurelius menyebutnya dengan memento mori, pengingat bahwa kita semua akan meninggalkan dunia dan sudah sepatutnya berbuat yang terbaik semasa kita hidup.
Aurelius mengajak kita melihat hal-hal yang kerap dipersepsikan sebagai tidak menyenangkan dari berbagai sisi. Ketika harus menghadapi musuh atau orang yang ingin menyakitinya, ia mengafirmasi kepada dirinya sendiri untuk menimbang segala baik dan buruk serta mengulik alasan seseorang dapat menyakitinya. Dengan demikian, akhirnya timbul rasa iba dalam diri dan memberikan kesempatan kepada diri kita untuk berbagi rasa atas kebaikan yang kita terima. Marah bukanlah solusi dari rasa sakit hati yang kita miliki.
Stoikisme: Spiritualitas “Kekinian”
Ketika membaca Meditations (2003) terjemahan dari Gregory Hays, saya merasa mengenal Marcus Aurelius begitu dekat seakan-akan dia baru hidup beberapa puluh tahun lalu—bukan ribuan tahun yang lalu. Pertempuran lahir-batin dan mental-raga yang ia jalani membantu saya menghadapi sedikit dari banyak “pertempuran” hati yang saya alami. Pertarungan yang kerap terjadi di usia saya, dan dialami oleh anak muda Indonesia, adalah penaklukan “Ibukota”. Ibukota adalah simbol kesuksesan, ia dapat hadir sebagai Jakarta, Jogja, atau apapun yang melambangkan suatu pencapaian dan kebanggaan. Melalui media sosial, saya melihat bagaimana rekan-rekan saya bertempur sebegitu kerasnya untuk menaklukkan “ibu kota”. Sebagai bagian dari generasi yang lahir sebagai imigran digital, saya benar-benar merasakan perbedaan sebelum dan sesudah keberadaan media sosial. Keberadaan media sosial seakan menjadi amunisi untuk memperoleh validasi—terutama dari orang-orang di lingkaran sosial terdekat yang hidupnya (dianggap) biasa-biasa saja. Di sisi lain, media sosial telah menjadi candu dan membuat saya, dan banyak generasi muda, jatuh ke dalam jurang insekuritas yang dibuat sendiri.
Di sinilah jurnal Meditations karya Aurelius menemukan signifikansinya. Stoikisme Aurelius mengajarkan dikotomi kendali. Hal-hal yang dilakukan oleh rekan-rekan saya adalah hal di luar kendali dan seorang stoik tidak boleh membiarkan hal ini mengambil alih dan mempengaruhi kehidupannya. Yang bisa saya lakukan adalah membentenginya dengan sikap yang bijak bahwa rekan-rekan saya memang sedang melakukan usaha yang perlu mereka lakukan sesuai dengan tujuannya, saya pun cukup melakukan demikian untuk hidup saya. Terlihat sederhana, tetapi maknanya dalam.
Jurnal Meditations ini begitu berpengaruh dalam perkembangan filasafat stoikisme maupun buku-buku self help di era modern. Hampir semua buku-buku stoikisme di era kiwari tak pernah alpa mengutip atau setidaknya menyinggung pemikiran Aurelius. Tak heran, sebagian orang membandingkan stoikisme dengan ajaran agama. Yang menarik, dalam jurnalnya, Aurelius sama sekali tidak menyinggung tentang peran kepercayaan yang ia anut karena, menurutnya, memang bukan praktik agama yang membantunya mengatasi masalah. Menurut saya, stoikisme dan agama tidak saling mengintervensi dan bisa berdampingan. Stoikisme bukanlah agama yang memiliki serangkaian ritual dan praktik atau bersifat mengikat. Seorang penganut agama tertentu dapat menjadi seorang stoik tanpa menafikkan keyakinannya. Stoikisme ala Aurelius adalah jembatan jiwa raga kita untuk menuju jembatan jiwa raga orang lain.
Meditations | Marcus Aurelius | The Modern Library, 2002. 303 hlm. | Introduction and notes copyright by Gregory Hays | e-ISBN 1-58836-173-X
______________________
Irzha Ayu Mandira adalah mahasiswa Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS), Sekolah Pascasarjana UGM, angkatan 2022. Baca tulisan Irzha lainnya di sini.

