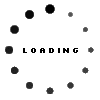Seberapa Universalkah Hak Asasi Manusia?
Azis Anwar Fachrudin – 1 Juli 2018
— Catatan ini berdasar pada dua kuliah pertama bersama Brett Scharffs dari International Centre for Law and Religious Studies, Brigham Young University
Sesuai namanya, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) diniatkan menjadi norma internasional yang berlaku universal. Ketika diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 1948, 48 dari 58 negara anggota PBB menyatakan dukungan terhadap DUHAM, 8 abstain, dan 2 tak ikut voting. Bisa dikatakan, adopsi DUHAM di PBB tak mendapat tentangan.
Melihat proses lahirnya DUHAM penting untuk menjawab apakah DUHAM, seperti anggapan sejumlah pihak, adalah bentuk pemaksaan nilai-nilai ‘Barat’ terhadap ‘Timur’. Komisi HAM PBB (United Nations Commission on Human Rights/UNCHR) yang membidani lahirnya DUHAM itu sendiri terdiri dari 18 negara, yaitu Australia, Belgia, Belarusia, Chile, Tiongkok, Mesir, Prancis, India, Iran, Lebanon, Panama, Filipina, Ukraina, Uni Soviet, Inggris, Amerika Serikat, Uruguay, dan Yugoslavia. Komisi khusus yang bertugas menyusun draf awal DUHAM beranggotakan Eleanor Roosevelt (AS), Charles Habib Malik (Lebanon), Peng Chun Chang (Tiongkok), John Humphrey (Canada), dan Rene Cassin (Prancis).
Dalam proses perdebatan untuk mengesahkan DUHAM, justru negara-negara kecil yang keras memperjuangkan adopsi DUHAM, sementara negara-negara adidaya seperti AS, Inggris, dan Uni Soviet cenderung enggan. AS saat itu masih mengidap segregasi rasial yang parah. Uni Soviet yang berideologikan komunisme meletakkan superioritas kepentingan kolektif atas kepentingan individu. Inggris pada waktu itu masih ingin mempertahankan kuasanya atas koloni-koloninya. Secara pragmatis, nilai-nilai dasar DUHAM akan condong pada kepentingan negara-negara kecil yang sedang atau baru saja lepas dari penjajahan, juga pada kaum yang tertindas di dalam suatu negara. Pasal pertama DUHAM berbunyi, “Semua manusia dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat dan hak-haknya. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan” (All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.)
Martabat (dignity), kemerdekaan (freedom), dan kesetaraan (equality) adalah tiga nilai yang mendasari HAM. Inilah istilah-istilah kunci yang kemudian menciptakan ‘diskursus’ tentang HAM. Tebal draf DUHAM pada mulanya ratusan halaman, dengan sebagian besar isinya berupa catatan kaki yang merujuk ke berbagai literatur dari beragam budaya, baik Barat maupun Timur, yang mengandung ajaran-ajaran yang pada substansinya berkonvergensi pada nilai-nilai yang mendasari DUHAM itu.
Adanya kata “conscience” (hati nurani) dan “in a spirit of brotherhood” (dalam semangat persaudaraan) pada Pasal 1 DUHAM itu sendiri bermula dari usulan Peng Chun Chang asal Tiongkok. Idenya adalah untuk memasukkan konsep “ren” (仁), yang berakar pada Konfusianisme. Kata ini tersusun dari dua aksara, yaitu “人” yang berarti “orang” dan “二” yang berarti “dua”. “Ren” merepresentasikan nilai “kedua-orangan” (terjemah literalnya dalam bahasa Inggris: two-man mindedness), atau lebih simpelnya: empati, yaitu tentang bagaimana manusia seharusnya memperlakukan satu sama lain dengan kebajikan (benevolence). Dalam tafsirnya oleh sejumlah filsuf Konfusian, “ren” kerap diartikan pemenuhan kewajiban terhadap orang lain yang sama-sama memiliki kepentingan dan hak yang setara.
Jadi, melalui “ren”, HAM bukan sekadar berisi dorongan untuk mengklaim hak, melainkan juga pemenuhan kewajiban. Keberadaan konsep “ren” ini membantu untuk menjembatani wacana HAM dalam konteks budaya yang lebih mengutamakan pemenuhan kewajiban (bagi kepentingan kolektif) dibanding klaim atas hak (bagi kepentingan individu), seperti di banyak negara Asia dan Afrika (di Afrika Selatan, misalnya, konsep senada diberi istilah “ubuntu”).
Dengan demikian, perumusan HAM yang dimaksudkan sebagai norma universal itu diupayakan sedapat mungkin menyerap konsep-konsep lintas budaya. Menyatakan HAM sebagai pemaksaan nilai-nilai ‘Barat’ justru berarti menegasikan kontribusi dan perjuangan negara-negara ‘Timur’ dalam meraih martabat yang setara.
Sebagai tindak lanjut dari DUHAM, pada 1966 terbit dua pakta/kovenan yang ditujukan sebagai dokumen legal sehingga lebih mengikat, yaitu International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR)—dua pakta ini pada mulanya ingin dibuat satu, namun akhirnya menjadi dua karena faktor rivalitas blok Barat dan blok Uni Soviet dalam Perang Dingin. Hingga kini, ICCPR telah diratifikasi oleh 171 negara. Indonesia meratifikasinya pada 2005.
Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
Karena DUHAM diniatkan menjadi norma internasional yang berlaku universal, muncul persoalan: bagaimana membuat sesuatu yang universal dari nilai-nilai lintas budaya yang beragam? Pada tataran praksisnya, pengadopsian dan pemberlakuan instrumen HAM tak dapat mengabaikan sensitivitas nilai tertentu dan, dalam sejumlah kasus, isu politik seperti kedaulatan negara. Dalam soal ini, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) bisa menjadi contoh.
Mengenai KBB, DUHAM menegaskannnya pada Pasal 18:
Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.
(Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaann dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri. —Terjemah Indonesia ini dari Komnas HAM)
Agar menjadi dokumen legal yang lebih mengikat, DUHAM ditindaklanjuti dengan instrumen turunan seperti ICCPR. Di ICCPR, KBB ditegaskan pada Pasal 18. Ayat pertama pasal ini, yang menegaskan hak individual yang tak bisa dibatasi (biasa disebut “forum internum”), berbunyi:
Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice….
(Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri… —Terjemah Indonesia ini mengikuti versi UU 12/2005 tentang Ratifikasi ICCPR)
Tampak ada yang berbeda antara klausul KBB di ICPPR dan di DUHAM. Di DUHAM frasa yang dipakai adalah “freedom to change his religion or belief” (kebebasan berganti agama atau kepercayaan). Di ICCPR, karena ingin mengakomodasi sensitivitas negara-negara mayoritas Muslim, frasanya dibuat lebih ‘lunak’ sehingga menjadi “freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice” (kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri). (Tentang Islam dan hak berganti agama, baca: Islam, Kebebasan Beragama, dan Hukuman Murtad)
Karena dalam DUHAM ada klausul mengenai hak berganti agama itulah Arab Saudi abstain dalam pengesahan DUHAM—inilah salah satu penyebab sensitivitas isu ini dan pelunakan redaksinya di ICCPR. Arab Saudi adalah satu-satunya negara mayoritas Muslim dalam 8 negara yang abstain itu. Negara Islam lain, misalnya Pakistan, melalui Menlu Muhammad Khan justru membangun argumen menarik: Islam sendiri adalah agama dakwah/misionaris yang ingin mengajak non-Muslim untuk masuk Islam, alias berganti agama; bagaimana bisa tak mengakui hak berganti agama?
Pasal 18 ICCPR juga mengandung ayat tentang pembatasan manifestasi KBB di ruang publik (biasa disebut “forum externum”). Bunyinya:
Freedom to manifest one’s religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedom of others.
(Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keselamatan publik, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.)
Khusus di Eropa, pada 1950 terbit pakta European Convention on Human Rights/ECHR (nama resminya: Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms). Di ranah legal, Konvensi ini melahirkan European Court of Human Rights (ECtHR). Yang istimewa dari ECtHR ini ialah: bila persengkataan antarnegara dibawa ke ranah internasional ke International Court of Justice (IJC), di Eropa orang bisa membawa kasus individu melawan negara ke ECtHR. Bila ada produk hukum suatu negara di Eropa yang dipandang telah melanggar HAM, seseorang dapat mengadukan kasusnya ke ECtHR.
Mengenai KBB, ECHR menegaskannya dengan nada kalimat yang mirip dengan Pasal 18. Ketentuan khusus yang sensitif di pasal itu, yakni mengenai hak “berganti agama”, diadopsi sama persis di ECHR. Dan, sama seperti ICCPR, klausul KBB di ECHR juga mengandung ayat yang menyoroti forum internum dan forum externum. Klausul tentang pembatasan KBB di ECHR berbunyi:
Freedom to manifest one’s religion or beliefs shall be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests of public safety, for the protection of public order, health or morals, or for the protection of the rights and freedom of others.
(Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum dan diperlukan bagi masyarakat demokratis demi kepentingan keselamatan publik, melindungi ketertiban publik, kesehatan, atau moral masyarakat, atau untuk melindungi hak-hak dan kebebasan orang lain.)
Setiap kasus KBB yang dibawa ke ECtHR selalu diputuskan dengan dasar ayat itu. Urutan untuk memutuskan apakah suatu pembatasan KBB sah atau tidak dalam perspektif HAM ialah: (1) apakah pembatasan itu telah ada ketentuan hukumnya (prescribed by law); (2) apakah pembatasan itu harus dilakukan demi melindungi ketertiban publik, keselamatan, hak orang lain, dst; dan (3) apakah pembatasan itu merupakan keharusan dalam masyarakat demokratis (necessary in a democractic society).
Dari ketiga urutan itu, hal terakhir (necessary in a democratic society, diperlukan bagi masyarakat demokratis) acapkali memicu kontroversi. Pada titik inilah muncul konsep yang disebut “margin of appreciation”, satu doktrin yudisial yang tak disebut dalam ECHR namun menjadi acuan terakhir ketika menghadapi kasus besar yang dipandang telah mengintrusi kedaulatan negara. Margin of appreciation pada dasarnya adalah kawasan hukum di mana pengadilan memberikan diskresi kepada suatu negara untuk menentukan apakah suatu pembatasan adalah keharusan untuk mempertahankan masyarakat “demokratis”. Dengan pengertian ini, “margin of appreciation”, yang berasal dari kata Prancis “marge d’appréciation”, bisa lebih mudah dipahami dengan istilah lain dalam bahasa Inggris, “zone of deference” atau “zone of state discretion”, kawasan diskresi negara.
Dua contoh dari praktik ECtHR dalam memberlakukan margin of appreciation ada dalam kasus pelarangan hijab di Prancis dan keharusan pemasangan salib di sekolah-sekolah negeri di Italia. Ketika dua kasus ini dibawa ke ECtHR, pada akhirnya pengadilan memberikan diskresi ke negara yang bersangkutan, dan keputusannya: negaralah yang menang. Alasan utama yang diberikan negara yang bersangkutan ialah pembatasan itu sudah menyangkut soal identitas nasional dan ideologi negara. Istilah khusus bagi ideologi negara ini di Prancis adalah “laïcité”. Di Prancis, laïcité begitu kuat memengaruhi diskursus mengenai identitas nasional. Kuatnya diskursus ini, yang sudah termaktub dalam konstitusi Prancis, turut dipengaruhi oleh sejarah Prancis itu sendiri, yaitu sejarah revolusi membebaskan diri dari hegemoni gereja, sehingga freedom di Prancis condong pada makna freedom from religion, alih-alih freedom of religion. Ke-Prancis-an bagi publik umum di Prancis lazim diartikan dalam pengertian ini. Dalam pengertian ini pula, pemakaian hijab di ruang publik dipandang sebagai sebuah serangan bagi identitas ke-Prancis-an.
Isu hijab di Perancis ini menunjukkan bahwa KBB dalam instrumen HAM internasional masih mendapat negosiasi (atau kontekstualisasi?) dalam praksisnya, khususnya ketika pemberlakuannya dipandang telah mengintrusi kedaulatan sebuah negara.
Bagi negara-negara lain, terlebih negara-negara mayoritas Muslim, kasus hijab di Prancis bisa dipandang sebagai standar ganda, atau lebih kasar lagi: hipokrisi. Khusus menyangkut soal ini, salah satu pengajar kuliah Religion and Human Rights di CRCS, Brett Scharffs, mengajak untuk melihat konteks Eropa belakangan ini, yaitu fakta bahwa integrasi Uni Eropa kini sedang rapuh. Sejumlah negara Eropa ingin keluar dari Uni Eropa karena memandang institusi ini terlalu mencampuri kedaulatan negara. Terjadinya “Brexit” adalah penanda paling signifikan. Uni Eropa sendiri dibangun atas dasar penolakan pada nasionalisme sempit. Dengan rapuhnya Uni Eropa, kerentanan terhadap gejolak yang sama turut terjadi pada Council of Europe, lembaga yang membawahi ECHR. Keberadan konsep margin of appreciation, yang memberikan diskresi pada negara, ialah salah satu jalan untuk mempertahankan integrasi dan soliditas Council of Europe ini. Keistimewaan pengadilan HAM seperti yang dimiliki ECtHR dipertaruhkan jika Council of Europe itu sendiri terancam bubar.
Hal terakhir ini menunjukkan bahwa DUHAM dan segenap turunannya, yang merupakan dokumen politik, juga tetap tak bisa menghindar dari ruang politik riil yang tidak vakum dari negosiasi kepentingan aktor-aktor politik yang menjadi anggotanya. Dalam kalimat lain, universalitas HAM mengalami partikularisasi dalam kasus semacam ini. Dibawa lebih jauh, ini juga menunjukkan bahwa kata “demokrasi” perlu diberi tanda petik, karena maknanya tak tunggal. Pada praktiknya, “demokrasi” tak selalu berimplikasi pada supremasi hak individu.
Pada akhirnya, diskursus mengenai HAM masih mendapati debat yang belum usai, bukan saja ihwal apakah HAM itu universal atau tidak, melainkan juga bagaimana yang universal dan yang partikular dalam HAM berinteraksi.
_______________
Catatan ini berdasar pada kuliah Religion and Human Rights di CRCS UGM, yang diadakan atas kerja sama dengan Oslo Coalition on Freedom of Religion and Belief dan International Centre for Law and Religious Studies Brigham Young University (ICLRS-BYU), pada semester pendek 2018 dengan para pengajar yang terdiri dari Zainal Abidin Bagir, Suhadi, Brett Scharffs, Tore Lindholm, Lena Larsen, Renata Arianingtyas, Rikardo Simarmata, dan Asfinawati.
Bahan tertulis untuk sesi kelas pertama ini adalah tulisan Brett Scharfs yang akan diterbitkan dalam waktu dekat dalam bahasa Indonesia dalam sebuah buku kumpulan tulisan mengenai HAM dan Syariah.