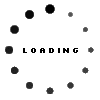CRCS| Wedforum | Riza Saputra
 Menarasikan kembali sejarah di masa yang lalu ke masa yang sekarang memang tidaklah semudah membolak-balikkan telapak tangan. Akan tetapi, mengkonstruksi ulang sejarah adalah hal yang perlu, apalagi jika sejarah itu masih diliputi dengan misteri dan kabut yang tebal. Tragedi 1965 di Indonesia yang terkait dengan pembantaian massal juga masih diliputi dengan puing-puing keganjilan. Namun, seiring dengan konstelasi politik pada tahun 1998, seiring pula dengan jatuhnya masa rezim Soeharto, dan berganti dengan era reformasi yang lebih bebas, muncullah ke permukaan pendapat-pendapat baru tentang peristiwa 1965 di Indonesia. Bercermin dari pembahasan ini, Ayu Dias Rahmawati, dosen sekaligus peneliti yang berasal dari Center for Security and Peace Studies (CSPS) Universitas Gadjah Mada, menyampaikan bahwa peristiwa 1965 perlu mendapatkan ruang yang lebih luas untuk didiskusikan kembali, tidak terbatas hanya kepada para korban dan pelaku, akan tetapi juga seluruh masyarakat yang turut menyaksikan peristiwa tersebut. Pernyataan ini Ayu sampaikan dalam acara Wednesday Forum yang dilaksanakan oleh CRCS dan ICRS di lantai empat, gedung pascasarjana Universitas Gadjah Mada (18/09/2013).
Menarasikan kembali sejarah di masa yang lalu ke masa yang sekarang memang tidaklah semudah membolak-balikkan telapak tangan. Akan tetapi, mengkonstruksi ulang sejarah adalah hal yang perlu, apalagi jika sejarah itu masih diliputi dengan misteri dan kabut yang tebal. Tragedi 1965 di Indonesia yang terkait dengan pembantaian massal juga masih diliputi dengan puing-puing keganjilan. Namun, seiring dengan konstelasi politik pada tahun 1998, seiring pula dengan jatuhnya masa rezim Soeharto, dan berganti dengan era reformasi yang lebih bebas, muncullah ke permukaan pendapat-pendapat baru tentang peristiwa 1965 di Indonesia. Bercermin dari pembahasan ini, Ayu Dias Rahmawati, dosen sekaligus peneliti yang berasal dari Center for Security and Peace Studies (CSPS) Universitas Gadjah Mada, menyampaikan bahwa peristiwa 1965 perlu mendapatkan ruang yang lebih luas untuk didiskusikan kembali, tidak terbatas hanya kepada para korban dan pelaku, akan tetapi juga seluruh masyarakat yang turut menyaksikan peristiwa tersebut. Pernyataan ini Ayu sampaikan dalam acara Wednesday Forum yang dilaksanakan oleh CRCS dan ICRS di lantai empat, gedung pascasarjana Universitas Gadjah Mada (18/09/2013).
Dalam forum ini, Ayu menyampaikan bahwa ‘collective memories’ atau ingatan bersama adalah hal yang sangat penting untuk merumuskan kembali sejarah yang telah tertanam di dalam ideologi masyarakat Indonesia. Setelah 40 tahun dalam kebisuan dan trauma yang mendalam. Bangsa Indonesia dewasa ini telah berani menyuarakan kembali pendapat mereka tentang tragedi 1965. Seperti halnya yang telah dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa perlu adanya tindakan hukum terhadap pelaku pembantaian kelompok yang diduga komunis pada tahun 1965. Selanjutnya permintaan maaf yang disampaikan oleh presiden Abdurrahman Wahid kepada korban peristiwa September 1965, karena keterlibatan kelompoknya Nahdhatul Ulama dalam tragedi ini. Dari contoh diatas, Ayu menyimpulkan bahwa apa yang telah mereka lakukan ini adalah salah satu bentuk negosiasi untuk menciptakan rekonsiliasi kepada para korban tragedi 1965. Namun, sayangnya, usaha rekonsiliasi yang telah dilakukan ini pada umunya selalu gagal dan mendapat penolakan.
Selanjutnya Ayu menyampaikan bahwa untuk menciptakan rekonsiliasi kita perlu melakukan negosiasi ingatan bersama pasca tragedi 1965. Rekonsiliasi adalah sebuah bentuk kerukunan sosial, hak asasi manusia, perpaduan kekuasaan negara, dan keadilan sosial ekonomi (Kubik dan Linch, 2006, p. 19). Ayu menyatakan bahwa di dalam rekonsiliasi terdapat dua klasifikasi, yaitu, pertama adalah ‘Psycho social Process’ atau Proses sosial kejiwaan yang mengutamakan terapi perorangan, dan yang kedua adalah ‘Structural Process’ atau Proses Struktural yang lebih mementingkan ketahanan struktur dibandingkan dengan perorangan. Kemudian, Ayu mengutip pendapat Lederach (1997) yang mengemukakan tiga fondasi penting dalam rekonsiliasi, yaitu, kebenaran, keadilan, dan kemurahan hati, yang semuanya ini terwujud dalam ruang kesadaran untuk saling memahami. Selanjutnya Ayu menghubungkan pendapat ini dengan pendapat Elster (2004), bahwa rekonsiliasi ditujukan untuk masyarakat yang dilayani. Dari dua pandangan ini, Ayu membuat sebuah gagasan bahwa untuk melakukan rekonsiliasi kita perlu menyelaraskan memori mereka yang ikut andil dalam peristiwa ini.
Ingatan atau memori pasca konflik pada umunya berkutat pada dua kelompok utama, korban dan pelaku, akan tetapi, karena memori ini sangat bersifat politikal, maka untuk menggabungkan dua kutub yang berseberang diperlukan sebuah penghantar yang dapat menetralisasi. Oleh karena itu, menyelaraskan testimoni ini maka diperlukan masyarakat yang telah berdiri sebagai saksi peristiwa ini. Ayu mengutip pendapat Asmaan (2008) yang menyatakan bahwa, memori hendaknya tidak hanya ditanamkan pada diri pribadi, akan tetapi, ia juga saling berbagi, sehingga perwujudan rekonsiliasi akan terlihat jelas dalam panorama yang pasti, baik itu pembenaran, penguatan, ataupun perdebatan antara satu memori dan memori lainnya.
Selanjutnya, sembari menunjukkan gambar monumen lubang buaya yang berwarna hitam putih, Ayu menyampaikan cerita yang banyak berkembang di masyarakat Indonesia, terkait peristiwa 1965. Seringkali kaum komunis dinyatakan dalam konotasi negatif, misalnya, pengkhianat, kejam, setan, dan atheis. Pernyataan ini menggambarkan sebuah makna yang ironi dalam setiap ungkapannya, seakan-akan masyarakat Indonesia ini berpijak pada sebuah gambaran kesalihan, baik, dan adil. Cerita-cerita yang bernada sumbang ini masih tertanam di dalam ideologi masyarakat Indonesia, karena proses sosialisasi yang terus menerus, hingga terbenam dalam sebuah realita yang masih samar. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ayu berdasarkan pendapatnya Ellul (1996). Propaganda memperoleh kekuatan di dalam keruwetan, ia bukanlah sepenuhnya kebohongan dan bukan pula kebenaran yang sesungguhnya, ia terhantar dalam tiada keterbatasan. Ayu menyatakan, kebenaran yang parsial inilah yang kemudian dideklarasikan kepada masyarakat Indonesia.
Ayu kembali menekankan bahwa kita tidak boleh mengabaikan cerita para korban dan pelaku, karena mereka adalah peran utama yang tampil dalam peristiwa ini. Pernyataan-pernyataan kosong seperti yang telah disampaikan diatas, ternyata telah merasuk ke dalam berbagai referensi sejarah Indonesia. Seperti halnya, pemerintah orde baru yang menyatakan dengan tegas bahwa dalang utama tragedi 1965 adalah Partai Komunis Indonesia (PKI). Namun, tidak berlarut lama, pada tahun 1996, dua orang sarjana asing, Benedict Anderson dan Ruth McVey mengunggat pernyataan pemerintah ini. Selain itu, Herald Croch menyatakan bahwa adanya keterlibatan jenderal Soeharto dalam kelompok pergerakan ini. Analisis terbaru disampaikan oleh John Rossa (2006) yang berpendapat bahwa kesimpangsiuran tragedi ini hanyalah sebagai dalih semata yang dilakukan oleh militer Indonesia untuk menghancurkan entitas yang berlawanan arus dari mereka.
Dari pembahasan di atas, muncullah beberapa pertanyaan yang cukup ruwet untuk dijawab, diantaranya adalah, bagaimana kita bisa mengukur rekonsiliasi yang telah dilakukan selama ini? Dan mengapa kita perlu membahas peristiwa ini kembali, sedangkan kita telah berada pada generasi yang ketiga? Menanggapi pertanyaan ini, Ayu mengatakan bahwa rekonsiliasi adalah sebuah bentuk penciptaan relasi untuk memahami satu sama lain, jadi penelitian ini bukanlah ditujukan untuk mengukur seberapa jauh rekonsiliasi yang telah ada. Akan tetapi, ia lebih kepada pengumpulan persepsi, khususnya mereka yang terkungkung dalam tragedi ini. Sejarah ini perlu dibahas kembali, karena kita perlu memperhatikan hak-hak para korban. Dalam rekonsiliasi, yang kita perlukan bukanlah hanya fakta atau kebenaran, akan tetapi bagaimana kita bisa menerima satu sama lain. Tentu saja kita perlu menarasikan kembali peristiwa ini, hanya saja tidak dalam pola yang sama, karena kita tidak ingin kehilangan satu aspek dari cerita mereka, baik itu pelaku maupun para korban. Oleh karena itu, untuk menciptakan rekonsiliasi, kita perlu melakukan negosiasi sebelum kita menceritakan ulang tragedi ini.
Pada akhir diskusi, Ayu menyimpulkan bahwa yang kita perlukan dari sebuah rekonsiliasi bukanlah makna yang berifat ekslusif atau hanya berpihak pada satu kelompok. Akan tetapi, kita perlu memberikan kelonggaran bagi mereka untuk menegosiasikan ingatan bersama. Tak terkecuali, masyarakat Indonesia pada umumnya yang turut serta menyaksikan hiruk pikuk peristiwa ini. Pada akhirnya, tidaklah mudah meletakkan arah ingatan bersama ke dalam lembaran putih dan yang hitam. Kesalahan negara adalah memetakan keterlibatan sebuah kelompok yang belum pasti, sehingga narasi 1965 terdistorsi pada kebenaran tertentu. Hal inilah yang menyebabkan proses rekonsiliasi sulit untuk diwujudkan kembali, karena narasi para korban yang tidak tersusun secara rapi. Pada akhir diskusi, Ayu menyampaikan bahwa kita perlu menjauhi pendekatan yang dianggap terlalu prosedural, dan individualistis, yang hanya berpihak pada tonggak tertentu.