
Agama dalam Narasi: Jawa sebagai Objek
Gedong Maulana Kabir – 21 Sept 2019
Dalam wacana publik maupun akademik mengenai agama di Jawa, kita kerap mendapati dikotomi terkenal dan berpengaruh seperti santri dan abangan, juga istilah-istilah seperti agama Jawa atau Islam Jawa. Istilah abangan—biasanya dengan makna peyoratif dan berkonotasi inferior di bawah santri—acapkali merujuk pada mereka yang praktik keagamaannya dianggap kurang murni atau hanya secara nominal saja. Agama Jawa, atau juga Islam Jawa, kerap dirujukkan ke mereka yang praktik keagamaannya sinkretik atau bercampur dengan entah unsur ‘kejawen’, ‘animisme’, atau ajaran Hindu/Buddha.
Oleh tak sedikit orang, istilah-istilah dan dikotomi itu diterima tanpa kritis dan dilestarikan begitu saja (bahkan sudah menjadi sejumlah judul buku) seolah-olah ia merupakan tipologi yang penuh sesuai dengan kenyataan. Penelusuran sejarah, seperti yang akan diulas dalam tulisan ini, menunjukkan bahwa makna yang terkandung dalam dikotomi dan istilah-istilah tersebut sebenarnya melalui serangkaian konstruksi yang lama melalui lensa ‘Barat’ dan bias agama-dunia yang kental.
Agama Jawa: Dari pelancong, orientalis, hingga misionaris
Konstruksi agama Jawa dapat dipancangkan permulaannya dari catatan-catatan para pelancong dan orientalis yang kemudian dimanfaakan oleh para kolonialis yang datang ke Jawa. Geografer asal Skotlandia, Hugh Murray, dalam The Travels of Marco Polo (1845) mengetengahkan narasi pelancong abad 13 asal Italia itu yang menggambarkan Jawa sebagai dihuni orang-orang yang menyembah raja yang kuat sekaligus membayar upeti kepada para pangeran dan mereka adalah penyembah berhala (“The people there are subject to a powerful king, are idolaters, and pay tribute to any other prince”).

Perlu dicatat bahwa dalam deskripsi Marco Polo, pemeluk ‘agama’ hanya ada empat jenis saja, yakni the Christians, the Jews, the Mahometans, dan the idolaters. Bukan hanya di Jawa, di pelbagai tempat lain yang dikunjungi Marco Polo, bila tiga jenis orang pertama tak ditemui, ia akan mendeskripsikan orang-orang yang ditemuinya sebagai ‘idolaters’. “Berdasarkan pandangan Barat [abad pertengahan],” demikian kata Tomoko Masuzawa dalam The Invention of World Religions (2005), “hanya ada empat agama di dunia ini, yakni Kristen, Yahudi, Islam, dan heathenism.” Kata yang terakhir merujuk ke orang-orang di luar tiga agama pertama, lebih khususnya kaum pagan atau penyembah berhala.
Perspektif Marco Polo itu pun merefleksikan pandangan populer di kalangan Kristiani Eropa abad pertengahan. Ini tercermin dalam narasi bahwa Islam belum disebut sepenuhnya sebagai agama tersendiri, tetapi aliran ‘sesat’ yang didirikan oleh ‘nabi palsu’, dan karena itu pengikutnya disebut ‘Mahometans’, di samping istilah lain seperti ‘Saracens’ atau ‘Moors’ (tentang ini, lihat misalnya tulisan Moran Cruz, Popular Attitudes towads Islam in Medieval Europe [1999]). Di abad 16, ketika sudah ada komunitas Muslim di Jawa, pelancong Portugis Duarte Barbosa mencatat perjalanannya dalam The Book of Duarte Barbosa dan menggambarkan Jawa pada 1512 dihuni dua kelompok masyarakat, yakni Moors dan Gentiles, dan bahwa masyarakat Moors ini membayar upeti kepada raja Gentiles.
Saya berpendapat, itulah cikal-bakal pandangan dikotomik dalam melihat agama di Jawa. Pandangan Barbosa masih dilanggengkan oleh para pelancong berikutnya dengan narasi yang hampir tidak berselisih. Di periode berikutnya, mulai sekitar abad 18, seiring bercokolnya kolonialis di Nusantara, pandangan itu masih dilestarikan dengan sedikit perbedaan, yakni mulai munculnya konstruksi terhadap apa yang disebut sebagai ‘agama Jawa’ (Javanese religion), yang bagi para orientalis memiliki karakter yang distingtif.
“Secara umum masyarakat Jawa menganut ajaran Muhammad, tetapi tidak cukup familiar dengan ajaran moralnya,” tulis seorang pegawai Belanda di Semarang pada tahun 1820-an bernama Hendrik Domis dalam karyanya De Residentie Passoeroeang Op Het Eiland Java (1836), “Banyak masyarakat menyembah arca Hindu, pohon keramat, dan tempat-tempat lain.”
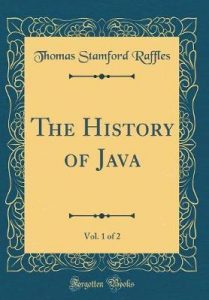
Karya Domis ini menandakan satu babak baru ketika agama orang Jawa mulai diasosiasikan dengan agama yang dianggap lebih tua, yaitu Hindu dan Buddha. Di fase ini, tokoh yang paling layak disebut sekaligus paling berpengaruh adalah Thomas Raffles dengan karya monumentalnya The History of Java (1817). Raffles antara lain berkata bahwa tradisi keagamaan Jawa yang berakar pada Hindu dan Buddha lebih sesuai dengan kepentingan Inggris untuk menjaga ketertiban publik ketimbang ‘the Mohammedan religion’ yang baginya “rebellious”, suka memberontak.
Setelah apa yang disebut sebagai ‘agama Jawa’ dikonstruksi, untuk pertama kalinya istilah yang bisa merujuk pada apa yang kini disebut ‘Islam Jawa’ ditemukan dalam uraian misionaris Belanda seperti Jan Frederik Brumund. Dalam Berigten Omtrent de Evangelisatie van Java (Perjuangan Mengenai Evangelisasi di Jawa)—semacam buletin yang diterbitkan oleh para evangelis Jawa pada 1854 yang bermarkas di Surabaya—Brumund mengatakan, “Javanese Mohammedans percaya bahwa terdapat kehidupan roh jahat di pohon tertentu.”Brumund memberikan label Islam Jawa (waktu itu masih memakai istilah ‘Javanese Mohammedan’) dalam penggambarannya terhadap masyarakat Muslim yang mempercayai takhayul kuno.
Karakterisasi tradisi keagamaan yang khas Jawa mulai kian mengkristal ketika pada kisaran 1860, Harthoorn dalam De zending op Java en meer bepaald die van Malang mulai memberikan label baru, ‘Javanism’, untuk menyebut tumpukan identitas di atas. Segendang sepenarian, Carel Poensen, anggota Masyarakat Misionaris Belanda (Nederlandsch Zendelinggenootschap) dalam Een en ander over den godsdienstigen toestand van den Javaan (‘Segala hal tentang situasi keagamaan di Jawa’, [1865]) mulai menggunakan istilah sinkretisme untuk menyebut praktik keagamaan masyarakat Jawa Muslim sebagai percampuran aneh antara Buddha, Hindu, dan Islam.
Periode Indonesia: Islam Jawa dalam narasi akademisi
Karya dua tokoh terakhir tersebut di atas itu turut digunakan oleh M.C. Ricklefs ketika mengulas asal-usul abangan dalam artikelnya The Birth of Abangan (2006). Dalam kehidupan sehari-hari, katanya, pada tahun 1880-an dan seterusnya sudah mulai ditemukan pemilahan dengan istilah abangan dan putihan. Fenomena ini merebak bersamaan peristiwa Haji Akbar di tahun 1880, 1885, dan 1888. Seperti dicatat Poensen, di Kediri kaum abangan semakin kehilangan basis keagamaannya sedangkan kaum putihan tampak semakin kuat. Pada periode ini, penggunaan istilah abangan masih sangat cair. Namun pada umumnya, istilah ini digunakan oleh kaum putihan untuk mengolok kaum abangan.
Artikel Ricklefs tersebut sebenarnya merupakan respons terhadap karya antropolog Amerika, Clifford Geertz, yang memilah kelas sosial keagamaan di Jawa menjadi abangan, santri, dan priyayi. Ricklefs seperti ingin mengatakan bahwa istilah abangan dan putihan (serupa dengan santri dalam istilah Geertz) telah ada jauh sebelum Geertz melakukan penelitian di Mojokuto (Pare), Kediri, yang kemudian ditulisnya dalam karya terkenal yang amat berpengaruh dalam kajian antropologi, The Religion of Java (1960). Karya Geertz ini menandakan suatu babak baru ketika ‘agama Jawa’ tidak lagi dibahas oleh para misionaris saja, tetapi juga oleh para akademisi. Dalam karya ini, Geertz antara lain menggambarkan abangan sebagai kelompok yang menjadikan slametan sebagai ritual inti.

Saya berpendapat, dikotomi ala Geertz ini sebenarnya merupakan terusan dari narasi era kolonial yang dulu memilah keagamaan masyarakat Jawa dalam dikotomi Islam dan penyembah berhala, lalu mengkristal dalam identifikasi agama Jawa, dan terakhir pada gambaran mengenai Islam Jawa yang sinkretis. Titik sinkretis inilah yang oleh Geertz dinamai abangan.
Namun demikian, identifikasi abangan oleh Geertz yang menjadikan tradisi slametan sebagai salah satu penanda utama itu tidaklah sepi dari kritik sarjana Barat lain. Kritik yang bersifat abstrak dan teoretis bisa kita temukan misalnya dalam Varieties of Javanese Religion: An Anthropological Account (1999) karya Andrew Beatty. Melalui konsep multivokalitas, Beatty berpendapat bahwa kelompok yang diidentifikasi sebagai abangan dan santri tidak benar-benar sedemikian tersegregasi dan dapat diidentifikasi secara jelas sebagaimana digambarkan Geertz. Kritik lain datang dari Mark Woodward dalam Islam in Java: Normative Piety and Mysticism in the Sultanate of Yogyakarta (1989). Alih-alih melihat kelompok mistisisme (yang dalam kadar tertentu juga dianggap sebagai identifikasi untuk kaum abangan) melalui cara pandang Islam normatif, Woodward melacaknya melalui naskah-naskah sufistik Islam dan berpendapat bahwa kelompok mistisisme ini absah disebut Islam Jawa, penyebutan untuk menunjukkan bagaimana Islam diartikulasikan selaras dengan budaya lokal seperti halnya Islam Maroko, Islam Gujarat, atau bahkan Islam Arab.
Adakah ‘Agama/Islam Jawa’?
Dari ulasan sejarah konstruksi makna agama Jawa dan Islam Jawa di atas, saya berpendapat bahwa ada benang merah yang sama dalam narasi-narasi itu, yakni adanya upaya mencari penanda yang distingtif mengenai ‘kejawaan’. ‘Kejawaan’ inilah yang diasumsikan hadir manifestasinya dalam praktik orang Jawa ketika memeluk agama (tak hanya Islam, tetapi juga agama lain) dan digambarkan seolah-olah ia memiliki pengertian yang sui generis atau mengandung substansi di dalam dirinya sendiri.
Asumsi adanya karater Jawa yang distingtif dan sui generis itu pada gilirannya melahirkan narasi tentang agama di Jawa yang menarik garis pemisah yang jelas antara ‘kejawaan’ vis-à-vis agama-agama dunia. Padahal kenyataannya praktik keagamaan di Jawa lebih cair dari itu, dan jauh lebih cair lagi dulu ketika dikotomi santri dan abangan ala Geertz belum ‘diciptakan’ (karena kini, sejak dikotomi itu menyebar, ia tak lagi sekadar deskripsi wacana, tetapi juga turut membentuk wacana dan proses identifikasi diri orang Jawa sendiri).
Slametan yang menjadi bekal Geertz untuk mengkarakterisasi aspek ‘Jawa’ dalam praktik keislaman di Jawa itu sendiri berlandaskan pada asumsi yang bermasalah: ia mengandaikan bahwa slametan bukan, atau tidak bisa menjadi, bagian dari praktik yang pada dirinya valid sebagai bagian dari praktik Islam. Di samping bahwa isi dan model dari tradisi slametan tak bisa dipisahkan dari muasal tradisi Islam di Nusantara yang dibawa para pendakwah pertama (kenduri, misalnya, tak lepas dari tradisi Persia), para praktisi slametan itu sendiri tak membuat distingsi antara abangan dan santri/putihan, karena kaum yang disebut santri oleh Geertz juga melakukan praktik slametan. Lebih dari itu, para praktisi slametan kemungkinan besar juga tidak akan terima jika praktik yang mereka amalkan ini disebut ‘sinkretis’.
Hal terakhir ini, saya berharap, bisa membawa pada satu refleksi mengenai bagaimana kajian antropologi dilakukan. Dalam konteks saat ini, deskripsi mengenai agama di Jawa harus dimulai dari penelaahan kritis terhadap narasi-narasi ‘Barat’ lama yang memperlakukan Jawa lebih sebagai objek, yang telah membekukan realitas yang sebelumnya ‘cair’, dan yang membentuk dikotomi yang hingga tingkat tertentu memiliki implikasi politis yang tak ringan.
___________________
Penulis, Gedong Maulana Kabir, adalah mahasiswa Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS), Sekolah Pascasarjana UGM, angkatan 2019.


(Asumsi adanya karater Jawa yang distingtif dan sui generis itu pada gilirannya melahirkan narasi tentang agama di Jawa yang menarik garis pemisah yang jelas antara ‘kejawaan’ vis-à-vis agama-agama dunia. Padahal kenyataannya praktik keagamaan di Jawa lebih cair dari itu, dan jauh lebih cair lagi dulu ketika dikotomi santri dan abangan ala Geertz belum ‘diciptakan’ (karena kini, sejak dikotomi itu menyebar, ia tak lagi sekadar deskripsi wacana, tetapi juga turut membentuk wacana dan proses identifikasi diri orang Jawa sendiri).
Tulisan pendek yang bagus. Sedikit komentar tentang buku Geertz, yang dalam penerbitan paling mutakhir diterjemahkan judulnya sebagai “Agama Jawa” (KOBAM), terutama berkaitan dengan paragraf yang saya kutip diatas. Menurut pendapat saya Geertz, sejauh yang bisa saya baca dari bukunya yang asli, “The Religion of Java” sudah sangat hati-hati menjelaskan pada calon pembacanya, bahwa menguraikan apa yang dia teliti sebagai “agama Jawa” sesungguhnya merupakan upaya yang tidak mudah karena kompleksitasnya, jika dia kemudian mengajukan beberapa temuan, antara lain mengenai “santri”, “abangan” dan priyayi”, itu harus juga dilihat sebagai upayanya untuk mendekati realitas yang kompleks itu. Dugaan saya, banyak orang sesungguhnya tidak membaca buku Geertz dengan teliti; bahkan mungkin tidak sedikit yang mungkin belum membacanya, yang kemudian menelan mentah-mentah selah-olah “trikotomi” itu sebagai sesuatu yang kaku, otonom, tidak berhubungan satu dengan lainnya secara cair. Sekali lagi selamat dengan tulisan yang bagus ini.
Terimakasih atas catatan berharganya mas.
Ya, saya sepakat soal itu. Thick description Geertz memang luar biasa. Misalnya, dalam kasus soal santri, dia mengeksplorasi perbedaan pandangan santri modernis dan santri tradisionalis. Dia secara detail menjelaskan praktik-praktik harian santri selama ramadhan dan idul fitri. Perbedaan keduanya sangat kentara. Bahkan, Geertz juga sempat merekam olok-olokan antara santri modernis dan tradisionalis. Sampai di titik ini, saya tentu sepakat bahwa realitas itu begitu cair. Dan tentu saja, santri bukanlah satu entitas yang homogen. Meski demikian, ketika dia membuat kesimpulan soal santri, tampak justru mereduksi kedalaman dan kekayaan deskripsinya sendiri.