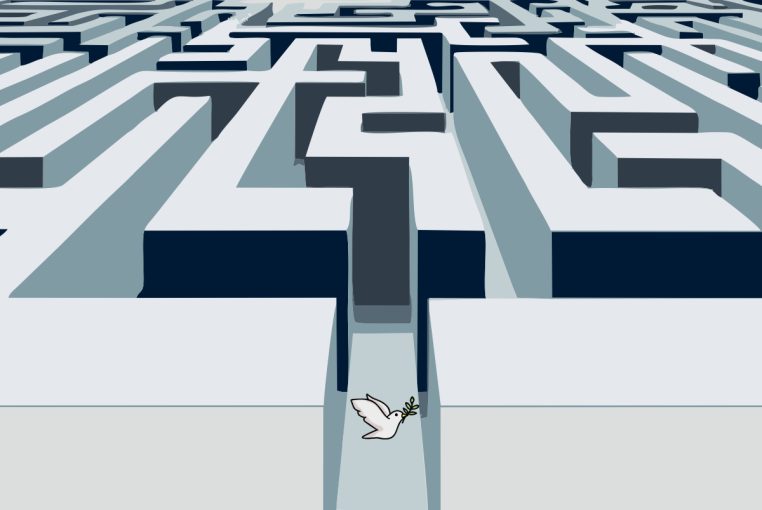
Januari 2023 silam, KUHP baru telah disahkan dan efektif diberlakukan pada Januari 2026 nanti. Ada beberapa perubahan signifikan dalam pasal-pasal terkait agama yang dianggap sebagai kemajuan, di antaranya bersandingnya kata kepercayaan dengan agama dan hilangnya frasa “penodaan agama.” Walaupun begitu, KUHP baru masih dipandang bermasalah oleh pegiat HAM dan pakar hukum pidana karena masih kental dengan semangat untuk melindungi agama atau kepercayaan itu sendiri dibanding semangat untuk melindungi manusia dan manifestasi keberagamaan atau kepercayaannya. Dengan kata lain, KUHP baru masih melindungi agama bukan individu. Implikasinya, kelompok rentan akan tetap rentan selama yang dilindungi adalah agama atau kepercayaannya bukan individunya. Dengan demikian, membaca KUHP baru dengan perspektif kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) menjadi penting untuk melindungi hak-hak individu dan ekspresi keagamaan atau kepercayaannya—alih-alih menjadi alat kepentingan kelompok mayoritas. Dengan demikian, dampak bias penafsiran pasal-pasal dari KUHP baru yang potensial menyasar kelompok rentan dapat diminimalkan.
Bersandingnya kata agama dengan berkeyakinan menunjukkan perspektif yang inklusif (lihat “Agama dalam KUHP: Kemajuan Setengah Jalan“). Selama ini, frasa “agama” kerap merujuk hanya pada enam agama mapan yang telah difasilitasi oleh negara. Masuknya kata “kepercayaan” menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberadaan keyakinan lain selain enam agama itu, khususnya kepercayaan atau agama-agama leluhur. Artinya, kepercayaan (lokal) juga mendapat perlindungan setara. Kedua, hilangnya frasa “penodaan agama” dianggap sebagai kemajuan karena dalam sejarah penerapannya, kelompok rentanlah yang seringkali menjadi sasaran pasal ini atas nama melindungi kerukunan beragama. Akan tetapi, hilangnya kata “penodaan agama” dalam KUHP baru tidak serta-merta menghilangkan substansinya, yaitu perlindungan terhadap agama/kepercayaan, yang umumnya lebih berpihak pada pandangan mayoritas atau yang dianggap mempunyai otoritas.
Dari perspektif hukum, para pakar hukum pidana menilai bahwa walaupun ada kemajuan dibanding KUHP yang lama, pasal-pasal keagamaan dalam KUHP baru tetap bermasalah karena potensial menjadi “pasal karet” yang mudah menjerat kelompok-kelompok rentan. Pasal-pasal karet ini akan mudah ditafsirkan berdasarkan kepentingan kelompok-kelompok intoleran. Pasal karet adalah pasal-pasal yang mengandung unsur-unsur tidak jelas atau menimbulan putusan hakim yang berbeda-beda dari pasal yang sama karena tafsir yang berbeda. Adanya pasal karet ini, menurut Asfinawati, terlihat dari lenturnya definisi agama serta menjadikan agama sebagai subjek hukum (lihat “Mengupas Pasal Karet terkait KBB dalam KUHP Baru”). Menurutnya, agama tidak mempuyai wujud sehingga tidak bisa menjadi objek tindak pidana. Selain itu, Asfinawati melihat ada banyak frasa dalam pasal-pasal KUHP 2023 yang bermasalah. Misalnya pada pasal 302 yang memuat tentang larangan menghasut untuk menjadi “tidak beragama atau berkepercayaan.” Selain kata “menghasut” bersifat multitafsir, pasal ini juga memaksa orang untuk beragama. Beragama menjadi sebuah kewajiban alih-alih sebagai hak. Padahal, UUD 1945 menempatkan beragama atau berkeyakinan sebagai hak yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara, bukan kewajiban yang harus dipaksakan.
Berkaca dari fenomena tersebut, perspektif KBB dalam memahami KUHP penting untuk diperjuangkan. Terkait pengelolaan keberagaman keagamaan, terdapat dua pendekatan yang mapan digunakan di Indonesia. Pendekatan mapan itu adalah “kerukunan beragama” yang pernah diterapkan oleh Orde Baru dan pendekatan “moderasi beragama” yang diimplementasikan oleh baru-baru ini oleh Kementerian Agama. Dua pendekatan tersebut ini kurang bisa melindungi setiap warga negara karena kentalnya kontrol negara dan keperpihakannya pada kelompok-kelompok mayoritas.
Paradigma KBB bukanlah hal baru atau berasal dari luar Indonesia. Ia mengakar kuat dalam tubuh dasar negara Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Jaminan konstitusional dan legal terhadap hak individu dalam beragama atau berkeyakinan diperkuat oleh TAP MPR nomor XVII/1998 mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dan UU no. 39/1999 tentang HAM, dilanjutkan dengan amandemen UUD 1945 dengan ditambahkannya bab khusus tentang HAM yang terkait dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dengan kata lain, konstitusi negara Indonesia mengakui kebebasan beragama atau berkeyakinan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Sayangnya, dalam penerapannya negara condong melindungi kelompok agama, terutama yang mayoritas atau dianggap otoritatif, yang secara politis memang lebih menguntungkan kekuasaan.
Berkaca dari berbagai fenomena tersebut, CRCS melakukan beberapa rangkaian kegiatan yang bertujuan memperkenalkan paradigma alternatif baik dalam pembacaan pasal-pasal KUHP baru maupun dalam pengelolaan keragaman beragama dan berkeyakinan, selain pendekatan yang telah mapan digunakan. Di antara kegiatan itu ialah rangkaian kegiatan lokakarya advokasi KBB di berbagai daerah dan berbagai universitas yang menghadirkan para dosen atau pengajar. Di samping itu, penting juga untuk melakukan penguatan kepada kelompok keagamaan yang rentan terdampak pasal-pasal dalam KUHP baru.
Salah satu poin penting dari rangkaian kegiatan itu ialah KUHP baru ini masih condong untuk melindungi tersangka, terpidana, dan terdakwa alih-alih melindungi korban dan saksi. Dengan kata lain korban tidak mendapatkan perhatian dalam hukum pidana terkait agama ini. Dalam perkara keagamaan, seringkali korbanlah yang menjadi tersangka karena posisinya yang rentan. Kerentanan ini berasal dari relasi kuasa yang tidak seimbang karena beberapa faktor, diantaranya: posisi dan jabatan, agama (mayoritas-minoritas), gender (laki-laki-perempuan), tingkat pendidikan, etnisitas, lokalitas (asli-pendatang), usia, dan abilitas (Eddyono, 2025).
Sosialisasi dan penguatan pemahaman mengenai pasal-pasal keagamaan dalam KUHP baru dengan perspektif KBB tidak bertujuan menjadikan jalur hukum sebagai tindakan yang utama dalam penyelesaian konflik-konflik keagamaan, tetapi untuk menyadarkan banyak pihak bahwasanya beragama atau berkeyakinan dan memanifestasikannya adalah hak individu yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara dan warga negara. Namun, ini tidak berarti bahwa individu mempunyai kebebasan tak terbatas dalam memanifestasikan haknya keagamaannya. Hak-hak itu akan terbatasi oleh hak orang lain dan negara perlu membatasi hak tersebut untuk melindungi hak orang lain tanpa melanggar hak yang bersangkutan (lihat Membatasi tanpa Melanggar). Eddiyono (2025) menyarankan agar penggunaan jalur hukum ditempuh sebagai jalan terakhir (ultimum remidium) mengingat dampak material dan psikologisnya yang begitu besar sehingga restorasinya tidak mudah. Untuk itu, kita memerlukan advokasi terhadap alternatif-alternatif resolusi konflik yang bisa digunakan. Salah satu yang diadvokasi oleh CRCS adalah penguatan jaringan dan pendekatan interseksionalitas, selain penguatan pemahaman terhadap pasal-pasal KUHP baru dan sosialisasi paradigma KBB. Mengingat masih kuatnya kontrol negara terhadap kehidupan beragama atau berkeyakinan, pergeseran paradigma dari kerukunan dan moderasi beragama ke kebebasan beragama atau berkeyakinan tampaknya masih perlu menempuh perjalanan jauh dan berliku.
______________________
Najiyah Martiam adalah alumnus Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS), Sekolah Pascasarjana UGM, angkatan 2006. Baca tulisan Najiyah lainnya di sini.
Artikel ini merupakan salah satu usaha CRCS UGM untuk mendukung SDGs nomor 4 tentang Pendidikan Berkualitas dan nomor 16 tentang Perdamaian, Keadilan, dan Pelembagaan yang Tangguh.

