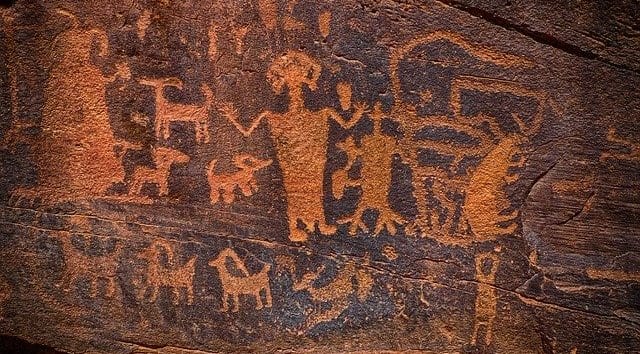
Problem Representasi dalam Animisme Baru
Zulfikar RH Pohan – 5 Mei 2020
Apa itu animisme? Bila mengikuti narasi antropolog yang pertama kali mengonstruksi maknanya, yakni Edward B Tylor dalam bukunya Primitive Culture (1871), pengertian animisme cukup sederhana: kepercayaan akan adanya ‘roh’ (anima) atau kekuatan supranatural di dalam ‘benda-benda’ seperti batu, pohon, sungai, gunung, dst; dan ‘roh’ itu diyakini memengaruhi nasib hidup manusia dan karena itu ‘disembah’.
Dalam kesarjanaan mutakhir, narasi seperti ini sudah banyak dikritik, paling tidak karena dua alasan, yakni (1) perspektifnya yang evolusionis dan esensialis, sehingga menyederhanakan ekspresi keberagamaan yang bermacam bentuknya; dan (2) paradigma yang mendasarinya bias cara pikir modern, yang pada praktiknya menjustifikasi ‘misi pemeradaban’ oleh para kolonial dan misionaris di dunia ‘Timur’. (Lebih detail tentang problem ini, baca tulisan kawan saya di web CRCS ini: Asal Mula Teori Animisme dan Masalahnya)
Mengkritik paradigma yang bermasalah dari animisme klasik itu, sejumlah sarjana belakangan mengajukan paradigma yang lain dan menyebutnya dengan animisme baru (new animism). Para pelopornya antara lain Irving Hallowell melalui gagasannya tentang personhood dan Nurit Bird-David melalui idenya tentang epistemologi relasional. Kritik dari dua sarjana ini mengubah paradigma animisme lama tentang ‘benda’ (akibat dari paradigma dualis Cartesian) menjadi ‘person’ (kemudian disebut sebagai ‘paradigma agama leluhur’), dan menjelaskan relasi antara manusia dan pohon, misalnya, bukan sebagai relasi penyembahan, melainkan relasi dividual antara dua person, yakni human person (manusia) dan non-human person (pohon).
Kajian antropologi agama mutakhir melihat gagasan tentang animisme baru ini lebih inklusif terhadap agama lokal yang sistem kepercayaannya berjalin integral dengan lingkungan tempat tinggalnya. Dalam kajian ekologi, gagasan ini juga dipandang sangat penting perannya dalam pelestarian alam.
Akan tetapi, apakah animisme baru ini bisa seutuhnya lepas dari masalah yang diidap oleh animisme lama? Persoalan ini dibahas dalam salah satu kelas dalam mata kuliah Indigenous Religions di CRCS UGM yang diampu oleh Dr Samsul “Anchu” Maarif.
Masalah keterwakilan
Problem utama yang rentan masih membayangi animisme baru ialah seberapa akomodatif ia pada pelbagai ekspresi keberagamaan agama-agama lokal. Bila masalah ini tak teratasi, meski dilandasi paradigma yang berbeda dan lebih inklusif, animisme baru masih rawan jatuh pada lubang yang sama dengan animisme lama.
Di antara yang memproblematisasi konsep animisme itu ialah Darryl Wilkinson dalam artikelnya Is There Such a Thing as Animism? (2017). Wilkinson menempatkan animisme sebagai istilah metodologis, alih-alih sebagai istilah yang sepenuhnya merefleksikan peribadatan dan tata laku agama lokal. Ia mengajukan pandangan bahwa konsep animisme baru itu sukar dipakai untuk membaca hubungan yang terjadi pada komunitas agama lokal tertentu yang memiliki konsep tentang patung dan azimat. Perbedaan yang penting di sini ialah, berbeda dengan pohon dan sungai, patung dan azimat tidak memiliki poros ekologis. Kepercayaan lokal mengenai patung dan azimat biasanya dikaji melalui konsep ‘fetisisme’.
Salah satu pengejawantahan konkret dari fetisisme ini, dalam contoh yang diajukan Wilkinson, ialah ritual komunitas Inka di Amerika Latin yang membalsem mayat agar awet dan menyakralkan bangunan-bangunan suci tempat penyimpanan mayat-mayat itu. Dalam kepercayaan masyarakat Inka, memberikan penghormatan kepada mayat yang diawetkan dipercayai akan memberkahi kehidupan sosial dan mempunyai peran bahkan dalam jalannya keadilan. Di sinilah, bagi Wilkinson, letak kekuatan fetis yang setara dengan kekuatan alam pada paradigma agama lokal.
Kealpaan dalam membaca fetisisme dan unsur lainnya dalam agama lokal ini menurut Wilkinson berangkat dari kesalahan dalam menafsirkan metafora-metafora yang dipakai komunitas agama lokal tertentu. Wilkinson dan Irving Hallowell sama-sama membicarakan batu, tetapi dengan pemahaman yang berbeda. Dalam studi mengenai orang Inka, Wilkinson membahas waq’as (para antropolog melihatnya sebagai batu, tetapi orang Inka tidak menganggap waq’as adalah batu) yang dikeramatkan oleh orang Inka. Para antropolog yang mengikuti paradigma animisme baru menggolongkan waq’as sebagai person non-manusia. Hallowell misalnya menggolongkan batu sebagai person dalam pandangan masyarakat Ojibwe di Kanada.
Namun, berbeda dengan Hallowell, Wilkinson ingin melihat lebih dalam: benarkah konsep person sendiri diyakini orang Inka? Menurut Wilkison, waq’as bukanlah sebagaimana person atau subjek yang setara sebagaimana dalam relasi personhood ala animisme baru. Waq’as adalah lambang yang digunakan sebagai medium ritual bagi orang Inka, dan tidak dipandang sebagai person. Menurut Wilkinson, jika orang Inka mengatakan ‘batu (ini) adalah teman’, itu adalah metafora, yang dibaca sarjana animisme baru dengan cenderung tekstual. Di sinilah persisnya letak problem yang diajukan Wilkinson: apakah animisme baru mewadahi sistem kepercayaan masyarakat Inka yang demikian ini?
Tantangan dinamika sejarah
Problem representasi itu akan kian tampak jika kita melihat begitu beragamnya ekspresi agama lokal dengan berpijak pertama-tama pada praktik-praktik agama lokal itu sendiri. Buku Animism in Southeast Asia (ed. Arhem & Sprenger, 2015), misalnya, menyoroti kepelbagaian ini dan mengundang pertanyaan dasar: apakah paradigma animisme baru itu bisa dipakai pukul rata untuk membaca semua kepercayaan dan praktik agama lokal? Pada kenyataannya, ekspresi agama lokal bermacam-macam jenisnya. Ada yang sebagian bisa dibaca dengan perspektif epistemologi relasional ala animisme baru itu, yakni yang memandang hubungan manusia-alam dalam relasi yang setara (horisontal) dan timbal balik. Akan tetapi tak sedikit pula yang memandang relasi manusia-alam secara hierarkis, antara lain seturut perjumpaan mereka dengan agama-agama dunia. Di beberapa komunitas agama lokal, entitas non-human person itu bahkan dipandang mempunyai kekuasaan lebih ketimbang manusia.
Untuk menyebut satu contoh: agama lokal Parmalim di Barus bisa jadi pada masa lampau masih memandang alam di sekitarnya dalam kerangka epistemologi relasional itu. Akan tetapi sejak abad ke-20, setelah bertemu dengan agama dunia seperti Islam, Katolik, dan Kristen Protestan, pandangan dunia mereka tampak berubah menjadi hierarkis. Hal terakhir ini terimplikasikan dalam paparan Rusmin Tumanggor dalam bukunya Gerbang Agama-Agama Nusantara: Kajian Antropologi Agama dan Kesehatan di Barus (2017). Buku Tumanggor ini menyampaikan bahwa ada perubahan acuan makna dalam sistem kepercayaan di Barus ketika sebagian datu-datu Parmalim masuk Islam: Tuhan Opputta Mulajadi Nabolon sebagai penguasa tertinggi dalam kepercayaan Parmalim beserta keturunan-keturunan-Nya ‘berubah’ menjadi Allah yang Esa. Konsep kosmologinya juga berubah: Debata (Tuhan) ialah kosmos yang menciptakan manusia (dengan status sebagai mikrokosmos). Dalam kerangka ini, Tuhan berada di puncak hierarki, lalu diikuti manusia yang mempunyai posisi lebih tinggi dibanding alam. Di sini tampak pandangan-dunia ala animisme baru sulit untuk bisa dinyatakan bisa secara utuh merefleksikan sistem kepercayaan Parmalim yang sudah berjumpa agama-agama dunia.
Karena itu, satu tantangan utama bagi animisme baru ialah seberapa akomodatif ia dalam menangkap dinamika sejarah agama-agama lokal. Mungkin ada banyak agama lokal yang masih merawat pandangan-dunia sebagaimana digambarkan dalam animisme baru. Akan tetapi banyak pula agama lokal yang, karena sudah lama menjalin kontak dengan agama-agama dunia, sistem kepercayaannya sedikit banyak sudah berbeda dari pandangan-dunia para leluhur mereka.
___________
Zulfikar Riza Haris Pohan adalah mahasiswa Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS), Sekolah Pascasarjana UGM, angkatan 2019. Baca tulisan Zulfikar lainnya di sini.

