
Asal Mula Teori Animisme dan Masalahnya
Ronald Adam – 18 Sept 2019
Banyak orang hingga kini, tak terkecuali di Indonesia, baik dalam diskursus publik maupun akademis, yang dengan tanpa sikap kritis mengadopsi teori animisme sebagai konsep untuk menjelaskan kepercayaan masyarakat “primitif” tentang adanya “roh” di dalam batu, pohon, gunung, dlsb., yang kemudian “disembah” masyarakat itu.
Padahal teori animisme itu bermula dari konstruksi kesarjanaan di Barat abad 19, khususnya dalam kajian antropologi, yang kemudian dibawa ke “Timur” seiring kolonialisme. Di Nusantara, konsep ini diperkenalkan oleh sarjana Belanda Albert Kruyt ketika mempublikasikan karyanya Het Animisme in den Indischen Archiple (1906). Kruyt sendiri adalah seorang misionaris Kristen Calvinis yang juga menulis karya berjudul The Presentation of Christianity to Primitive Peoples: The Toradja Tribes of Central Sulawesi (1915).
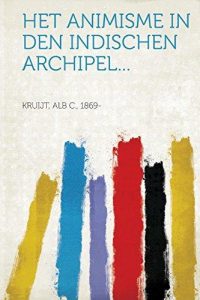
Teori animisme ini belakangan mendapat kritik yang cukup luas dari kesarjanaan mutakhir studi agama dan antropologi karena sifatnya yang esensialis dan bias paradigma modern. Terlepas teori animisme itu benar atau tidak, pada kenyataannya ia bisa memberikan justifikasi bagi proyek “pemeradaban”: bahwa masyarakat primitif dengan kepercayaan animisnya belum beradab, maka perlu diperadabkan. Apa yang disebut modernisasi, dalam narasi kolonial awal abad 20, hingga tingkat tertentu tak lain adalah upaya mengonversi masyarakat yang disebut animis itu agar memeluk agama-agama dunia (lebih khusus lagi agama-agama monoteis) yang dipandang “modern”. Teori animisme ini, beserta teori-teori lain dalam studi agama dan kritik-kritik terhadapnya, dipelajari di CRCS dalam mata kuliah Academic Study of Religion dengan pengajar Dr Samsul “Anchu” Maarif.
Animisme dalam paradigma evolusionis-esensialis
Pencetus gagasan tentang animisme adalah Edward B Tylor (1832-1917), yang kerap disebut sebagai bapak antropologi budaya, dan diteruskan oleh James G Frazer (1854-1941). Karya utama Tylor adalah dua jilid buku bejudul Primitive Culture (1871)—jilid pertama tentang asal muasal budaya dan jilid kedua tentang agama dalam kebudayaan primitif (animisme diulas di jilid kedua ini). Karya Frazer yang paling terkenal ialah The Golden Bough: A Study of Magic and Religion (1890) yang menguraikan hubungan antara praktik sihir dan ritual, dan konsepnya tentang “totem” memengaruhi karya psikoanalis Sigmund Freud, Totem and Taboo (1913).
Sebelum meringkas pemikiran Tylor dan Frazer, perlu kita catat dulu konteks kesarjanaan keduanya. Tylor hidup sezaman dengan Charles Darwin. Buku Primitive Culture (1871) ditulis 12 tahun setelah publikasi On the Origin of Species (1859). Karya Darwin ini turut membentuk semangat zaman (Zeitgeist) kesarjanaan paruh kedua abad 19 yang cenderung ingin menjelaskan asal muasal (origin) segala sesuatu dalam paradigma evolusionis. Bila Darwin menguraikan asal muasal dan evolusi spesies, Tylor mengulas asal muasal dan evolusi budaya dan agama. Frazer meneruskan paradigma evolusionis untuk menjelaskan asal muasal agama dan menambahinya dengan sejumlah gagasan.
Beda Frazer dengan Tylor ialah, bila Tylor tak mengenyam pendidikan tinggi formal tetapi banyak melakukan perjalanan, Frazer berpendidikan formal tapi hampir tak pernah melakukan perjalanan. Sebagian besar informasi Frazer tentang budaya di luar Eropa disuplai oleh catatan-catatan perjalanan orientalis, sedemikian sehingga Daniel Pals, penulis buku daras Eight Theories of Religion (2006), menyebut Frazer sebagai salah satu contoh intelektual “menara gading”.
Bagaimana Tylor mengulas asal muasal dan evolusi agama? Narasi ringkasnya adalah sebagai berikut.

Masyarakat berevolusi dalam tahap yang bermula dari savagery (animisme), ke barbarism (politeisme), menuju civilization (monoteisme). Pada mulanya masyarakat savage merenungkan dua hal utama: kematian dan mimpi. Kematian menandakan ketakabadian raga, sementara mimpi dipahami sebagai penanda adanya “roh” (spirit; “anima” adalah kata Latin bagi spirit) yang tetap hidup meski raga telah mati. Dari kepercayaan akan roh dalam raga ini, masyarakat savage kemudian membayangkan juga adanya roh lain dalam benda-benda; roh-roh yang kekuatannya memengaruhi roh manusia, yang bersemayam dalam batu, pohon, gunung, sungai, dlsb. Di tahap selanjutnya, masyarakat memahami roh-roh itu bukan hanya di pohon atau gunung tertentu, tetapi ada roh untuk semua pohon, roh untuk semua gunung, roh untuk semua sungai, dst. Di tahap inilah muncul “dewa-dewa” (dewa langit, dewa bumi, dewa laut, dst) yang dalam narasi Tylor menandakan peralihan ke kepercayaan politeisme. Dari kepercayaan ini, masyarakat berlanjut bahwa dari dewa-dewa itu ada Dewa Tertinggi, yang Satu, dan pada tahap ini (fase civilization), monoteisme mewujud.
Tentu saja Tylor memaksudkan narasinya ini sebagai penjelasan yang universal. Animisme baginya adalah bentuk primitif dan merupakan pondasi dari semua agama. Anima, spirit, soul, jiwa, sukma, dsb, bagi Tylor, merupakan kata yang ada padanannya lintas agama dan budaya. Bagi Tylor, semua agama bila diperas pada akhirnya akan berbagi dan mengerucut pada dua elemen esensial saja, yakni keabadian jiwa dan kehidupan pascakematian (entah dengan doktrin akhirat atau reinkarnasi). Definisi agama bagi Tylor sederhana saja, yakni “belief in spiritual beings”.
Frazer, penerus Tylor, menambahi dengan ulasan sejumlah fitur masyarakat primitif-animis itu dengan sedikit perbedaan: bila Tylor berhenti pada monoteisme, Frazer menyatakan sainslah tempat berhentinya. Narasi evolusionis Frazer lebih sederhana: mulai dari primitive magic, berlanjut ke agama, kemudian diganti sains.
Sama seperti Tylor, masyarakat primitif-animis mula-mula bergulat dengan pertanyaan tentang hidup dan mati. Namun, karena kekurangan pengetahuan, mereka membangun mitos. Di antara contoh mitos yang dinukil Frazer ialah kepercayaan masyarakat Zulu di Afrika Selatan. Dalam mitos Zulu, Dewa Unkulunkulu memberikan titah kehidupan abadi kepada bunglon untuk dihantarkan kepada manusia, tetapi ternyata bunglon ini jalannya lambat dan suka istirahat di perjalanan. Lalu Unkulunkulu berubah pikiran, sehingga ia ganti memberikan titah kematian, kini diberikan kepada kadal, untuk disampaikan kepada manusia. Kadal berjalan cepat dan sampai lebih dulu dari bunglon. Akhirnya setelah menerima titah kematian, manusia tertakdir untuk mati. Karena mitos ini, masyarakat Zulu menghukum bunglon dan memperbolehkan anak-anak untuk membunuh bunglon di manapun menemukannya. Dalam narasi Frazer, mitos semacam ini ada di masyarakat Afrika lain—di masyarakat Ashanti, misalnya, yang berperan seperti bunglon dan kadal adalah domba dan biri-biri.
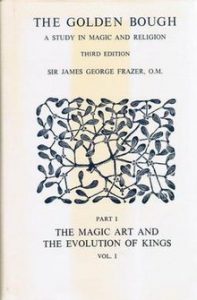
Frazer juga mengulas konsep tentang sihir dalam masyarakat primitif-animis. Menurutnya, masyarakat primitif-animis meyakini adanya “hukum” yang mengatur alam. Frazer menyebutnya dengan prinsip magis simpatis (sympathetic magic) yang terbagi menjadi dua: pertama, hukum kesamaan atau imitasi (law of similarity) yang menjadi prinsip dasar dari magis imitasi (homoeophatic atau imitative magic), dan kedua hukum kontak atau penularan (law of contact or contagion) yang menjadi prinsip dari ilmu magis penularan (contagious magic). Contohnya ada dalam praktik santet (voodoo): ketika jarum ditancapkan ke boneka jerami (sebagai imitasi) yang merepresentasilan korban dan diberi rambut (sebagai kontak) dari seseorang yang hendak disihir, santet itu akan mujarab menyakiti korban target. Kedua hukum ini kebanyakan dilakukan untuk melukai orang, tetapi dalam perkembangan masyarakat primitif-animis selanjutnya, praktik magis dilakukan para dukun guna mengendalikan cuaca untuk kepentingan pertanian. Misalnya, saat lahan pertanian kekurangan air, masyarakat primitif-animis akan melakukan ritual tarian, yang salah satu dari mereka akan meminum air dan menyemburkannya agar menyerupai hujan (hukum imitasi).
Frazer banyak mengulas contoh-contoh mitos (yang melahirkan konsep tabu dalam masyarakat) dan praktik sihir di masyarakat primitif-animis ini, seperti sesembahan untuk gunung agar tak meletus, sesembahan untuk sungai agar tak banjir, larangan menebang wilayah hutan terentu agar dewa bumi tak marah sehingga melahirkan gempa, dan seterusnya. Dan, sama seperti Tylor, Frazer memandang masyarakat primitif ini, karena kekurangan pengetahuan, memiliki nalar yang kekanak-kanakan (“childlike chain of reasoning”).
Cara pandang baru: epistemologi relasional
Narasi animisme ala Tylor-Frazer yang cukup lama memengaruhi kajian antropologi itu kini mendapat kritik. Di antaranya dari Irving Hallowell (melalui ide tentang personhood) dan Nurit Bird-David (melalui ide tentang epistemologi relasional).
Di samping kurangnya observasi yang memadai terhadap pelbagai varian kepercayaan masyarakat adat-lokal (indigenous communities), kritik mutakhir terhadap teori animisme ini ada pada sifat esensialisnya yang hendak menyamaratakan semua kepercayaan dan praktik masyarakat adat dalam narasi besar tentang asal muasal agama (yang dinarasikan secara evolusionis oleh Tylor dan Frazer). Kritik lainnya menyasar pada bias pandangan-dunia modern yang memproyeksikan paradigma dualis Cartesian antara subjek (manusia) dan objek (alam)—dan dalam paradigma ini alam sebagai objek dipandang sebagai “benda” (“thing”)—sementara masyarakat adat-lokal itu tidak memeluk pandangan-dunia semacam itu.
Gagasan Hallowell berdasar pada kajian antropologisnya terhadap komunitas adat Ojibwe di Kanada, dan dia mengajukan tesis mengenai personhood sebagai pandangan-dunia masyarakat adat. Person dalam pandangan-dunia ini bukan sekadar mencakup manusia (human person), melainkan juga alam (non-human person), dan tidak memandang non-manusia sebagai “thing”, melainkan sebagai person. Hubungan antara keduanya juga bukan hubungan antara subjek dan objek (secara individual), melainkan hubungan integral yang setara (secara dividual), yang dalam istilah Bird-David, berdasarkan kajiannya terhadap masyarakat pemburu (hunter-gatherers) Nayaka di India selatan, berlaku dalam kerangka “epistemologi relasional”.
Dalam kerangka ini, hubungan antara person manusia dan person non-manusia, yang dalam masyarakat Nayaka disebut dengan “Devaru”, bukanlah hubungan penyembahan (worship), melainkan hubungan etis, tanggung-jawab, dan timbal-balik. Keberadaan diri manusia juga tidak dipahami dalam kerangka diri-modern (melalui konsep tentang “self” yang eksis dalam dirinya sendiri) melainkan dalam hubungan (relasional) dengan person yang lain. Manusia tidak dipahami dalam eksistensi yang mandiri, melainkan dalam relasinya dengan non-manusia sebagai sesama subjek (intersubjektivitas) dan sesama person (interpersonal). Dalam penjelasan Dr Anchu, bila formula ontologis Cartesian menyatakan “I think, therefore I am”, formula epistemologis masyarakat adat-lokal ini bisa dinyatakan dengan “I relate, therefore I am”. (Lebih jauh, baca makalah Bird-David [1999]: “ Animism” Revisited: Personhood, Environment, and Relational Epistemology)
Demikian itu, kurang lebih, cara pandang baru yang ditawarkan oleh kesarjanaan antropologis modern dalam membaca apa yang oleh banyak orang disebut sebagai “animisme”. Sebagai penjelasan akademis, ia tentu akan terbuka untuk mendapat kritik lain yang hendak menawarkan cara pandang lain.
Namun demikian, kepercayaan masyarakat adat yang digambarkan secara peyoratif dengan istilah animisme itu justru kini banyak dilihat kembali khususnya dalam kajian agama dan ekologi, yang belakangan mulai menyadari efek negatif dari pandangan modern dan agama-agama dunia yang antroposentris terhadap alam, yang memandang alam semata sebagai “benda” yang ditakdirkan tunduk pada kehendak manusia. Banyak masyarakat adat memiliki kepercayaan mengenai tanah dan hutan yang sakral, yang pohon-pohonnya haram ditebang—disertasi Dr Anchu sendiri mengulas masyarakat Ammatoa di Sulawesi yang memiliki kepercayaan ini. Kepercayaan semacam ini membantu melestarikan hutan. Oleh karena itu, suatu prakarsa agama dan ekologi untuk menyelamatkan bumi kini tak bisa lagi mengabaikan pelibatan masyarakat adat dan kepercayaan lokal.
_________________
Penulis, Ronald Adam, adalah mahasiswa Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS), Sekolah Pascasarjana UGM, angkatan 2019.
Baca juga: Menyelamatkan Hutan: Aliansi Lintas Agama dan Masyarakat Adat
Jurnal kelas lain yang berkaitan: Agama (Religion) sebagai Konstruksi Modern

