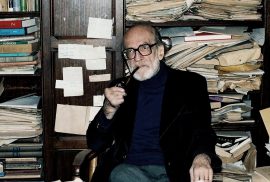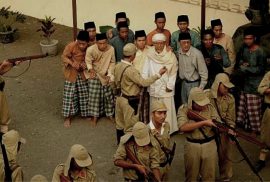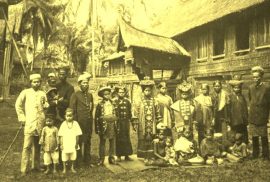Menjadi Wong Gunungkidul Bersama Komunitas Resan
Ronald Adam dan Jonathan D. Smith – 17 April 2023
Di tengah terkikisnya budaya dan tradisi lokal yang beriringan dengan krisis lingkungan, suatu kelompok di Gunungkidul bernama Komunitas Resan mencoba menguatkan kembali identitas lokal mereka sebagai “orang Gunungkidul”.
Wilayah Gunungkidul, D.I. Yogyakarta, seringkali mendapatkan stigma peyoratif sebagai tempat miskin di pedalaman yang selalu dilanda kekeringan, marginal, dan banyak kasus orang bunuh diri (pulung gantung). Di samping itu, tradisi budaya dan kearifan lokal Gunungkidul dalam memuliakan alam sering dipandang sebagai mistis atau klenik. Tak jarang, sebagian kelompok mencap mereka sebagai “penyembah pohon”.