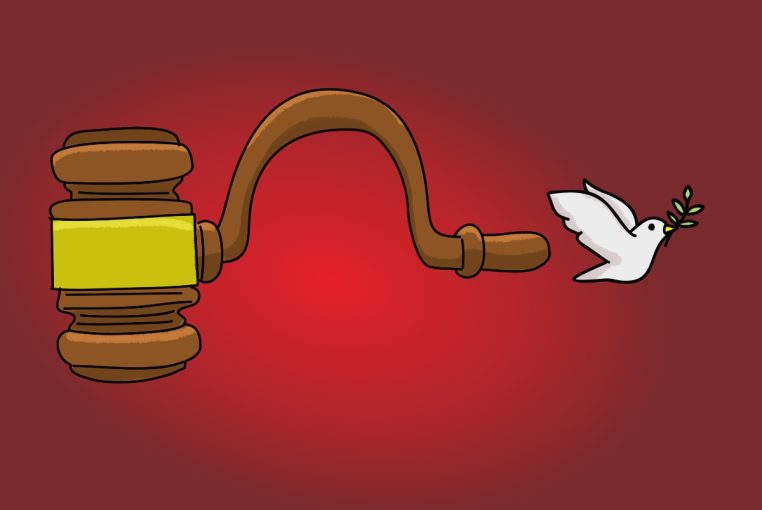
Keberadaan delik terkait agama atau kepercayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023 membawa angin segar bagi kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) di Indonesia. Namun, hukum pidana tak selalu menjadi solusi atas kasus intoleransi dan diskriminasi yang terjadi.
Setelah lebih dari seabad menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda, Indonesia akhirnya memiliki KUHP baru pada 2023. Undang-undang terkait hukum pidana di negara kita memang baru muncul pada 1946 melalui UU no. 1 tahun 1946. Akan tetapi, undang-undang tersebut merupakan hasil naturalisasi dari produk hukum kolonial Belanda yaitu Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvS).
Bagi negara-negara pascakolonial, kebutuhan KUHP baru ini bukan sekadar proyek dekolonialisasi, melainkan juga untuk memenuhi perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan tolok ukur dan pandangan kolektif masyarakat. Salah satu contohnya ialah posisi agama atau kepercayaan dalam hukum pidana. Dalam KUHP lama, tindak pidana terkait agama tidak diatur secara khusus, tetapi tersebar dalam Bab V tentang Kejahatan terkait Ketertiban Umum. Padahal, kendati bukan negara agama, agama memainkan peran vital dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia.
Di sisi lain, dengan menempatkan urusan agama atau kepercayaan dalam payung ketertiban umum, paradigma KUHP kolonial tersebut condong kepada praktik perukunan atau penertiban masyarakat. Dengan kata lain, hak-hak beragama atau berkeyakinan dapat direpresi oleh hukum atas nama ketertiban umum. Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan UUD 45 yang menempatkan kebebasan beragama atau berkeyakinan sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh negara.
Potensi KUHP 2023 untuk Memajukan KBB
Secara praktik, hukum pidana dan HAM di Indonesia seringkali dipandang sebagai dua entitas hukum terpisah. Contoh paling gamblang ialah kecenderungan persepsi bahwa pelanggaran HAM merupakan yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia. Padahal, seperti dinyatakan UU no. 26 tahun 2000, Pengadilan Hak Asasi Manusia hanya berwenang mengadili pelanggaran HAM berat yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Lebih lanjut, seperti ditunjukkan Eddyono (2024:114), dinamika HAM justru berkontribusi besar pada perkembangan hukum pidana di dunia, tak terkecuali di Indonesia.
Lantas bagaimana dengan KUHP 2023?
Keberadaan hukum pidana pada mulanya merupakan upaya untuk melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan negara. Keberadaan hukum pidana membuat negara tidak boleh lagi menghukum warganya tanpa landasan hukum yang jelas. Dengan demikian, asas legalitas menjadi salah satu asas penting dalam hukum pidana. Namun, dalam KUHP lama, asas legalitas ini justru absen disebutkan. KUHP 2023 bergerak lebih maju dengan mengedepankan asas legalitas sebagai salah satu dasar perumusan hukumnya seperti tercantum pada Pasal 1 ayat 1 dan penjelasan pengertian hukum pidana pada Pasal 12.
Dengan kata lain, tidak ada satu pun perbuatan dapat dipidana kecuali telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana. Dalam konteks kehidupan beragama atau berkeyakinan, asas legalitas ini lebih menjamin kepastian hukum karena seseorang tidak lagi dapat dipidana hanya karena status keagamaan atau keyakinan yang ia anut. Hal lain yang juga penting untuk digarisbawahi, ketika terjadi benturan antara kepastian hukum dan keadilan, yang diutamakan ialah keadilan. Alhasil, aparat hukum tidak boleh lagi memidana suatu perbuatan hanya berdasar pada pemenuhan delik pidana.
Lebih lanjut, KUHP 2023 mengatur secara khusus tindak pidana terkait keagamaan atau keyakinan dalam pasal 300–305. Seperti dibahas oleh Bagir (2023), salah satu perbedaan mencolok dari KUHP sebelumnya ialah hilangnya istilah “penodaan agama” yang justru kerap menyasar kelompok rentan. Sayangnya, penghilangan istilah tersebut secara substansi tidak sepenuhnya menghilangkan unsur penodaan agama. Selain orang/kelompok orang, KUHP baru ini masih juga menempatkan agama/kepercayaan sebagai subjek hukum yang dilindungi., Karenanya, KUHP 2023 ini masih menyisakan potensi kriminalisasi bagi warga negara, terutama kelompok rentan keagamaan.
Di sisi lain, KUHP 2023 ini juga membuka peluang pemidanaan kepada kelompok-kelompok intoleran yang melakukan persekusi dan gangguan terhadap aktivitas peribadatan/pertemuan keagamaan kelompok keagamaan/kepercayaan lainnya. Keberadaan istilah “pertemuan keagamaan” ini cukup inklusif dibanding KUHP sebelumnya karena menghindari perdebatan terkait aktivitas mana yang bisa disebut ibadat. Pasalnya, perdebatan terhadap istilah ibadat seringkali masih berperspektif agama mayoritas dan paradigma agama dunia.
Hukum Pidana: Pisau Bermata Dua
Kendati menyediakan perangkat untuk mengadili kelompok intoleran, hukum pidana tidak selalu menjadi opsi terbaik dalam menyelesaikan kasus-kasus terkait keagamaan atau kepercayaan di Indonesia. Dalam lokakarya “Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan Berbasis Komunitas” (25/2), Sri Wiyanti Eddyono mengemukakan bahwa, “Hukum pidana tidak selalu menjadi opsi terbaik, dan di Indonesia seringkali merugikan bagi kelompok rentan.”
Mengutip ada Barda Nawawi (2001), dosen Fakultas Hukum UGM ini mengemukakan lima faktor yang membuat penegakan hukum via pengadilan tidak selalu menjadi opsi terbaik. Lima hal tersebut ialah pengetahuan aparat penegak hukum terkait undang-undang, cara pandang atau keyakinan penegak hukum, kepentingan dari penegak hukum dan pihak-pihak lain, budaya institusi, serta keberadaan aturan turunan/infrastruktur hukum yang belum memadai. Dengan kata lain, “Hukum pidana itu tidak bebas nilai dan tidak selalu objektif,” jelasnya.
Di sisi lain, proses hukum pidana membutuhkan waktu panjang dan menyita tenaga, pikiran, maupun uang. Tak jarang, setelah proses pidana selesai, relasi sosial di masyarakat susah untuk direstorasi seperti semula atau bahkan muncul ketegangan baru. Padahal, pemidanaan dilakukan untuk menyelesaikan konflik akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat (Pasal 51 ayat 3). Perubahan menjadi KUHP 2023 bukan sekadar perubahan pasal dan delik melainkan juga pergeseran paradigma hukum dari yang mulanya keadilan retributif menjadi keadilan yang mengedepankan restoratif dan rehabilitatif.
“Hukum pidana itu ultimum remedium, ia adalah jalan keluar terakhir ketika cara-cara yang lain dianggap tidak berhasil,” jelas dosen yang juga pernah menjadi saksi ahli dalam kasus Meliana dan suara azan ini. Hukum pidana memang pisau bermata dua. Di satu sisi, ia dapat menjadi pendekatan represi yang dimiliki oleh aparat hukum. Di sisi lain, ia merupakan alat untuk perlindungan HAM. Oleh karenanya, ketika menggunakan hukum pidana, dampak pelanggaran HAM dan risiko advokasi perlu menjadi pertimbangan utama.
______________________
m rizal abdi adalah alumni Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS), Sekolah Pascasarjana UGM, angkatan 2015. Baca tulisan abdi lainnya di sini.
Artikel ini merupakan salah satu usaha CRCS UGM untuk mendukung SDGs nomor 4 tentang Pendidikan Berkualitas dan nomor 16 tentang Perdamaian, Keadilan, dan Pelembagaan yang Tangguh.

