
Rawls, Agama, dan Nalar Publik
Refan Aditya – 11 Oktober 2022
Bagaimana mungkin mereka yang berpegang pada doktrin agama tertentu, dan otoritas agama tertentu, di saat yang sama berpegang pada konsep politik liberal yang mendukung rezim demokratis? (Rawls 2000, hlm. 149)
John Rawls bertanya demikian sebab dalam sebuah masyarakat demokratis, idealnya, tidak ada entitas yang boleh dikecualikan tanpa alasan, termasuk agama. Demokrasi yang disokong oleh konsep politik liberalisme mengandaikan sebuah tatanan masyarakat yang berpegang teguh pada kebebasan, kesetaraan, dan hak-hak sipil (equality before the law). Tatanan itu diikat dalam kontrak sosial yang mengatur batas dan distribusi yang setimpal; fair. Maka agama, supaya mendapat haknya di ruang publik, mau tak mau mesti mengikuti prosedur demokrasi yaitu konsensus politik. Artikel ini membahas posisi agama di ruang publik dalam pemikiran politik John Rawls. Pertama-tama, penting untuk memahami terlebih dulu “kelabilan” pemikiran Rawls tentang konsep politik justice as fairness.
Rawls dan Revisi-revisinya
Meski lahir dan besar dalam tradisi filsafat politik kontrak sosial, John Rawls (1921-2002) mengkritik tren pemikiran pendahulunya, terutama teori kontrak sosial klasik Lockian, yang terlalu mematok keutamaan pada manfaat bagi kelompok dengan jumlah terbanyak. Pemikiran yang dikenal luas dengan nama utilitarianisme ini memiliki diktum the greatest benefit for the greatest number of people. Di ekstrem lain, Rawls juga menendang tren filsafat politik yang melulu merujuk nurani sebagai standar moral justifikasi keutamaan (ethics virtue)—yang berkiblat pada moralitas Kantian. Ide ini dikenal dengan intuisionisme. Bagi Rawls, justifikasi moral semata tidak memadai untuk mencapai sebuah konsensus bersama karena majemuknya preferensi moral dalam sebuah masyarakat. Karenanya, Rawls beranjak lebih jauh. Setidaknya, ada tiga buku utama Rawls yang merekam lini masa perjalanan intelektualnya.
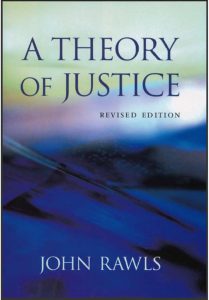
A Theory of Justice (1971) menjadi manifesto filsafat politiknya yang, sampai kini, masih kental mewarnai diskursus teori keadilan. Membicarakan keadilan dalam filsafat politik hari ini tidak bisa meninggalkan buah pikiran Rawls. A Theory of Justice berbicara tentang keadilan sebagai ‘kesetimpalan’—Justice as Fairness. Pada prinsipnya, fairness mencakup kebebasan, kesetaraan, dan kesamaan kesempatan dalam posisi asali. Dalam konteks politik, Rawls percaya keadilan dapat dicapai dengan prasyarat ini. Masyarakat yang tengah bermufakat mesti masuk ke dalam posisi asali dengan mengubur kepentingan terselubungnya dan menyetarakan diri terlebih dahulu. Dengan begitu, bagi Rawls, maka akan tercapailah keadilan ekonomi dan keadilan sosial yang fair.

Telaahnya tentang keadilan mendapat kritik karena kurang memberikan perhatian pada pluralitas publik. Ini mendorongnya untuk menguji dan menganggit kembali teori keadilan. Political Liberalism (1993) adalah pengejawantahan dari A Theory of Justice-nya dalam ranah konstitusi, politik, dan negara. Dalam buku ini, Rawls membicarakan sekaligus menguji bagaimana legitimasi politik dan pokok-pokok konstitusi dapat diasalkan dari konsep politik tentang keadilan di tengah himpunan konsep-konsep tentang keadilan dalam masyarakat. Ini yang, menurut saya, membuat Rawls otentik. Alih-alih berambisi memformulasikan sebuah tatanan ideal yang baku dan tahan lama seperti teoritikus-teoritikus politik liberal pendahulunya, Rawls mengusulkan konsepsi politik liberal yang berpijak dari fakta pluralnya konsep-konsep politik demokratis dalam suatu masyarakat. Karenanya, konsepsi ini harus senantiasa terbuka bagi penyelidikan-penyelidikan rasional dan dapat diterima secara publik melalui reflective equilibrium—sebuah interupsi demi kesetimbangan.
Rawls adalah seorang liberal dalam pengertian yang berbeda. Ia menekankan pentingnya fungsi public reason atau ‘nalar publik’ dalam merumuskan sebuah nilai-nilai konstitusional atau konsensus. Konsep ini mengandaikan bahwa setiap warga negara memiliki kapasitas untuk terlibat dan diperhitungkan dalam percakapan politik dan publik dengan ketentuan-ketentuan rasional yang dapat diterima bersama, yang mengutamakan kemampuan berargumen secara fair tanpa ada tendensi dominatif satu terhadap yang lain.
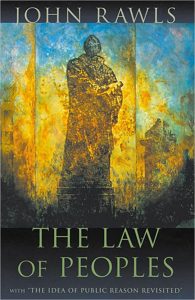
Fakta bahwa John Rawls rajin merevisi pandangannya ini menunjukkan komitmennya pada keterbukaan dan pencarian kebenaran yang tak pernah usai. Di penghujung usia, Rawls menerbitkan The Law of Peoples (1999) yang berisi tinjauan ulang atas beberapa esainya di John Rawls: Collected Paper (1999) dan satu revisi tajam atas gagasan nalar publiknya, “The Idea of Public Reason Revisited” (1997). Dalam revisi ini, Rawls memberi catatan khusus tentang posisi agama di ruang publik. Berbeda dari karya-karya sebelumnya yang fokus pada konsep politik liberal, nilai-nilai konstitusional, dan teori keadilan, The Law of People menyorot peran warga publik dalam merumuskan sebuah konsep liberalisme untuk tatanan sosial demokratis yang ideal. Agama, bersama dengan sekularisme dan doktrin nonreligius lainnya terhitung dalam rumpun doktrin yang diterima nalar. Nalar siapa? Tentu saja nalar publik.
Agama dan Nalar Publik
Menarik dicatat, dalam sistem filsafat politiknya—dari Justice as Fairness hingga Political Liberalism—Rawls tidak terlalu memberikan perhatian pada agama. Agama, terutama di ruang privat, hanya dibahas sejauh sebagai doktrin baku, sebagaimana halnya aliran-aliran pemikiran yang ia kategorikan dengan “sekularisme” seperti marxisme, komunisme, feminisme, dan liberalisme yang bersandar pada suatu pandangan filsafat tertentu. Posisi agama di ruang publik baru mendapat perhatian khusus di “Idea of Public Reason Revisited”.
Menurut Rawls, agama baru memiliki justifikasi secara publik dan boleh “dihitung” dalam arena politik ketika ia memiliki nalar publik. Sebelum diterima dan diperhitungan dalam arena politik dan publik, agama hanya tinggal sebagai doktrin komprehensif (comprehensive doctrine) di ruang privat pemeluknya. Namun, ketika agama mampu menawarkan argumen yang dipandang sesuai dengan konsep politik keadilan yang berlaku di ruang publik tanpa mencederai badan doktrin atau ajarannya sendiri, barulah agama tersebut menjadi reasonable comprehensive doctrine . Dengan demikian, untuk mendapat hak konstitusional demokratis atau hak politik, agama harus mampu memberikan argumentasi publik dari doktrin komprehensifnya sendiri.
Akan tetapi, menurut Rawls, suatu doktrin tidak bisa dikatakan sebagai reasonable jika doktrin itu berkompromi dengan konsep politik liberal atau rezim demokratis melalui modus vivendi atau kesepakatan sementara untuk hal-hal praktis, misalnya dalam rangka menjaga kerukunan dan menghindari konflik. Rawls memberi contoh kasus Katolik dan Protestan di abad ke-16 dan ke-17 ketika prinsip toleransi dijunjung sebagai modus vivendi. Kompromi ini semata dibangun untuk menghindari konflik agama dan menjaga stabilitas sosial—agar kedua institusi keagamaan ini tidak saling menjatuhkan manakala memperoleh kuasa politik. Modus vivendi dalam contoh ini memang menjamin kebebasan beragama dan harmoni. Namun, bagi Rawls, ini bukanlah konsensus yang hendak dituju oleh nalar publik yang berkomitmen penuh pada ideal dan cita-cita masyarakat demokratis.
Sebaliknya, Rawls juga tidak menghendaki masyarakat demokratis dengan nalar publik yang menerima secara buta konsensus, sementara agamanya sendiri dibatasi atau bahkan terancam. Prinsip toleransi hanya dapat dihitung sebagai nalar publik sejauh ia diturunkan dari argumentasi resiprokal yang fair. Karenanya, fundamental bagi setiap doktrin untuk menggugat konstitusi manakala eksistensinya terancam dan terpinggirkan. Tentu jika ia punya nalar publik.
Lantas, bagaimana caranya agar agama tertentu mendukung rezim konstitusi meskipun comprehensive doctrine-nya tidak mendapat tempat atau bahkan ditolak secara politik dan publik?
Ada dua “jalan” agar agama dapat mendapat tempat di ruang publik. Yang pertama murni politik, dengan menawarkan argumentasi yang sesuai dengan konsep politik tentang keadilan yang berlaku dan diterima publik. Argumen kedua tidak murni politik yang diturunkan dari dalam tubuh doktrin agama itu sendiri. Rawls menyebut argumen ini dengan reasoning from conjecture—berargumen melalui premis-premis doktrin dan berusaha untuk menunjukkan bahwa doktrin komprehensif yang mereka pegang secara intrinsik mengandung nalar publik dan seiya dengan konsep politik tentang keadilan yang berlaku dan diterima publik.
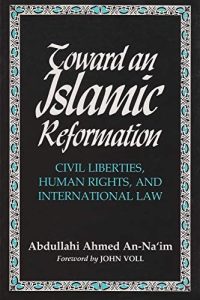
Gagasan Abdulla Ahmed an-Na’im dalam Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law (1990) tentang pemberlakuan hukum Islam menjadi contoh reasoning from conjecture bekerja dalam konteks agama Islam. Menurut Na’im, sebagaimana dikutip Rawls, ajaran Islam pada dasarnya mendukung demokrasi konstitusional dan pro hak asasi manusia. Interpretasi terhadap ajaran Islam p ada periode Mekkah menunjukkan bagaimana Islam menjunjung prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan kebebasan penuh untuk memilih agama dan keyakinan. Keduanya selaras dengan prinsip konstitusional “kesetaraan mendahului hukum”. Meski al-Qur’an tidak menyebut konstitusionalisme, pemikiran rasional manusia menunjukkan bahwa konstitusionalisme adalah niscaya bagi terciptanya keadilan dan masyarakat yang ideal sebagaimana diserukan Al-Qur’an. Maka, agama harus diterjemahkan, menggunakan bahasa Na’im, dalam bentuk civic reason—public reason versinya.
Nah, komitmen pada kesetaraan dan antidiskriminasi inilah yang menjadi dasar justifikasi publik agama. Rasionalisasi Islam terhadap konstitusionalisme ini adalah bentuk nalar publik yang merupakan wujud reasoning from conjecture dari doktrin agama Islam. Dalam contoh lain, Rawls menulis, “In endorsing a constitutional democratic regime, a religious doctrine may say that such are the limits God sets to our liberty.” Pada contoh ini, Tuhan (sebagai personifikasi dari doktrin) diyakini telah membatasi diri (kuasa)-Nya untuk kebebasan manusia dalam mengurus urusan publik-nya—dalam hal ini penyelenggaran negara. Pada prinsipnya, jika ingin tetap “dihitung” sebagai doktrin yang diterima secara publik, agama tidak boleh membatalkan doktrinnya sendiri demi sebuah konsensus, tetapi harus melalui upaya public reasoning. Agama—maupun paham sekuler—mesti memberikan justifikasi publik berupa argumentasi atau nalar publik atas doktrinnya sendiri dengan berpijak pada budaya politik demokrasi yang ada, sebagaimana juga dengan doktrin-doktrin lain, untuk menciptakan konsensus yang saling melengkapi (overlapping consensus).
Rawls Dikritik
Meski telah melakukan revisi dan penyempurnaan atas beberapa pandangannya, Rawls tetap tidak kebal kritik. Salah satu kritik atas pandangan liberalisme politik Rawls datang dari neo-marxist Chantal Mouffe (1943-sekarang). Tentang kritik Mouffe ini, tengok “Pluralisme Agonistik: Menimbang Ulang Konsensus dan Hegemoni dalam Demokrasi” . Secara garis besar, kritik yang dialamatkan kepada Rawls adalah kecenderungannya untuk bertumpu semata pada kemampuan rasional dan mengabaikan aspek hasrat dan emosional publik/warga negara dalam mewujudkan kesetiaan pada nilai-nilai konstitusi. Kritik inilah yang kemudian menstigma gagasan liberalisme Rawls sebagai sesuatu yang naif, utopis, dan tidak memberi ruang pada kelompok yang “gagal” melakukan public reasoning. Oleh karenanya, nalar publik Rawls mengabaikan sisi antagonistis dalam konsensus liberalisme politiknya yang dapat berakibat pada eksklusi pihak-pihak yang “kalah” dalam arena nalar publik dan pelanggengan hegemoni yang tersembunyi di balik konsensus. Bagaimana pun, dalam mengkritik Rawls, Mouffe datang dengan sudut pandang yang berbeda, bahkan bertentangan. Mouffe hadir dengan perspektif neo-marxisme yang mengedepankan dialektika oposisional yang sarat konflik, sementara perspektif liberalisme Rawls mengutamakan tatanan demokratis pluralis yang ideal.
______________________
Refan Aditya adalah mahasiswa Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS), Sekolah Pascasarjana UGM, angkatan 2022. Baca tulisan Refan lainnya di sini.


Maaf admin, izin berntanya. Jika kita ingin mengirim tulisan untuk di publish di website CRCS apakah bsa dan ada syaratnya? terimakasih