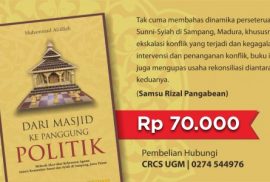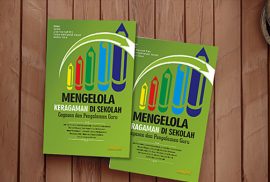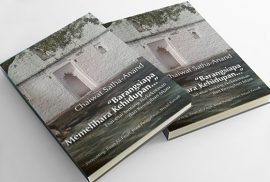Dhamma Yudha: Bunyi Genderang Perang Buddhisme Militan
Candra Dvi Jayanti – 1 Februari 2024
Bertolak belakang dengan citra agama Buddha yang penuh kedamaian dan nirkekerasan, negara-negara dengan mayoritas buddhis justru terlibat dalam kekerasan komunal—dan promotor kekerasan itu ialah para biksu.
Demikianlah Peter Lehr membuka pembahasan terkait Buddhisme dan kekerasan dalam bukunya Buddhisme Militan: Bangkitnya Kekerasan Agama di Sri Lanka, Myanmar, dan Thailand. Melalui penelusurannya di tiga negara dengan mayoritas buddhis, Lehr berupaya mencari jawaban atas pertanyaan: bagaimana sebuah agama yang bercorak nonkekerasan menjelaskan, membenarkan, bahkan mempromosikan jalan kekerasan? Yang menarik, ketiga negara yang menjadi representasi kasus tersebut berbasis Theravada, aliran yang berusaha memegang teguh ajaran awal Buddhisme terutama pada aturan kebiksuan (vinaya).