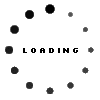“Setelah doa subuh, umat muslim selalu pergi ke kedai kopi pecinan untuk minum kopi di sana. Alasannya sederhana, hanya kedai kopi itulah yang buka sedari pagi buta”
Begitulah kira-kira gambaran relasi antaretnis dan agama yang terjadi dalam masyarakat Makassar. Kedai kopi yang dianggap sekadar tempat transaksi ekonomi, ternyata menjadi ruang penting terciptanya sebuah dinamika relasi lintas etnis dan agama yang sarat akan luka masa lalu. Ruang seperti kedai kopi menjadi salah satu ruang vital menciptakan stabilitas kehidupan sosial masyarakat multietnis di Makassar. Ketika “serangan” Covid-19 terjadi, ruang-ruang itu terpaksa harus dibatasi bahkan ditutup. Lantas bagaimana masyarakat Makassar menyikapinya? Bagaimana eksistensi ruang-ruang itu selama pandemi? Apakah berakibat fatal terhadap relasi yang telah susah sulit dibangun bersama dalam ruang-ruang itu? Dalam Wednesday Forum (18/9/24) Syamsul Asri, dosen ICRS UGM, mencoba mengartikulasikan realitas kedai kopi di Makassar dengan tema “Against Social Distancing: Chinese Coffee Houses as Redemptive Space in Makassar”.
Kedai Kopi: antara Ruang Nongkrong dan Artikulasi
Relasi antaretnis masyarakat Makassar memiliki dinamikanya sendiri. Secara historis, relasi antara etnis Tionghoa, Melayu, Bugis, Makassar serta relasi antara agama Konghucu, Kristen, dan Islam di Makassar sarat akan ingatan pahit masa lalu. Tragedi anti-Tionghoa di 1965 dan 1998 pada rezim Orde Baru serta peristiwa pembunuhan salah seorang warga Makassar oleh seorang pria keturunan Tionghoa di September 1997 silam menjadi memori kelam. Menurut Asri, kisah masa lalu ini belum usai sebab tiada permohonan maaf ataupun pemberian maaf dari pihak-pihak yang berkonflik. Relasi yang penuh sentimen tersebut membutuhkan sebuah “ruang penebusan”. Ruang itu, bagi Asri, terwujud dalam rupa kedai kopi.
Tiga kedai kopi pecinan yang menjadi tempat penelitian Asri adalah Tong San Café, Phoe Nam Café, dan Hai Hong Café. Di tengah persaingan dengan kedai kopi kekinian yang estetik, kedai kopi pecinan ini mempertahankan identitas ke-Tionghoa-an mereka dalam interior ruang. Kendati merupakan kedai kopi Tionghoa, mereka menjual kopi khas Toraja dan makanan yang diproduksi oleh warga muslim di sekitar kedai seperti jalangkote. Para pelanggan yang datang untuk nongkrong menikmati kopi dan penganan khas Makassar berasal dari berbagai latar belakang etnis dan agama. Narasi personal tentang relasi antara etnis Tionghoa dan Makassar ini pun tecermin dalam kesaksian hidup pemilik Phoe Nam Café. Ia mengaku bahwa dirinya telah menganggap orang Makassar sebagai saudaranya walau tak sedarah. Berpijak pada narasi tersebut, bagi Asri, relasi yang terjalin bukan sebatas praktik ekonomi, melainkan juga sebuah gestur saling memaafkan.
Kedai kopi pecinan menjadi sebuah ruang berharga. Ditinjau dari teori third space (Ray Oldenburg, 1989), ruang-ruang sosial di luar rumah (first space) dan tempat kerja (second space) berperan penting untuk membangun relasi sosial dalam komunitas. Kedai kopi menjadi ruang bertemu yang memungkinkan proses saling menebus kesalahan dan memaafkan terjadi. Penerimaan pemilik kedai kopi pecinan terhadap perempuan muslim yang menitipkan jualan makanan merupakan perwujudan ruang penebusan tersebut. Asri menggarisbawahi, hal tersebut berdampak positif bagi relasi yang dibangun oleh masyarakat antaretnis di Makassar.
Ruang Penebusan selama Pandemi
Ruang yang menjadi jantung keseimbangan relasi antaretnis ini menemui pergumulannya ketika berhadapan dengan pembatasan sosial. Selama pandemi, atas arahan pemerintah, ruang-ruang itu wajib tutup. Akibatnya, proses panjang “penebusan” tersebut terinterupsi. Pembatasan ini pun memunculkan beragam respons di masyarakat, sebagian besar bernada penolakan. Sejak negara mengumumkan aturan pembatasan sosial, masyarakat Makassar hanya menjalankannya selama tiga bulan.
Mengapa respons masyarakat Makassar sangat ambivalen terhadap aturan pemerintah? Meminjam perspektif galactic policy (Stanley J. Tambiah, 1976), Asri menjelaskan bahwa pusat kekuasaan, yaitu Jakarta, kehilangan kekuatan dan pengaruhnya di Makassar karena jaraknya yang jauh. Kekuatan itu menghilang karena dihadang oleh narasi konspirasi tentang keadaan semasa Covid-19 yang menurut masyarakat terlalu dilebih-lebihkan. Bagi mereka, angka kematian Covid-19 menjadi tinggi karena kaburnya penyebab kematian akibat Covid murni atau sekadar penyertaan. Salah satu pemilik kedai kopi yang menjadi responden menyatakan, “Jika Covid itu beneran ada, kita tidak akan mungkin akan membicarakan dan mempertanyakannya lagi.” Beberapa narasi ini menunjukkan bahwa masyarakat mencoba merasionalkan narasi konspirasi tersebut.
Uniknya, di tengah narasi konspirasi yang hadir, muncul pula narasi budaya passianakkang dan sipakatau yang telah terinternalisasi dalam masyarakat Bugis dan Makassar. Passianakkang artinya hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang kuat yang tercipta melalui garis perkawinan. Sedangkan sipakatau bermakna sikap saling memanusiakan manusia yang lain. Dengan adanya narasi pasianakkang dan sipakatau ini, terlihat jelas bahwa masyarakat Makassar sangat menjunjung tinggi ikatan sosial yang terbentuk dalam masyarakat baik secara individu maupun komunitas. Jalinan erat antarmasyarakat Makassar sebagai sebuah keluarga yang saling memanusiakan menjadi terputus karena adanya pembatasan sosial. Sesederhana perihal tidak saling berjumpa dan tidak saling mengenal karena menggunakan masker dilihat sebagai ancaman bagi eksistensi masyarakat Makassar. Narasi budaya ini pun melengkapi narasi konspirasi untuk menggugat pembatasan sosial. Hal ini, bagi Asri, dapat dipahami sebagai sebuah cara masyarakat multietnis di Makassar untuk terus mempertahankan ruang “penebusan” yang telah menjadi media artikulasi luka dan memori-memori masa lalu.
______________________
Sonia Putri Ana Awa Matalu adalah mahasiswa Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS), Sekolah Pascasarjana UGM, angkatan 2024. Baca tulisan Puma lainnya di sini.
Foto tajuk artikel: Ariani/Celebesmedia.id (2018)
Artikel ini merupakan salah satu usaha CRCS UGM untuk mendukung SDGs nomor 16 tentang Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh.