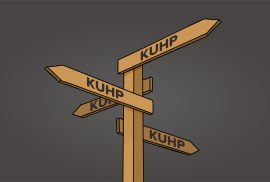Di mata pihak-pihak intoleran, teks-teks hukum “yang tidak jelas” dapat diterjemahkan secara intoleran juga.
Pemerintah dengan percaya diri menyatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang disahkan 2023 silam memberikan jaminan kehidupan beragama atau berkeyakinan (KBB) yang lebih baik. Pasal 300–305 KUHP 2023 yang bertajuk Tindak Pidana terhadap Agama, Kepercayaan, dan Kehidupan Beragama atau Kepercayaan secara khusus mengatur delik keagamaan. Namun, pasal-pasal tersebut rupanya berpotensi kuat menjadi “pasal karet” yang rentan untuk ditafsirkan menurut kepentingan pihak-pihak intoleran. Jika demikian, perlindungan terhadap masyarakat yang berasal dari kelompok-kelompok rentan keagamaan akan makin terciderai.